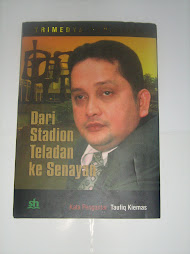Oleh : Tri Agus S Siswowiharjo*
Saat memberi pengarahan pada Rapim TNI dan Rakor Polri di Istana Negara (29/1) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, “Saya mendengar informasi ada seorang petinggi TNI-AD yang mengatakan ABS (asal bukan calon presiden berinisial S).” Pernyataan presiden yang kemudian tak dipercayai sendiri itu tetap saja mengundang pertanyaan, mengapa rumor yang belum jelas kebenarannya, itu disampaikan pada pertemuan resmi? Sejauh mana rumor dan humor merebak menjelang Pemilu 2009?
SBY ingin agar TNI dan Polri tetap menjaga kenetralan pada pemilu. Namun, dengan memberi informasi yang ia sendiri tak percayai, ini sebenarnya adalah ‘tragedi’. Mengapa SBY tak memerintahkan aparatnya untuk menyelidiki rumor itu sebelum menyampaikan ke kalangan TNI dan Polri? Bukankah SBY, sebagai Panglima Tertinggi TNI mempunyai tangan-tangan yang mampu menjangkau dari Mabes Cilangkap sampai tingkat Koramil?
Sebelum rumor soal ABS, SBY dan Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri terlibat berbalas pantun, soal yoyo dan gangsing. Megawati menyerang pemerintah memperlakukan rakyat seperti yoyo dan dijawab pengurus Partai Demokrat, justru saat pemerintah Megawati rakyat diperlakukan seperti gangsing - hanya berputar di tempat tak kemana-mana “Adu yoyo” ini seolah melanjutkan episode saling menyindir pada Pemilu 2004. Saat itu, Taufiq Kiemas menyindir “jendral kekanak-kanakan”, dan SBY menuai untung, dari simpati publik.
Megawati juga pernah mengeritik kinerja pemerintah SBY seperti orang menari poco-poco. Gerakan poco-poco maju selangkah kemudian mundur dua langkah. Jadi tak ada maju-majunya. Menanggapi kritikan Megawati, Wapres Jusuf Kala mengatakan justru kinerja pemerintah SBY jauh lebih bagus. Pada pemerintahan Megawati, justru kinerjanya berputar-putar seperti orang menari dansa!
Sungguh, pemilu merupakan peristiwa serius paling lucu. Bayangkan betapa lucunya hari-hari ini kita diserbu oleh wajah-wajah di spanduk, poster, dan baliho para caleg yang tak kita kenal. Mereka semua gayanya hampir sama, seolah-olah berwibawa, religius dan peduli rakyat. Kita juga digelontor iklan di televisi di mana banyak calon presiden beriklan. Ada ketua partai mengeluarkan miliaran rupiah hanya untuk mengatakan, “hidup adalah perjuangan.” Ada juga presenter televisi mengiklankan diri sembari berteriak, “if there is a will, there is a way.” Tak ketinggalan, ada mantan tentara yang ‘tiba-tiba’ mengaku pejuang para petani dan pedagang tradisionil.
Mari sedikit menghibur diri, bahwa di balik keseriusan dan kekhawatiran KPU mempersiapan Pemilu 2009, ada kelucuan atau humor yang menyegarkan.
Wapres Jusuf Kalla selalu tampil spontan dan segar. Saat membuka sebuah acara di Universitas Indonesia Depok, JK menyatakan dirinya merasa seperti di rumah sendiri berada di lingkungan UI. Para mahasiswa dan dosen saling pandang, bukankah JK lulusan Universitas Hassanuddin Makassar bukan alumni UI? Rupanya yang membuat JK at home adalah jaket almamater UI yang berwarna kuning.
Masih tentang JK yang kali ini berkunjung ke IPB (bukan Institut Pak Beye). Terjadi pembicaraan antara Wapres dan Rektor IPB. Dengan percaya diri sang rektor membanggakan bahwa alumnus IPB tersebar dan hebat dalam berbagai bidang. “Alumnus kami hebat di berbagai berbagai profesi dari wartawan sampai presiden,” ujar rektor. Dengan santai JK menimpali, “Ya alumnus IPB hebat di mana-mana, kecuali bidang pertanian.”
Berikut cerita tentang Fadjroel Rachman, yang kekeh sumekeh mencalonkan diri menjadi presiden 2009-2014 melalui jalur independen. Meski begitu, Fadjroel cukup berkeringat berusaha menggolkan capres independen melalui yudicial review UU Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Karena perjuangan yang tak kenal lelah, para wartawan menjuluki Fadjroel punya partai baru namanya MK.
Lain Fadjroel lain pula Garin Nugroho yang mendukung Sri Sultan Hamengkubuwono X. Garin kini sibuk berkeliling nusantara mendampingi Sultan. Bukan dalam rangka membuat film Capres di Bawah Bantal, Opera Pemilu atau Sultan dan Sepotong Roti. Melainkan Garin adalah konsultan politik HB X yang telah mendeklarasikan diri sebagai capres. Sebagai konsultan, dikongkon-kongkon (disuruh) Sultan, Garin bangga dipanggil Ngarso Luar. Sedangkan HB X oleh rakyatnya dipanggil Ngarso Dalem.
Rumor dan humor adalah bagian dari komunikasi politik. Praktik komunikasi politik selalu mengikuti sistem politik yang berlaku. Di negara yang menganut sistem politik tertutup, komunikasi politik pada umumnya mengalir dari penguasa ke rakyat. Penerapan pendekatan ini memang bukan satu-satunya, namun yang dominan dilaksanakan adalah top down. Untuk mewujudkan paradigma tersebut, pendekatan komunikasi politik terhadap media massa bersifat transmisional.
Kini, di era reformasi, komunikasi politik antara elite legislatif, eksekutif, dan yudikatif relatif seimbang. Muatan pesan politik yang disampaikan pada umumnya untuk mewujudkan kepentingan elite sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat. Jadi, meski sistem politik berubah dari sistem tertutup ke sistem terbuka, namun pendekatan komunikasi politik cenderung tidak berubah. Karena itu rumor dan humor masih muncul melengkapi komunikasi politik.
Mantan Presiden Abdurrahman Wahid pernah menulis kolom di majalah Tempo edisi Desember 1981 yang kemudian dijadikan judul buku kumpulan kolomnya, “Melawan Melalui Humor” (PDAT Tempo, 2000). Menurut Gus Dur, lelucon merupakan wahana ekspresi politis yang menyatukan bahasa rakyat dan mampu mengidentifikasikan masalah-masalah yang dikeluhkan dan diresahkan. Selain itu, lelucon juga memiliki kemampuan menggalang “musuh bersama”. Karena itu, fungsi perlawanan kulturalnya menunjuk kepada kesadaran yang tinggi untuk menyatakan apa yang benar sebagai kewajiban tak terelakkan.
Jika mengacu pendapat Gus Dur, masyarakat akan membuat lelucon dengan tokoh yang paling dibenci. Pada Orde Baru mantan Presiden Soeharto paling sering dihumorkan. Kini ketika otoritarianisme sudah tak ada, mereka yang dirumorkan dan dihumorkan adalah pejabat pemerintah atau pejabat publik yang tak pro rakyat atau ingkar janji. Mereka bisa anggota DPR, gubernur, bupati, walikota, menteri, sampai presiden.
Kata orang bijak, seseorang bisa disebut waras, lebih pintar dan lebih maju jika sudah bisa menertawakan sikap dan perbuatannya masa lalu. Bangsa Indonesia jika mau disebut dewasa, tentu harus mampu menertawakan kekonyolan pemilu!
Mahasiswa Pascasarjana Magister Manajemen Komunikasi Politik, Universitas Indonesia
Sabtu, 07 Februari 2009
Yoyo, Gangsing dan Kampanye Negatif
Oleh : Tri Agus S Siswowiharjo*
Berbalas iklan politik mulai memanas menjelang Pemilu 2009. Iklan Partai Demokrat yang mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menurunkan harga BBM tiga kali, dibalas oleh iklan serupa oleh PDI Perjuangan. Megawati Soekarnoputri bahkan menyerang pemerintah memperlakukan rakyat seperti yoyo, dan dijawab pengurus Partai Demokrat, justru pada saat pemerintah Megawati rakyat diperlakukan seperti gangsir - hanya berputar di tempat tak kemana-mana (Tempo, 30 Januari 2009). Kampanye negatif, saling menyerang, kini mulai akrab bagi kita, melalui tayangan di televisi maupun di media cetak. Bermanfaatkah kampanye negatif bagi masyarakat yang hendak memilih?
Sesungguhnya tak ada definisi yang diterima secara universal tentang iklan negatif. Namun pada dasarnya ia lebih berfokus terhadap pesaing daripada terhadap kandidat. Ini berarti, iklan negatif berkonsentrasi pada apa yang salah pada pesaing, baik secara personal atau dalam hal sikap terhadap isu atau kebijakan. Kendati banyak ahli sepakat bahwa iklan negatif adalah tidak etis, namun ada banyak peneliti berpendapat bahwa iklan negatif justru menyajikan kepada pemilih informasi yang baik dan solid sebagai dasar pengambil keputusan. Karena itu tak salah jika para konsultan politik sering menamakan iklan negatif sebagai “comparative” atau “contrast” yang membantu pemilih menilai kekuatan dan kelemahan para kandidat.
Menurut pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Dedy Nur Hidayat, kalau hanya berbalas pantun, sama sekali tidak mendidik. Harusnya adu argumentasi agar publik mengetahui alasan masing-masing pihak. Bagi Dedy, iklan Megawati sudah masuk kategori kampanye negatif, saling menyerang. Satu kandidat menawarkan suatu program kemudian dibalas oleh kandidat yang lain. Memang itu seharusnya, agar rakyat bisa memilih. Kalau hanya sebatas iklan politik, sama sekali tidak mendidik. Karena tidak terjadi proses pendidikan politik, tidak meningkatkan kualitas pemilih. Mungkin masyarakat akan memilih hanya karena image yang mereka tampilkan, tapi mereka tidak melakukan pilihan berdasarkan argumentasi yang rasional dan yang bisa diterima.
Kampanye negatif juga tak terhindarkan pada pilpres 2004. Menjelang dan selama kampanye capres 2004, media tiba-tiba mendapat isu menarik tentang Wiranto dan keterlibatannya dalam Pam Swakarsa. Organisasi ini didirikan untuk membantu mengamankan Sidang Umum MPR 1998, khususnya untuk menghadapi demonstrasi mahasiswa. Media sangat antusias menangkap isu yang dilontarkan Mayor Jendral Kivlan Zen, yang diketahui sebagai mantan koordinator pembentukan Pam Swakarsa. Kivlan Zen yang kecewa karena uang pembentukan Pam Swakarsa belum dibayar Wiranto, saat itu Panglima TNI, ternyata dekat dengan Prabowo Subianto, rival Wiranto di Angkatan Darat dan konvensi Partai Golkar. Kiprah Kivlan Zen ini ditengarai sebagai kampanye negatif melalui media untuk menyudutkan Wiranto.
Usai persoalan Pam Swakarsa, Wiranto kembali ‘diserang’ dengan beredarnya VCD anti-Wiranto bersampul pagelaran Akademi Fantasi Indosiar (AFI). Dalam VCD itu mulanya delapan menit lagu Menuju Bintang yang dinyanyikan Fery, juara AFI. Setelah itu muncul gambar tragedi Semanggi dan Trisakti dan wajah Wiranto. Disusul kemudian teks berjalan dengan kalimat “Adili Jendral (purn) Wiranto. Tolak Capres dari militer” “Anda ingin peristiwa Semanggi dan Trisakti terulang kembali? Jika iya maka: pilih SBY atau Wiranto sebagai presiden kita. Dijamin Indonesia banjir darah.”
Partai Hanura pernah memasang iklan politik dengan Wiranto sebagai bintang iklannya. Dalam iklan itu dicantumkan jumlah rakyat miskin Indonesia 49,5 persen. Wiranto mengaku tak bermaksud mendiskriditkan pihak mana pun. “Iklan itu adalah ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan,” ujar Wiranto (Kompas, 21/12/2007). Iklan itu menjadi polemik menarik. Dari soal data yang digunakan sampai dugaan upaya kampanye negatif menyerang pemerintah. Presdien SBY beralasan, perhitungan yang benar menggunakan data BPS 2007, di mana orang miskin 16,5 persen.
Kampanye negatif pada Pilpres di Amerika Serikat 2008 juga marak terjadi. Salah satu yang terkenal adalah iklan Partai Republik, di mana Barack Obama, diperlihatkan di depan ratusan ribu penggemarnya saat berceramah di Berlin, Jerman. Foto menggiurkan Britney Spears dan Paris Hilton diselipkan dalam film singkat itu, seolah mereka hadir di Berlin. Lalu ada suara menimpa, bertanya dengan nada menakutkan, ”Dia selebriti terbesar di dunia, tetapi apakah dia siap memimpin?” Tim kampanye Obama juga membuat iklan yang menyerang McCain. Digambarkan McCain yang kaya raya memiliki tujuh rumah, karena itu tak layak menempati rumah baru berikutnya, White House di Washington.
Berguna bagi publik?
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Gazali dalam diskusi "Dengan Iklan Politik Menuju Kontrak Politik" di Jakarta, (19/11/2008), mengungkapkan dua hingga tiga bulan terakhir sebelum 2009 model dan muatan iklan politik sebatas perkenalan, belum menyerang (attacking), atau membandingkan (contrasting) . "Mungkin, sekitar Januari baru akan terlihat kampanye yang bersifat menyerang. Perkenalan ke arah kontrak politik sudah, misalnya Gerindra yang sudah melangkah dari branding," ujarnya. Apa yang diramalkan Effendi Gazali terbukti, kini iklan politik saling menyerang hadir di sekitar kita. Meski demikian, lanjut Effendi Gazali, kampanye negatif tak perlu dicemaskan, bahkan wajib kehadirannya. Karena, tujuan akhir dari komunikasi politik adalah well informed citizen.
Di tengah meningkatnya iklan politik, praktisi periklanan dan media dituntut untuk taat kepada etika moral dan tanggungjawab profesi. Mereka harus berani memilah dan memilih materi iklan yang mencerdaskan bukan mencederai akal sehat pemilih. Menyerang pesaing mungkin bisa dibenarkan dan akan berguna bagi calon pemilih asal dengan argumentasi yang masuk akal. Semua akan terpulang kepada pemilih yang makin cerdas menentukan mana iklan politik mencerahkan atau hanya dialamatkan kepada perasaan, menyederhanakan persoalan karena keterbatasan waktu dan dana, menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui publik, sampai memakai manipulasi teknologi.
Dengan demikian, iklan negatif, sejauh mempunyai argumentasi yang tepat, faktual dan cerdas, sebenarnya bisa bermanfaat bagi calon pemilih. Karena pemilih butuh pembanding untuk menilai kekuatan dan kelemahan kandidat. Iklan negatif membantu kita memilah dan memilih calon pemimpin. Kita menjadi mengerti siapa yang sebenarnya yoyo dan siapa yang sejatinya gangsing. Kualitas pemimpin juga makin terkuak melalui iklan yang saling menyerang. Pendek kata, kampanye negatif, menjadikan publik well informed citizen.
Mahasiswa Pascasarjana Magister Manajemen Komunikasi Politik, Universitas Indonesia
Berbalas iklan politik mulai memanas menjelang Pemilu 2009. Iklan Partai Demokrat yang mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menurunkan harga BBM tiga kali, dibalas oleh iklan serupa oleh PDI Perjuangan. Megawati Soekarnoputri bahkan menyerang pemerintah memperlakukan rakyat seperti yoyo, dan dijawab pengurus Partai Demokrat, justru pada saat pemerintah Megawati rakyat diperlakukan seperti gangsir - hanya berputar di tempat tak kemana-mana (Tempo, 30 Januari 2009). Kampanye negatif, saling menyerang, kini mulai akrab bagi kita, melalui tayangan di televisi maupun di media cetak. Bermanfaatkah kampanye negatif bagi masyarakat yang hendak memilih?
Sesungguhnya tak ada definisi yang diterima secara universal tentang iklan negatif. Namun pada dasarnya ia lebih berfokus terhadap pesaing daripada terhadap kandidat. Ini berarti, iklan negatif berkonsentrasi pada apa yang salah pada pesaing, baik secara personal atau dalam hal sikap terhadap isu atau kebijakan. Kendati banyak ahli sepakat bahwa iklan negatif adalah tidak etis, namun ada banyak peneliti berpendapat bahwa iklan negatif justru menyajikan kepada pemilih informasi yang baik dan solid sebagai dasar pengambil keputusan. Karena itu tak salah jika para konsultan politik sering menamakan iklan negatif sebagai “comparative” atau “contrast” yang membantu pemilih menilai kekuatan dan kelemahan para kandidat.
Menurut pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Dedy Nur Hidayat, kalau hanya berbalas pantun, sama sekali tidak mendidik. Harusnya adu argumentasi agar publik mengetahui alasan masing-masing pihak. Bagi Dedy, iklan Megawati sudah masuk kategori kampanye negatif, saling menyerang. Satu kandidat menawarkan suatu program kemudian dibalas oleh kandidat yang lain. Memang itu seharusnya, agar rakyat bisa memilih. Kalau hanya sebatas iklan politik, sama sekali tidak mendidik. Karena tidak terjadi proses pendidikan politik, tidak meningkatkan kualitas pemilih. Mungkin masyarakat akan memilih hanya karena image yang mereka tampilkan, tapi mereka tidak melakukan pilihan berdasarkan argumentasi yang rasional dan yang bisa diterima.
Kampanye negatif juga tak terhindarkan pada pilpres 2004. Menjelang dan selama kampanye capres 2004, media tiba-tiba mendapat isu menarik tentang Wiranto dan keterlibatannya dalam Pam Swakarsa. Organisasi ini didirikan untuk membantu mengamankan Sidang Umum MPR 1998, khususnya untuk menghadapi demonstrasi mahasiswa. Media sangat antusias menangkap isu yang dilontarkan Mayor Jendral Kivlan Zen, yang diketahui sebagai mantan koordinator pembentukan Pam Swakarsa. Kivlan Zen yang kecewa karena uang pembentukan Pam Swakarsa belum dibayar Wiranto, saat itu Panglima TNI, ternyata dekat dengan Prabowo Subianto, rival Wiranto di Angkatan Darat dan konvensi Partai Golkar. Kiprah Kivlan Zen ini ditengarai sebagai kampanye negatif melalui media untuk menyudutkan Wiranto.
Usai persoalan Pam Swakarsa, Wiranto kembali ‘diserang’ dengan beredarnya VCD anti-Wiranto bersampul pagelaran Akademi Fantasi Indosiar (AFI). Dalam VCD itu mulanya delapan menit lagu Menuju Bintang yang dinyanyikan Fery, juara AFI. Setelah itu muncul gambar tragedi Semanggi dan Trisakti dan wajah Wiranto. Disusul kemudian teks berjalan dengan kalimat “Adili Jendral (purn) Wiranto. Tolak Capres dari militer” “Anda ingin peristiwa Semanggi dan Trisakti terulang kembali? Jika iya maka: pilih SBY atau Wiranto sebagai presiden kita. Dijamin Indonesia banjir darah.”
Partai Hanura pernah memasang iklan politik dengan Wiranto sebagai bintang iklannya. Dalam iklan itu dicantumkan jumlah rakyat miskin Indonesia 49,5 persen. Wiranto mengaku tak bermaksud mendiskriditkan pihak mana pun. “Iklan itu adalah ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan,” ujar Wiranto (Kompas, 21/12/2007). Iklan itu menjadi polemik menarik. Dari soal data yang digunakan sampai dugaan upaya kampanye negatif menyerang pemerintah. Presdien SBY beralasan, perhitungan yang benar menggunakan data BPS 2007, di mana orang miskin 16,5 persen.
Kampanye negatif pada Pilpres di Amerika Serikat 2008 juga marak terjadi. Salah satu yang terkenal adalah iklan Partai Republik, di mana Barack Obama, diperlihatkan di depan ratusan ribu penggemarnya saat berceramah di Berlin, Jerman. Foto menggiurkan Britney Spears dan Paris Hilton diselipkan dalam film singkat itu, seolah mereka hadir di Berlin. Lalu ada suara menimpa, bertanya dengan nada menakutkan, ”Dia selebriti terbesar di dunia, tetapi apakah dia siap memimpin?” Tim kampanye Obama juga membuat iklan yang menyerang McCain. Digambarkan McCain yang kaya raya memiliki tujuh rumah, karena itu tak layak menempati rumah baru berikutnya, White House di Washington.
Berguna bagi publik?
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Gazali dalam diskusi "Dengan Iklan Politik Menuju Kontrak Politik" di Jakarta, (19/11/2008), mengungkapkan dua hingga tiga bulan terakhir sebelum 2009 model dan muatan iklan politik sebatas perkenalan, belum menyerang (attacking), atau membandingkan (contrasting) . "Mungkin, sekitar Januari baru akan terlihat kampanye yang bersifat menyerang. Perkenalan ke arah kontrak politik sudah, misalnya Gerindra yang sudah melangkah dari branding," ujarnya. Apa yang diramalkan Effendi Gazali terbukti, kini iklan politik saling menyerang hadir di sekitar kita. Meski demikian, lanjut Effendi Gazali, kampanye negatif tak perlu dicemaskan, bahkan wajib kehadirannya. Karena, tujuan akhir dari komunikasi politik adalah well informed citizen.
Di tengah meningkatnya iklan politik, praktisi periklanan dan media dituntut untuk taat kepada etika moral dan tanggungjawab profesi. Mereka harus berani memilah dan memilih materi iklan yang mencerdaskan bukan mencederai akal sehat pemilih. Menyerang pesaing mungkin bisa dibenarkan dan akan berguna bagi calon pemilih asal dengan argumentasi yang masuk akal. Semua akan terpulang kepada pemilih yang makin cerdas menentukan mana iklan politik mencerahkan atau hanya dialamatkan kepada perasaan, menyederhanakan persoalan karena keterbatasan waktu dan dana, menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui publik, sampai memakai manipulasi teknologi.
Dengan demikian, iklan negatif, sejauh mempunyai argumentasi yang tepat, faktual dan cerdas, sebenarnya bisa bermanfaat bagi calon pemilih. Karena pemilih butuh pembanding untuk menilai kekuatan dan kelemahan kandidat. Iklan negatif membantu kita memilah dan memilih calon pemimpin. Kita menjadi mengerti siapa yang sebenarnya yoyo dan siapa yang sejatinya gangsing. Kualitas pemimpin juga makin terkuak melalui iklan yang saling menyerang. Pendek kata, kampanye negatif, menjadikan publik well informed citizen.
Mahasiswa Pascasarjana Magister Manajemen Komunikasi Politik, Universitas Indonesia
Lembaga Survei, Bersatulah!
Oleh: Tri Agus S. Siswowiharjo *)
Salah satu fenomena dalam politik kita lima tahun terakhir ini adalah munculnya lembaga survei, sekaligus produk perhitungan cepat (quick count) pada Pemilu 2004 dan Pilkada-pilkada setelah itu. Jumlah lembaga survei di Indonesia memang baru belasan, tak sebanyak di negara demokrasi baru seperti Philippina atau Korea Selatan yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Sebagai pemain baru, banyak pihak belum memahami peran lembaga survei, termasuk penyelenggara pemilu, dan sebagian ketua partai politik.
Jika tak ada perubahan, pada 24-25 Januari 2009, sejumlah lembaga survei di Indonesia akan bertemu, bermusyawarah, dan kemungkinan membentuk asosiasi. Asosiasi lembaga survei kehadirannya sangat ditunggu karena melalui asosiasi itu kode etik bisa dibuat dan kemudian ditaati para anggotanya. Jika ada lembaga survei yang ‘nakal’ maka lembaga ini bisa ‘menjewer’.
Kehadiran lembaga survei adalah keharusan bagi negara demokrasi. Studi tentang pendapat umum di Amerika Serikat (AS) telah mengalami perkembangan pesat sejak 1950-an, terutama untuk mengetahui sikap dan preferensi politik masyarakat umum. Pada era 1970-an, metode ini kian populer untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan publik terhadap pendapat umum atau sebaliknya, bagaimana pendapat umum memengaruhi kebijakan publik. Di AS misalnya ada lembaga-lembaga yang sangat terkenal seperti Gallup Poll, Harris Poll, Roper, Crosley Poll, Pew Research Center, dan Rasmussen
Fenomena perhitungan cepat yang dilakukan lembaga survei pada Pemilu 2004 membuka mata kita tentang salah satu pemain baru dalam demokrasi. Hadirnya sekitar 13 lembaga survei – belum termasuk litbang media – cukup meramaikan dan menambah bobot demokrasi di tanah air. Betapa tidak, kini hampir tiap bulan kita dapat mengetahui opini masyarakat mengenai isu-isu yang menyangkut ekonomi, politik, dan sosial. Lembaga survei silih berganti mengadakan konperensi pers, mengumumkan hasil survei tentang berbagai isu, termasuk yang paling ‘seksi’ yaitu soal partai politik atau calon presiden pilihan masyarakat. Namun, seperti pers yang muncul bak jamur di musim reformasi, lembaga survei juga sama. Akan ada seleksi alam, dan hanya yang kompeten dan punya integritas yang akan bertahan.
Persoalan yang muncul kemudian adalah adanya suara-suara ketidakpuasan dari tokoh partai politik atau calon presiden yang menurut survei popularitasnya tak pernah naik. Mereka kesal, lalu menuduh ada lembaga survei bayaran, yang hasilnya bisa dipesan. Selain itu, ada upaya dari KPU untuk mengatur atau membatasi lembaga survei dengan berbagai ketentuan. Sungguh ini kabar buruk bagi lembaga survei sekaligus bagi masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari dan mendapatkan informasi. Ada satu atau dua institusi survei yang nakal, lalu coba mengatur dan mengebiri semua lembaga survei. Memang harus diakui, ada institusi survei yang tak memiliki kompetensi, dan lebih buruk lagi, tak mempunyai integritas. Institusi survei yang terakhir ini biasanya membuat survei untuk memberi kepuasan pemesan, dan diumumkan ke publik.
Menurut Hasan Hasbi dari Cirus Surveyors Group, hasil survei dapat menjadi pintu masuk untuk bisnis yang lebih besar, yaitu konsultan politik. Selalu ada godaan untuk menghibur klien, (Kompas, 16/1/09). Selain itu, KPU yang berencana mengatur lembaga survei, bisa dimaknai dua hal. Pertama, KPU menganggap dirinya bak superbody, ingin mengatur semua hal termasuk di luar kewenangan dan kompetensinya. Kedua, KPU ingin mengalihkan perhatian publik dari kelemahan dan kelambatan mereka mempersiapkan Pemilu 2009.
Jika pers telah lama diakui sebagai pilar keempat demokrasi, menurut M Qodari, direktur Indo Barometer, lembaga survei adalah pilar kelima demokrasi. Survey opini publik membantu mendekatkan keputusan-keputusan publik dengan aspirasi publik, dan elit mengetahui keputusan-keputusan yang kurang populer tetapi harus dibuat sehingga perlu dijelaskan kepada publik secara luas. Dengan demikian, pemerintah demokratis akan menjadi semakin legitimate, stabil, bertanggungjawab dan efektif. Survei opini publik menjadi ‘barometer’ aspirasi masyarakat, dan pembuat kebijakan. Tidak perlu menunggu pemilu lima tahun lagi atau referendum untuk mengetahui pendapat masyarakat.
Perselingkuhan Lembaga Survei dan Konsultan Politik
Selain munculnya lembaga pengumpul jajak pendapat, marak pula kehadiran konsultan politik. Seorang konsultan politik adalah seorang profesional kampanye yang terlibat dalam pemberian nasihat dan jasa-jasa kepada para kontestan pemilu, baik berupa jajak pendapat, produksi, dan penciptaan media. Di sinilah kadang konflik interes terjadi, bisa seorang pollster sekaligus konsultan politik.
Fenomena konsultan politik seperti di AS ini juga telah merambah ke tanah air, terutama sejak diterapkannya sistem pemilihan presiden secara langsung pada 2004. Setelah itu, sejak 2005 ketika pemilihan kepala daerah juga dilakukan secara langsung, ‘industri’ tim sukses dan survei ini kian marak.
Konsultan politik harus bersikap profesional dan bersikap jujur tentang aneka kelemahan dari survei yang dilakukan atau dilakukan pihak lain. Mereka juga harus mau bersikap jujur untuk memberitahukan siapa yang mensponsorisurvei dan jajak pendapat yang mereka lakukan. Di AS misalnya, salah satu kode etik yang disepakati melalui Asosiasi Amerika untuk Penelitian Pendapat Publik (American Association for Public Opinion Reserarch) telah mencantumkan keharusan bagi lembaga yang melakukan penelitian pendapat publik. Konsultan politik yang profesional adalah yang mampu mengantarkan kliennya ke tujuan dengan cara-cara yang cerdas, bermartabat, dan efisien.
Dalam setahun terakhir ini banyak survei politik dilakukan lembaga survei yang sudah dikenal masyarakat seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Indo Barometer, Cirus Surveyors Group, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Reform Institute, Paskalis UI, Lembaga Riset Informasi, dan lain-lain.
Uniknya, kedua LSI dan Indo Barometer dahulu berasal dari satu institusi yang sama di bawah Denny JA, yaitu Lembaga Survei Indonesia. Dalam perjalanannya, Syaiful Mujani mengundurkan diri dari LSI dan membentuk LSI baru dengan nama yang sama yaitu Lembaga Survei Indonesia, sedangkan Denny JA dan M. Qodari tetap di LSI dengan nama baru Lingkaran Survei Indonesia, baru kemudian M. Qodari pecah kongsi dengan Denny J.A dan kemudian membentuk Indo Barometer.
LSI Syaiful Mujani dan Indo Barometer M Qodari tampaknya memilih di jalur yang memisahkan antara pollster dengan konsultan politik. Hal itu diyakini akan lebih menghasilkan survei yang akurat, kredibel, dan independen. Sementara Denny J.A berpendapat lain. Sah-sah saja bila lembaga survei bergerak sekaligus konsultan politik partai, kandidat presiden atau berbagai kandidat dalam pilkada. Di AS pun, ujar Denny J A, sejak 1970-an konsultan politik yang sekaligus melakukan survei tumbuh bak jamur di musim hujan, yang berdampak negatif bagi fungsi mesin partai karena digantikan para konsultan politik profesional.
Demi profesionalitas, maka integritas dan kompetensi sebuah lembaga survei harus diutamakan. Independensi juga sangat penting. Karena itu, memisahkan antara pekerjaan pollster dengan konsultan politik adalah sebuah keharusan. Namun karena belum ada asosiasi lembaga survei, perselingkuhan antara pollster dan konsultan politik terus berlangsung. Asosiasi lembaga survei sangat perlu segera dibentuk. Di sanalah diatur kode etik profesi - seperti profesi wartawan, dokter, dan pengacara. Kita berharap kehadiran asosiasi akan memantapkan lembaga survei sebagai pilar kelima demokrasi yang kompeten, kredibel, independen, dan mempunyai integritas. Karena itu, lembaga survei Indonesia, bersatulah!
*) penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Manajemen Komunikasi Politik, Universitas Indonesia
Alamat Surat: Apartemen Margonda Residence B 411
Jl. Margonda Raya, Depok Jawa Barat
HP: 0815 803 1815
Salah satu fenomena dalam politik kita lima tahun terakhir ini adalah munculnya lembaga survei, sekaligus produk perhitungan cepat (quick count) pada Pemilu 2004 dan Pilkada-pilkada setelah itu. Jumlah lembaga survei di Indonesia memang baru belasan, tak sebanyak di negara demokrasi baru seperti Philippina atau Korea Selatan yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Sebagai pemain baru, banyak pihak belum memahami peran lembaga survei, termasuk penyelenggara pemilu, dan sebagian ketua partai politik.
Jika tak ada perubahan, pada 24-25 Januari 2009, sejumlah lembaga survei di Indonesia akan bertemu, bermusyawarah, dan kemungkinan membentuk asosiasi. Asosiasi lembaga survei kehadirannya sangat ditunggu karena melalui asosiasi itu kode etik bisa dibuat dan kemudian ditaati para anggotanya. Jika ada lembaga survei yang ‘nakal’ maka lembaga ini bisa ‘menjewer’.
Kehadiran lembaga survei adalah keharusan bagi negara demokrasi. Studi tentang pendapat umum di Amerika Serikat (AS) telah mengalami perkembangan pesat sejak 1950-an, terutama untuk mengetahui sikap dan preferensi politik masyarakat umum. Pada era 1970-an, metode ini kian populer untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan publik terhadap pendapat umum atau sebaliknya, bagaimana pendapat umum memengaruhi kebijakan publik. Di AS misalnya ada lembaga-lembaga yang sangat terkenal seperti Gallup Poll, Harris Poll, Roper, Crosley Poll, Pew Research Center, dan Rasmussen
Fenomena perhitungan cepat yang dilakukan lembaga survei pada Pemilu 2004 membuka mata kita tentang salah satu pemain baru dalam demokrasi. Hadirnya sekitar 13 lembaga survei – belum termasuk litbang media – cukup meramaikan dan menambah bobot demokrasi di tanah air. Betapa tidak, kini hampir tiap bulan kita dapat mengetahui opini masyarakat mengenai isu-isu yang menyangkut ekonomi, politik, dan sosial. Lembaga survei silih berganti mengadakan konperensi pers, mengumumkan hasil survei tentang berbagai isu, termasuk yang paling ‘seksi’ yaitu soal partai politik atau calon presiden pilihan masyarakat. Namun, seperti pers yang muncul bak jamur di musim reformasi, lembaga survei juga sama. Akan ada seleksi alam, dan hanya yang kompeten dan punya integritas yang akan bertahan.
Persoalan yang muncul kemudian adalah adanya suara-suara ketidakpuasan dari tokoh partai politik atau calon presiden yang menurut survei popularitasnya tak pernah naik. Mereka kesal, lalu menuduh ada lembaga survei bayaran, yang hasilnya bisa dipesan. Selain itu, ada upaya dari KPU untuk mengatur atau membatasi lembaga survei dengan berbagai ketentuan. Sungguh ini kabar buruk bagi lembaga survei sekaligus bagi masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari dan mendapatkan informasi. Ada satu atau dua institusi survei yang nakal, lalu coba mengatur dan mengebiri semua lembaga survei. Memang harus diakui, ada institusi survei yang tak memiliki kompetensi, dan lebih buruk lagi, tak mempunyai integritas. Institusi survei yang terakhir ini biasanya membuat survei untuk memberi kepuasan pemesan, dan diumumkan ke publik.
Menurut Hasan Hasbi dari Cirus Surveyors Group, hasil survei dapat menjadi pintu masuk untuk bisnis yang lebih besar, yaitu konsultan politik. Selalu ada godaan untuk menghibur klien, (Kompas, 16/1/09). Selain itu, KPU yang berencana mengatur lembaga survei, bisa dimaknai dua hal. Pertama, KPU menganggap dirinya bak superbody, ingin mengatur semua hal termasuk di luar kewenangan dan kompetensinya. Kedua, KPU ingin mengalihkan perhatian publik dari kelemahan dan kelambatan mereka mempersiapkan Pemilu 2009.
Jika pers telah lama diakui sebagai pilar keempat demokrasi, menurut M Qodari, direktur Indo Barometer, lembaga survei adalah pilar kelima demokrasi. Survey opini publik membantu mendekatkan keputusan-keputusan publik dengan aspirasi publik, dan elit mengetahui keputusan-keputusan yang kurang populer tetapi harus dibuat sehingga perlu dijelaskan kepada publik secara luas. Dengan demikian, pemerintah demokratis akan menjadi semakin legitimate, stabil, bertanggungjawab dan efektif. Survei opini publik menjadi ‘barometer’ aspirasi masyarakat, dan pembuat kebijakan. Tidak perlu menunggu pemilu lima tahun lagi atau referendum untuk mengetahui pendapat masyarakat.
Perselingkuhan Lembaga Survei dan Konsultan Politik
Selain munculnya lembaga pengumpul jajak pendapat, marak pula kehadiran konsultan politik. Seorang konsultan politik adalah seorang profesional kampanye yang terlibat dalam pemberian nasihat dan jasa-jasa kepada para kontestan pemilu, baik berupa jajak pendapat, produksi, dan penciptaan media. Di sinilah kadang konflik interes terjadi, bisa seorang pollster sekaligus konsultan politik.
Fenomena konsultan politik seperti di AS ini juga telah merambah ke tanah air, terutama sejak diterapkannya sistem pemilihan presiden secara langsung pada 2004. Setelah itu, sejak 2005 ketika pemilihan kepala daerah juga dilakukan secara langsung, ‘industri’ tim sukses dan survei ini kian marak.
Konsultan politik harus bersikap profesional dan bersikap jujur tentang aneka kelemahan dari survei yang dilakukan atau dilakukan pihak lain. Mereka juga harus mau bersikap jujur untuk memberitahukan siapa yang mensponsorisurvei dan jajak pendapat yang mereka lakukan. Di AS misalnya, salah satu kode etik yang disepakati melalui Asosiasi Amerika untuk Penelitian Pendapat Publik (American Association for Public Opinion Reserarch) telah mencantumkan keharusan bagi lembaga yang melakukan penelitian pendapat publik. Konsultan politik yang profesional adalah yang mampu mengantarkan kliennya ke tujuan dengan cara-cara yang cerdas, bermartabat, dan efisien.
Dalam setahun terakhir ini banyak survei politik dilakukan lembaga survei yang sudah dikenal masyarakat seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Indo Barometer, Cirus Surveyors Group, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Reform Institute, Paskalis UI, Lembaga Riset Informasi, dan lain-lain.
Uniknya, kedua LSI dan Indo Barometer dahulu berasal dari satu institusi yang sama di bawah Denny JA, yaitu Lembaga Survei Indonesia. Dalam perjalanannya, Syaiful Mujani mengundurkan diri dari LSI dan membentuk LSI baru dengan nama yang sama yaitu Lembaga Survei Indonesia, sedangkan Denny JA dan M. Qodari tetap di LSI dengan nama baru Lingkaran Survei Indonesia, baru kemudian M. Qodari pecah kongsi dengan Denny J.A dan kemudian membentuk Indo Barometer.
LSI Syaiful Mujani dan Indo Barometer M Qodari tampaknya memilih di jalur yang memisahkan antara pollster dengan konsultan politik. Hal itu diyakini akan lebih menghasilkan survei yang akurat, kredibel, dan independen. Sementara Denny J.A berpendapat lain. Sah-sah saja bila lembaga survei bergerak sekaligus konsultan politik partai, kandidat presiden atau berbagai kandidat dalam pilkada. Di AS pun, ujar Denny J A, sejak 1970-an konsultan politik yang sekaligus melakukan survei tumbuh bak jamur di musim hujan, yang berdampak negatif bagi fungsi mesin partai karena digantikan para konsultan politik profesional.
Demi profesionalitas, maka integritas dan kompetensi sebuah lembaga survei harus diutamakan. Independensi juga sangat penting. Karena itu, memisahkan antara pekerjaan pollster dengan konsultan politik adalah sebuah keharusan. Namun karena belum ada asosiasi lembaga survei, perselingkuhan antara pollster dan konsultan politik terus berlangsung. Asosiasi lembaga survei sangat perlu segera dibentuk. Di sanalah diatur kode etik profesi - seperti profesi wartawan, dokter, dan pengacara. Kita berharap kehadiran asosiasi akan memantapkan lembaga survei sebagai pilar kelima demokrasi yang kompeten, kredibel, independen, dan mempunyai integritas. Karena itu, lembaga survei Indonesia, bersatulah!
*) penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Manajemen Komunikasi Politik, Universitas Indonesia
Alamat Surat: Apartemen Margonda Residence B 411
Jl. Margonda Raya, Depok Jawa Barat
HP: 0815 803 1815
Sabtu, 27 Desember 2008
Politisi dan Pers
Kasus Wartawan Menjadi Anggota DPR 2004-2009
Pendahuluan:
Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mendatang, ada sekitar 120 wartawan atau mantan wartawan di seluruh Indonesia ikut berkompetisi menjadi calon anggota legislatif. Ada wajah lama yang kembali mencalonkandiri atau dicalegkan parpol, seperti Cyprianus Aoer, Alfridel Djinu, Yoseph Umar Hadi, Panda Nababan dari PDI P, dan Effendy Chorie (PKB). Ada pula wajah-wajah baru yang mencoba menjadi politisi yang katanya sebagai panggilan seperti Helmi Fauzi dan Hamid Basyaib (PDI P), Bruno Kakawao (PKPI), Teguh Djuwarno (PAN), Mutia Hafild (Partai Golkar). Terdapat juga nama Manuel Kasiepo (PDI P). Dari kalangan kolumnis terdapat nama Zuhairi Misrawi (PDI P), Abdul Rohim Ghozali (PAN).
Munculnya wartawan sebagai caleg mendapat perhatian publik yang kurang lebih sama dengan kehadiran artis dan aktivis pada kontestasi Pemilu 2009. Wartawan, artis dan aktivis seolah dianggap sekelompok manusia yang kurang elok masuk dunia politik di parlemen yang penuh intrik. Wartawan seharusnya independen, artis sejatinya menghibur masyarakat, dan aktivis pantasnya berjuang secara imparsial dan tak mengharap kekuasaan. Itulah sorotan publik dengan kacamata yang kurang positif, yang pada intinya makhluk jenis wartawan, artis, dan aktivis tak pantas berada di lembaga legislatif.
Fenomena wartawan menjadi politikus bukanlah hal baru. Sejarah mencatat para jurnalis perintis menggunakan surat kabarnya sebagai bagian propaganda politik untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Pada masa kemerdekaan, kita melihat sejumlah surat kabar dan wartawan ikut dalam politik melawan rekolonialisasi sekutu. Pada periode 1950-1960-an, ada banyak wartawan menjadi anggota partai politik dan ada beberapa wartawan menjadi duta besar. BM Diah, misalnya, adalah salah satu dari sejumlah wartawan yang menjadi duta bangsa.
Semasa Orde Baru hingga Orde Reformasi kita mengenal sejumlah wartawan senior yang juga diangkat jadi duta besar, seperti Sabam Siagian (Australia), Djafar Assegaff (Vietnam), dan Susanto Pudjomartono (Rusia). Mantan Wakil Presiden Adam Malik dan mantan Menteri Penerangan dan Ketua DPR/MPR Harmoko juga adalah wartawan senior. Pada era reformasi, kian banyak wartawan masuk dunia politik dan beberapa menjadi anggota parlemen. Nama-nama seperti Hery Akhmadi, Cyprianus Aoer, Aco Manafe, Panda Nababan (PDI Perjuangan), Effendie Choirie (PKB), Djoko Susilo (PAN), Benny Harman (PKPI), Max Sopacoa (PD), Antoni Z Abidin, Bambang Sadono (Golkar) adalah sebagian dari sejumlah wartawan yang banting setir masuk dunia politik. Mereka adalah para anggota DPR RI periode 2004-2009.
Mengapa kehadiran wartawan di parlemen menarik perhatian? Hal itu tak lepas posisi wartawan sebagai bagian masyarakat media atau pers yang dalam negara demokrasi dianggap sebagai salah satu dari empat pilarnya. Pilar lain demokrasi adalah eksekutuf, yudikatif, dan legislatif. Menjadi wartawan sebagai penyampai berita dan pengritik pemerintah, sebenarnya sudah cukup, karena mereka telah menjalankan peran sebagai salah satu pilar demokrasi. Namun, toh tiap lima tahun sekali, sesuai periode pemilu di Indonesia, selalu ada migrasi profesi, dari wartawan ke poltitisi atau anggota parlemen.
Tilisan “Government and Media Relations” ini mengajukan sejumlah pertanyaan. Pertanyaan yang kemudian mengemuka, antara lain adalah 1) Mengapa sejumlah wartawan pindah profesi menjadi politikus di Senayan? 2) Apa kelebihan wartawan sehingga dianggap layak masuk ke dunia politik terutama menjadi anggota DPR? 3) Adakah peluang ‘menggiurkan’ atau ‘menantang’ dalam dunia politik yang membuat mereka pindah profesi? 4) Adakah kontribusi positif kepada demokrasi kita dari masuknya wartawan ke politik formal. 5) Bagaimana komunikasi politik wartawan anggota DPR dengan sesama anggota DPR, pemerintah, dan masyarakat? 6) Betulkah mereka telah memberikan perbedaan signifikan (dalam arti positif) dibandingkan profesi lain terhadap kinerja parlemen di masa lalu?
Agar pembahasan “Government and Media Relations” ini lebih fokus, maka yang kami dipilih sebagai obyek pengamatan, adalah para wartawan yang terjun menjadi anggota DPR periode 2004-2009. Mengapa periode 2004-2009? Karena anggota DPR periode ini tengah berjalan dan hampir selesai masa tugasnya, sehingga lebih mudah data yang akan kita peroleh untuk diteliti dan dianalisa.
2. Kerangka Teori:
Pers merupakan pilar keempat demokrasi (the fourth estate of democracy). Anggapan umum yang selama ini beredar di tengah-tengah masyarakat mengatakan demikian. Bahkan pernyataan "media merupakan kekuatan keempat setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif" telah menjadi aksioma politik, sebuah kebenaran cara berpikir politis yang tidak perlu dibantah lagi. Meski demikian, media atau pers tak hidup di ruang hampa. Ia berada dalam sebuah negara yang mempunyai sistem tertentu.
Dalam karyanya yang ditulis tiga dasa warsa lampau Fred Siebert dan rekan-rekan mengemukakan ada empat teori utama tentang hubungan antara pemerintah dan pers: 1) teori otoriter bahwa kekuasaan pemerintah harus dipusatkan pada satu orang atau elit, dan pers harus berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk memelihara ketertiban dan pemerintahan golongan elit; 2) teori libertarian yang berargumentasi bahwa pers harus berjalan dengan cara laissez faire, tidak dikekang, untuk menciptakan pluralisme titik pandang yang memberikan pengujian independen terhadap pemerintah dan peluang untuk menelaah semua opini secara bebas dan terbuka; 3) teori komunis yang melihat pers sebagai alat untuk menyampaikan kebijakan sosial untuk kepentingan ideologi dan tujuan yang diwakili oleh partai komunis; dan 4) teori pertanggungjawaban sosial yang menerima prinsip pers bebas, tetapi pers yang melaksanakan pelayanan masyarakat melalui kritik sosial dan pendidikan masyarakat yang bertanggungjawab, dengan anggapan bahwa jaminan atas pers bebas adalah jaminan kepada warga negara nasion, bukan yang pada dasarnya merupakan perlindungan atas hak pemilikan bagi pemilikan pers[1]
Teori pers libertarian paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia ini. Hal ini tak lepas dari kemenangan kapitalisme atas komunisme pascaperang dingin akhir 1980an. Sistem Pers Bebas menurut Walter Lippman[2] sesungguhnya merupakan ekspresi suatu kebenaran yang muncul dari cara “Free reporting” dan “Free discussion” dan sama sekali bukan dari apa yang disajikan secara sempurna dan instan yang diucapkan oleh seseorang. Pada sistem ini, pers layak disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Karena kebebasannya, pers mampu menjadi “wacthdog” pemerintah.
Kini, di tengah tekanan kapitalisasi dan iklim kebebasan, peran sentral pers dalam konteks demokrasi dan politik masih kokoh. Pers yang terletak pada dua entitas—organisasi pemberitaan (news organization) dan organisasi bisnis (business organization)—diharapkan mampu menyeimbangkan perannya sebagai pilar keempat demokrasi.
Menarik menyimak pemikiran yang diungkapkan oleh pakar media politik asal Amerika Serikat (AS), Timothy E Cook[3] (1998). Dia menyebut term media sebagai political actor (aktor politik) atau institusi politik. Cook berargumen bahwa media merupakan salah satu aktor atau institusi politik yang dapat menggunakan haknya sendiri secara independen, ”political actor / institution in its own right.” Selama ini ketika berbicara tentang media dan politik, kita kerap terjebak pada tataran komunikasi politik. Artinya, dalam perspektif ini media hanya dijadikan salah satu medium pasif bagi para spin doctor untuk menyampaikan pesan-pesan (kampanye) politik demi meraih kekuasaan.
Dalam sistem yang kini dianut Indonesia memungkinkan institusi media dan awak media menjadi sangat berperan dalam perubahan, dan karenanya sangat dikenal oleh masyarakat. Institusi media mungkin lebih dikenal publik daripada para wartawan yang tiap hari bekerja mengais berita. Interaksi antara partai politik dan media menjadikan dua pelaku demokrasi yang sama-sama mengklaim penyambung lidah masyarakat itu berinteraksi saling menghormati dan menguntungkan. Mereka saling mengagumi satu sama lain, meski terkadang saling mengritisi. Banyaknya anggota DPR yang terkuak skandalnya-- baik korupsi maupun perselingkuhan seks—tak lepas dari peran wartawan. Sebaliknya, banyak kejadian yang mungkin tak terungkap, meski bisa diungkap ke publik, karena para politisi mampu “membeli” atau “memelihara” wartawan. Simbiosis mutualisma atau perselingkuhan antara wartawan dan politisi ini tentu sangat [4]merugikan publik, baik sebagai konstituen partai politik, maupun pembaca media yang berhak untuk mendapatkan informasi.
Bill Kovach, kurator Nieman Foundation on Journalism, Universitas Harvard, salah satu guru wartawan yang paling dihormati dari Amerika Serikat, berpendapat mengenai makna informasi buat seorang politikus dan seorang wartawan. Kovach menutip Presiden Jimmy Carter (1975), "Ketika Anda memiliki kekuasaan, Anda menggunakan informasi untuk membuat orang mengikuti kepemimpinan Anda. Namun kalau Anda wartawan, Anda menggunakan informasi untuk membantu orang mengambil sikap mereka sendiri."[5]
Informasi yang sama dipakai untuk dua tujuan yang berbeda. Bahkan berlawanan. Inilah yang membuat Kovach mengambil sikap teguh untuk independen dari dunia politik maupun politisi. Kovach setia pada jurnalisme dan tak pernah mau menerima tawaran masuk ke dunia politik.
Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat. Sembilan elemen jurnalisme Kovack dan Tom Rosenstiel sangat terkenal di kalangan jurnalis. Delapan elemen lainnya adalah; kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran; intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi; praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita; jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan; jurnalisme harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat; jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting menarik dan relevan; jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional; dan praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka[6].
Loyalitas utama seorang wartawan adalah kepada warga masyarakat tempatnya berada. Wartawan bisa melayani warga dengan sebaik-baiknya apabila mereka bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput. Independen baik dari institusi pemerintah, bisnis, sosial maupun politik. Wartawan bahkan harus independen dari pemilik media tempatnya bekerja.
3. Pembahasan: Politisi Wartawan atau Wartawan Politisi?
Dalam buku “Wajah DPR dan DPD 2004-2009” terbitan PT. Kompas Media Nusantara (2006), terdapat sekitar 23 mantan waratawan[7]. Mereka berasal dari enam partai yaitu Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia. Di antara wartawan yang menjadi politisi Senayan 2004-2009, ada yang telah lama meninggalkan profesi wartawan, ada pula yang masih berstatus wartawan ketika migrasi menjadi politisi.
Wartawan termasuk warga negara biasa yang punya hak politik dan sering diharapkan ikut memimpin masyarakatnya. Mereka sah melakukannya. Cyprianus Aoer sangat memrihatinkan warga Flores karena kurang diperjuangkan di Jakarta. Tidakkah pilihan Aoer sah untuk terjun ke Parlemen?Bisa jadi alasan wartawan lainnya terjun ke parlemen berbeda. Ada yang seperti Aoer untuk memperjuangkan daerah asalnya, ada pula yang ingin memperjuangkan suatu isu tertentu misalnya pemberantasan korupsi atau transparansi pemerintahan.
Bagi Andreas Harsono[8], mantan wartawan The Jakarta Post yang kini mengelola Yayasan Pantau, suatu lembaga nirlaba untuk kemajuan jurnalisme, keterlibatan wartawan dalam politik memang kadang tak terhindarkan. Namun, sebaiknya diberlakukan sebagai one-way ticket. Artinya, seorang wartawan boleh menjadi politikus tetapi ia sebaiknya jangan kembali menjadi wartawan. Aoer boleh masuk parlemen tapi jangan kembali ke Suara Pembaruan. Djoko Susilo boleh menjadi politikus handan di Komisi I DPR namun jangan kembali ke Jawa Pos. Bila seorang wartawan masuk politik menjadi anggota DPR, ia akan mempunyai sikap yang berbeda terhadap informasi, sehingga lebih baik bila ia tak kembali ke media. Praktik bolak-balik ini akan menimbulkan citra kurang baik dari masyarakat tehadap media di Indonesia, apalagi pada masa demokratisasi sekarang ini, di mana warga butuh informasi yang bermutu untuk mengambil sikap terhadap berbagai isu penting di Indonesia.
Pandangan Andreas Harsono di atas memang sangat ideal. Namun bagi kalangan wartawan yang kini menduduki kursi empuk di Senayan, tentu tak semua menerima pendapat Andreas. Banyak alasan yang bisa dikemukakan mengapa seseorang melakukan ganti profesi dan kembali lagi ke pekerjaan semula. Ada yang memajukan alasan ingin melakukan perubahan dari dalam, sampai yang terus terang sekedar mencari jabatan. Wajar saja wartawan sebagai korps keempat pilar demokrasi tampil sebagai anggota legislatif karena peran atau profesi apa pun punya peran sosial kemasyarakatan. Yang penting wartawan sebagai anggota DPR tidak semata membawa ambisi politik, tetapi juga membawa tekad untuk membawa perubahan dan kesegaran baru[9].
Lain Andreas lain pula Arswendo Atmowiloto[10], wartawan sekaligus budayawan. Sebuah karya jurnalistik, kata Arswendo, baik tulisan maupun gambar pada derajat tertentu mampu menyodorkan informasi menjadi fakta yang menggugah publik. “Wartawan lebih powerful daripada anggota DPR,“ ujarnya. Wartawan, lanjut Arswendo, bisa menulis tentang banyak hal dan menggerakkan banyak orang untuk melihat realita sosial yang ada dan melakukan perubahan ke arah yang lebih positif. Hal ini yang belum mampu dilakukan bahkan oleh anggota DPR sekalipun. Karya-karya jurnalistik di Indonesia seharusnya dapat memotret realita sosial yang ada sehingga dapat memberikan dampak luas bagi masyarakat. Karya-karya jurnalistik yang lebih peka dan humanis akan membawa dampak sosial kepada masyarakat luas.
Sudah bagus berperan sebagai wartawan tetapi mengapa malah pindah profesi sebagai politisi? Adalah hak setiap warga untuk berpolitik dan berganti profesi. Apa kelebihan para jurnalis ini sehingga bisa masuk dunia politik? Betulkah kehadiran para mantan jurnalis ini memberi kontribusi positif bagi dunia politik partai saat ini? Ataukah ia akan ”larut dan hanyut” gelombang perpolitikan parlemen seperti banyak dikritik? Dunia kewartawanan dan politik dapat dikatakan merupakan dua hal yang jauh berbeda. Salah satu fungsi wartawan adalah melakukan kontrol terhadap pejabat publik dan politisi. Namun, kedua profesi yang bertolak belakang itu dapat dijalani dengan baik oleh orang yang tak mudah “larut dan hanyut”.
Dibandingkan profesi lain, wartawan dianggap memiliki kelebihan dalam melobi orang lain, terutama orang penting, termasuk pejabat publik. Sebagian wartawan juga dikenal pandai berargumentasi, lihai bersilat lidah, dan—ini tak kalah penting—kemudahan akses pada informasi dan media massa. Bagi sebagian wartawan itu, dunia politik adalah bagian kehidupan sehari-hari saat menjadi jurnalis. Bagi partai politik, mungkin wartawan dianggap bisa menjadi pasukan segar untuk bertarung tahun depan.
Apakah fenomena wartawan menjadi politikus tak lebih dari para pihak yang ingin masuk politik kekuasaan untuk kepentingan sendiri atau partainya? Ini mengingatkan kita pada Friedrich Nietzsche soal the will to power. Bahasa mudahnya, ini tak lebih dari sekadar ”’mencari perbaikan nasib” saja. Masyarakat punya harapan besar jika para mantan wartawan ini bisa menjalankan fungsi legislatif dengan lebih baik—fungsi pengawasan terhadap pemerintah, pembuatan UU, budgeting dan lain-lain.
Kinerja 23 orang wartawan di tengah 550 orang anggota DPR ternyata tak bagus-bagus amat. Bahkan Anthony Zeidra Abidin, anggota Komisi IX, saat ini menjadi pesakitan karena diduga terlibat dalam skandal aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp. 500 juta. Bagaimana bisa wartawan yang mengerti hukum dan menjunjung etika dalam tugasnya, justru hanyut dan tenggelam di dasar sungai bernama kejahatan kerah putih? Memang tak semua wartawan menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugasnya, misalnya menerima amplop[11]. Ada media yang melarang keras wartawannya menerima amplop seperti harian Kompas dan majalah / koran Tempo. Organisasi jurnalis yang mengharamkan amplop bahkan berkampanye untuk itu keluar lembaga sendiri adalah AJI (Aliansi Jurnalis Independen)[12]
.Selain Anthony Z Abidin yang jelas-jelas sudah mendekam di penjara dan kasusnya tengah disidangkan. Ada nama lain, yaitu Bambang Sadono, yang justru mengadu nasib ingin meraih kursi gubernur Jawa Tengah, namun gagal. Kita tak tahu pasti apa alasan Bambang Sadono ingin menjadi gubernur, meski alasan yang standar selalu mengatakan akan membangun Jawa Tengah lebih bagus lagi, seperti yang bisa kita saksikan dalam kampanye pilgub yang dimenangkan Bibit Waluyo-Rustriningsih yang diusung PDI P.
Apa hebat dan uniknya wartawan yang menjadi politisi kalau dia tidak bisa membawa warna baru dunia politik di Indonesia. Publik sebenarnya mencatat tingkah laku yang tak terpuji para anggota DPR. Contohnya Panda Nababan.. Apa yang dia bawa dari Sinar Harapan atau majalah Forum ke PDI P sebagai jurnalis yang pernah mendapat Hadiah Adinegoro untuk karya investigasinya? Menularkan semangat? Membagi ilmu? Menyuarakan pembaruan? Nothing. Ternyata, yang dilakukan dia malah ikut-ikutan membagi-bagikan travel check BII dalam kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, Miranda Goeltom.[13]
Jika ada yang mesti diapresiasi dari beberapa wartawan yang kini aktif di DPR, setidaknya ada dua. Mereka adalah Djoko Susilo, Ketua Komisi I, dan Effendy Choirei, anggota Komisi I. Joko dan Choirie sangat aktif mengritisi pemerintah terutama soal anggaran militer dan politik luar negeri. Joko juga menjadi Wakil Ketua ASEAN Inter-Parliamanetary Myanmar Caucus (AIPMC) yang berpusat di Kuala Lumpur. Kaukus ini sangat tegas dan kritis terhadap pemerintah Indonesia dan junta militer Burma (Myanmar) agar segera mengakhiri penindasan terhadap rakyat negara itu dan membebaskan tokoh pro demokrasi Aung San Suu Kyi.
Dalam berkomunikasi politik dengan kolega maupun mitra mereka, para wartawan anggota DPR tampaknya tak menunjukkan keberbedaan mereka dibanding yang bukan berasal dari kalangan wartawan. Logikanya, wartawan yang kaya data dan mudah mendapat akses ke mana pun, memiliki ‘peluru’ untuk ‘ditembakkan’ ke pemerintah sebagai mitra. Mereka semestinya mempunyai kelebihan di atas rata-rata anggota DPR lainnya. Kenyataannya, modalitas awal ini tak dimanfaatkan. Mereka tak ada bedanya dengan anggota DPR lainnya yang berasal dari partai politik. Tugas utama DPR yaitu pengawasan, budgeting, dan legislasi, seharusnya tak menyulitkan mereka yang berlatar belakang wartawan.
Wartawan atau politisi? Siapapun dari profesi apapun, ketika mereka sudah berada di DPR maka mereka adalah politisi. Sebagai politisi, logika profesi asal mereka acap kali ditinggalkan. Politisi biasanya bekerja dengan alasan atau cara kerja politik. Dalam politik keputusan lahir dari sebuah kompromi atau pemaksaan kehendak mayoritas. Contoh nyata, rekomendasi DPR[14] yang menyatakan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo adalah disebabkan bencana alam bukan kesalahan manusia. Dengan keputusan yang dipengaruhi Lapindo ini, jelas yang diuntungkan adalah Lapindo karena menimpakan penyelesaian masalah kepada pemerintah. DPR dalam hal ini tak menggunakan logika dan nurani – apalagi tersentuh oleh ribuan korban bencana ini. Mereka murni menjadi politisi yang kompromistis demi menyelamatkan Lapindo. Entah keuntungan apa yang didapat para anggota DPR.
Berbondong-bondongnya wartawan pindah ke Senayan tampaknya tak berdampaknya secara signifikan bagi demokratisasi di Indonesia. Pasalnya para wartawan yang bermigrasi dari jurnalis menjadi politisi itu, ketika di tempat yang baru tak memaksimalkan modalitas yang ada seperti kaya data, kritis, akses luas dan ahli lobi, umumnya mereka malah tenggelam atau hanyut dalam langgam irama anggota DPR lainnya. Hanya beberapa nama yang mampu menduduki Ketua Komisi atau Ketua Fraksi, selebihnya anggota biasa. Dari 23 orang mantan wartawan, juga hanya sedikit yang namanya sering muncul menghiasi media karena kritis terhadap pemerintah atau vokal terhadap suatu masalah bangsa. Karena dampak migrasi wartawan ke anggota dewan tak cukup signifikan bagi demokratisasi di Indonesia, maka sejujurnya kehadiran mereka tak lebih dan tak kurang seperti kehadiran para artis dan selebriti ke Senayan. Seperti kita tahu, artis yang ‘manggung’ di Senayan, mereka tak seatraktif di panggung yang sebenarnya, bahkan ada yang suaranya, seperti iklan, “nyaris tak terdengar!”
4. Kesimpulan
Munculnya fenomena “caleg impor” pada Pemilu 2009 bisa dipahami dalam dua hal. Pertama adalah miskinnya kader di partai-partai politik peserta pemilu tahun depan. Kedua memberikan kesempatan kepada kalangan berkualitas di luar partai untuk ikut menjalankan kettanegaraan. “Caleg impor” yang dimaksud adalah mereka dicalonkan sebagai anggota DPR namun buka dari kader partai. Mereka diandalkan keahliannya untuk mendulang suara atau pada saat mereka menjadi legislator. Masuk dalam kategori “caleg impor” antara lain artis atau selebriti, aktivis (mahasisw atau LSM), pakar atau akademisi, dan wartawan.
Mengingat pada periode 2004-2009 ada 23 orang wartawan yang bermigrasi menjadi ‘anggota dewan”. Dan kehadiran mereka tidaklah terlalu menonjol atau mempengruhi secara signifikan kiprah DPR dalam sistem demokrasi kita. Bahkan ada satu anggota DPR dari kalangan wartawan yang menjadi pesakitan karena kasus korupsi. Maka tak bisa dimungkiri, kehadiran mantan wartawan di DPR belum mampu mewarnai kinerja lembaga itu. Yang terjadi justru mereka hanyut dan terwarnai oleh warna DPR yang telah lama coreng-moreng. Wartawan, akademisi, aktivis, bahkan artis atau selebriti sebenarnya menjadi tak penting ketika mereka sudah menjadi anggota DPR. Bukan dari mana asal profesi sebelumnya, melainkan mampukah untuk tak tergoda oleh sistem yang korup.
Daftar Bahan Bacaan:
Komunikasi Politik, Dan Nimmo, cetakan keenam Juni 2005, PT Remaja Rosdakarya
Diktat kuliah “Government and Media Relations”, Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA
Governing with The News-The Media as a Political Institution, University of Chicago, 1998
Blog Andreas Harsono, “Wartawan atau Politikus?” 7 Juni 2004.
Sembilan Elemen Jurnalisme, Bill Kovack dan Tom Rosenstiel, edisi ketiga, Yayasan Pantau 2006
Wajah DPR dan DPD 2004-2009, PT. Kompas Media Nusantara (2006)
www.Inilah.com, 27 Maret 2008
Majalah Tempo, 2 Maret 2008
[1] Fred Siebert dalam Komunikasi Politik, Dan Nimmo, cetakan keenam Juni 2005, PT Remaja Rosdakarya, hal 259
[2] Diktat kuliah “Government and Media Relations”, Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA, hal 23
[3] Governing with The News-The Media as a Political Institution, University of Chicago, 1998
[5] Blog Andreas Harsono, “Wartawan atau Politikus?” 7 Juni 2004.
[6] Sembilan Elemen Jurnalisme, Bill Kovack dan Tom Rosenstiel, edisi ketiga, Yayasan Pantau 2006, hal 6
[7] . Antony Zeidra Abidin, Bambang Sadono, Irsyad Sudiro, Musfihin Dahlan, Slamet Effendy Yusuf, (Partai Golkar); Agung Sasongko, Cyprianus Aoer, Heri Achmadi, Jacobus Mayongpadang, Panda Nababan, Rendhi Lamadjido, Supomo SW, Widada Bujuwiryono, Yoseph Umarhadi (PDI P); Max Sopacoa (PD); Dedy Djamaluddin Malik, Djoko Susilo, Totok Daryanto (PAN); Effendy Choirie, Masduki Baidlowi (PKB); Herman Benediktus Kabur (PKPI)
[8] Blog Andreas Harsono, “Wartawan atau Politisi?”, 7 Juni 2004
[9] Blog Andreas Harsono, “Wartawan atau Politikus?” 7 Juni 2004.
[10] www.Inilah.com, 27 Maret 2008
[11] Biasanya berupa uang atau hadiah barang lainnya yang diberikan sebelum atau sesudah liputannya dimuat atau ditayangkan.
[12] AJI dideklarasikan di Sirnagalih, Bogor, pada 7 Agustus 1994 oleh 58 jurnalis se Indonesia, menyusul pembredelan majalah Tempo, editor dan tabloid Detik. AJI kini beranggotakan lebih dari 500 jurnalis.
[13] Tempo Interaktif, 23 Agustus 2008
[14] Rapat Paripurna DPR, 19 Februari 2008. DPR menyebutkan lumpur yang muncrat merupakan fenomena alam (Tempo, 2 Maret 2008)
Pendahuluan:
Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mendatang, ada sekitar 120 wartawan atau mantan wartawan di seluruh Indonesia ikut berkompetisi menjadi calon anggota legislatif. Ada wajah lama yang kembali mencalonkandiri atau dicalegkan parpol, seperti Cyprianus Aoer, Alfridel Djinu, Yoseph Umar Hadi, Panda Nababan dari PDI P, dan Effendy Chorie (PKB). Ada pula wajah-wajah baru yang mencoba menjadi politisi yang katanya sebagai panggilan seperti Helmi Fauzi dan Hamid Basyaib (PDI P), Bruno Kakawao (PKPI), Teguh Djuwarno (PAN), Mutia Hafild (Partai Golkar). Terdapat juga nama Manuel Kasiepo (PDI P). Dari kalangan kolumnis terdapat nama Zuhairi Misrawi (PDI P), Abdul Rohim Ghozali (PAN).
Munculnya wartawan sebagai caleg mendapat perhatian publik yang kurang lebih sama dengan kehadiran artis dan aktivis pada kontestasi Pemilu 2009. Wartawan, artis dan aktivis seolah dianggap sekelompok manusia yang kurang elok masuk dunia politik di parlemen yang penuh intrik. Wartawan seharusnya independen, artis sejatinya menghibur masyarakat, dan aktivis pantasnya berjuang secara imparsial dan tak mengharap kekuasaan. Itulah sorotan publik dengan kacamata yang kurang positif, yang pada intinya makhluk jenis wartawan, artis, dan aktivis tak pantas berada di lembaga legislatif.
Fenomena wartawan menjadi politikus bukanlah hal baru. Sejarah mencatat para jurnalis perintis menggunakan surat kabarnya sebagai bagian propaganda politik untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Pada masa kemerdekaan, kita melihat sejumlah surat kabar dan wartawan ikut dalam politik melawan rekolonialisasi sekutu. Pada periode 1950-1960-an, ada banyak wartawan menjadi anggota partai politik dan ada beberapa wartawan menjadi duta besar. BM Diah, misalnya, adalah salah satu dari sejumlah wartawan yang menjadi duta bangsa.
Semasa Orde Baru hingga Orde Reformasi kita mengenal sejumlah wartawan senior yang juga diangkat jadi duta besar, seperti Sabam Siagian (Australia), Djafar Assegaff (Vietnam), dan Susanto Pudjomartono (Rusia). Mantan Wakil Presiden Adam Malik dan mantan Menteri Penerangan dan Ketua DPR/MPR Harmoko juga adalah wartawan senior. Pada era reformasi, kian banyak wartawan masuk dunia politik dan beberapa menjadi anggota parlemen. Nama-nama seperti Hery Akhmadi, Cyprianus Aoer, Aco Manafe, Panda Nababan (PDI Perjuangan), Effendie Choirie (PKB), Djoko Susilo (PAN), Benny Harman (PKPI), Max Sopacoa (PD), Antoni Z Abidin, Bambang Sadono (Golkar) adalah sebagian dari sejumlah wartawan yang banting setir masuk dunia politik. Mereka adalah para anggota DPR RI periode 2004-2009.
Mengapa kehadiran wartawan di parlemen menarik perhatian? Hal itu tak lepas posisi wartawan sebagai bagian masyarakat media atau pers yang dalam negara demokrasi dianggap sebagai salah satu dari empat pilarnya. Pilar lain demokrasi adalah eksekutuf, yudikatif, dan legislatif. Menjadi wartawan sebagai penyampai berita dan pengritik pemerintah, sebenarnya sudah cukup, karena mereka telah menjalankan peran sebagai salah satu pilar demokrasi. Namun, toh tiap lima tahun sekali, sesuai periode pemilu di Indonesia, selalu ada migrasi profesi, dari wartawan ke poltitisi atau anggota parlemen.
Tilisan “Government and Media Relations” ini mengajukan sejumlah pertanyaan. Pertanyaan yang kemudian mengemuka, antara lain adalah 1) Mengapa sejumlah wartawan pindah profesi menjadi politikus di Senayan? 2) Apa kelebihan wartawan sehingga dianggap layak masuk ke dunia politik terutama menjadi anggota DPR? 3) Adakah peluang ‘menggiurkan’ atau ‘menantang’ dalam dunia politik yang membuat mereka pindah profesi? 4) Adakah kontribusi positif kepada demokrasi kita dari masuknya wartawan ke politik formal. 5) Bagaimana komunikasi politik wartawan anggota DPR dengan sesama anggota DPR, pemerintah, dan masyarakat? 6) Betulkah mereka telah memberikan perbedaan signifikan (dalam arti positif) dibandingkan profesi lain terhadap kinerja parlemen di masa lalu?
Agar pembahasan “Government and Media Relations” ini lebih fokus, maka yang kami dipilih sebagai obyek pengamatan, adalah para wartawan yang terjun menjadi anggota DPR periode 2004-2009. Mengapa periode 2004-2009? Karena anggota DPR periode ini tengah berjalan dan hampir selesai masa tugasnya, sehingga lebih mudah data yang akan kita peroleh untuk diteliti dan dianalisa.
2. Kerangka Teori:
Pers merupakan pilar keempat demokrasi (the fourth estate of democracy). Anggapan umum yang selama ini beredar di tengah-tengah masyarakat mengatakan demikian. Bahkan pernyataan "media merupakan kekuatan keempat setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif" telah menjadi aksioma politik, sebuah kebenaran cara berpikir politis yang tidak perlu dibantah lagi. Meski demikian, media atau pers tak hidup di ruang hampa. Ia berada dalam sebuah negara yang mempunyai sistem tertentu.
Dalam karyanya yang ditulis tiga dasa warsa lampau Fred Siebert dan rekan-rekan mengemukakan ada empat teori utama tentang hubungan antara pemerintah dan pers: 1) teori otoriter bahwa kekuasaan pemerintah harus dipusatkan pada satu orang atau elit, dan pers harus berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk memelihara ketertiban dan pemerintahan golongan elit; 2) teori libertarian yang berargumentasi bahwa pers harus berjalan dengan cara laissez faire, tidak dikekang, untuk menciptakan pluralisme titik pandang yang memberikan pengujian independen terhadap pemerintah dan peluang untuk menelaah semua opini secara bebas dan terbuka; 3) teori komunis yang melihat pers sebagai alat untuk menyampaikan kebijakan sosial untuk kepentingan ideologi dan tujuan yang diwakili oleh partai komunis; dan 4) teori pertanggungjawaban sosial yang menerima prinsip pers bebas, tetapi pers yang melaksanakan pelayanan masyarakat melalui kritik sosial dan pendidikan masyarakat yang bertanggungjawab, dengan anggapan bahwa jaminan atas pers bebas adalah jaminan kepada warga negara nasion, bukan yang pada dasarnya merupakan perlindungan atas hak pemilikan bagi pemilikan pers[1]
Teori pers libertarian paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia ini. Hal ini tak lepas dari kemenangan kapitalisme atas komunisme pascaperang dingin akhir 1980an. Sistem Pers Bebas menurut Walter Lippman[2] sesungguhnya merupakan ekspresi suatu kebenaran yang muncul dari cara “Free reporting” dan “Free discussion” dan sama sekali bukan dari apa yang disajikan secara sempurna dan instan yang diucapkan oleh seseorang. Pada sistem ini, pers layak disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Karena kebebasannya, pers mampu menjadi “wacthdog” pemerintah.
Kini, di tengah tekanan kapitalisasi dan iklim kebebasan, peran sentral pers dalam konteks demokrasi dan politik masih kokoh. Pers yang terletak pada dua entitas—organisasi pemberitaan (news organization) dan organisasi bisnis (business organization)—diharapkan mampu menyeimbangkan perannya sebagai pilar keempat demokrasi.
Menarik menyimak pemikiran yang diungkapkan oleh pakar media politik asal Amerika Serikat (AS), Timothy E Cook[3] (1998). Dia menyebut term media sebagai political actor (aktor politik) atau institusi politik. Cook berargumen bahwa media merupakan salah satu aktor atau institusi politik yang dapat menggunakan haknya sendiri secara independen, ”political actor / institution in its own right.” Selama ini ketika berbicara tentang media dan politik, kita kerap terjebak pada tataran komunikasi politik. Artinya, dalam perspektif ini media hanya dijadikan salah satu medium pasif bagi para spin doctor untuk menyampaikan pesan-pesan (kampanye) politik demi meraih kekuasaan.
Dalam sistem yang kini dianut Indonesia memungkinkan institusi media dan awak media menjadi sangat berperan dalam perubahan, dan karenanya sangat dikenal oleh masyarakat. Institusi media mungkin lebih dikenal publik daripada para wartawan yang tiap hari bekerja mengais berita. Interaksi antara partai politik dan media menjadikan dua pelaku demokrasi yang sama-sama mengklaim penyambung lidah masyarakat itu berinteraksi saling menghormati dan menguntungkan. Mereka saling mengagumi satu sama lain, meski terkadang saling mengritisi. Banyaknya anggota DPR yang terkuak skandalnya-- baik korupsi maupun perselingkuhan seks—tak lepas dari peran wartawan. Sebaliknya, banyak kejadian yang mungkin tak terungkap, meski bisa diungkap ke publik, karena para politisi mampu “membeli” atau “memelihara” wartawan. Simbiosis mutualisma atau perselingkuhan antara wartawan dan politisi ini tentu sangat [4]merugikan publik, baik sebagai konstituen partai politik, maupun pembaca media yang berhak untuk mendapatkan informasi.
Bill Kovach, kurator Nieman Foundation on Journalism, Universitas Harvard, salah satu guru wartawan yang paling dihormati dari Amerika Serikat, berpendapat mengenai makna informasi buat seorang politikus dan seorang wartawan. Kovach menutip Presiden Jimmy Carter (1975), "Ketika Anda memiliki kekuasaan, Anda menggunakan informasi untuk membuat orang mengikuti kepemimpinan Anda. Namun kalau Anda wartawan, Anda menggunakan informasi untuk membantu orang mengambil sikap mereka sendiri."[5]
Informasi yang sama dipakai untuk dua tujuan yang berbeda. Bahkan berlawanan. Inilah yang membuat Kovach mengambil sikap teguh untuk independen dari dunia politik maupun politisi. Kovach setia pada jurnalisme dan tak pernah mau menerima tawaran masuk ke dunia politik.
Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat. Sembilan elemen jurnalisme Kovack dan Tom Rosenstiel sangat terkenal di kalangan jurnalis. Delapan elemen lainnya adalah; kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran; intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi; praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita; jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan; jurnalisme harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat; jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting menarik dan relevan; jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional; dan praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka[6].
Loyalitas utama seorang wartawan adalah kepada warga masyarakat tempatnya berada. Wartawan bisa melayani warga dengan sebaik-baiknya apabila mereka bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput. Independen baik dari institusi pemerintah, bisnis, sosial maupun politik. Wartawan bahkan harus independen dari pemilik media tempatnya bekerja.
3. Pembahasan: Politisi Wartawan atau Wartawan Politisi?
Dalam buku “Wajah DPR dan DPD 2004-2009” terbitan PT. Kompas Media Nusantara (2006), terdapat sekitar 23 mantan waratawan[7]. Mereka berasal dari enam partai yaitu Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia. Di antara wartawan yang menjadi politisi Senayan 2004-2009, ada yang telah lama meninggalkan profesi wartawan, ada pula yang masih berstatus wartawan ketika migrasi menjadi politisi.
Wartawan termasuk warga negara biasa yang punya hak politik dan sering diharapkan ikut memimpin masyarakatnya. Mereka sah melakukannya. Cyprianus Aoer sangat memrihatinkan warga Flores karena kurang diperjuangkan di Jakarta. Tidakkah pilihan Aoer sah untuk terjun ke Parlemen?Bisa jadi alasan wartawan lainnya terjun ke parlemen berbeda. Ada yang seperti Aoer untuk memperjuangkan daerah asalnya, ada pula yang ingin memperjuangkan suatu isu tertentu misalnya pemberantasan korupsi atau transparansi pemerintahan.
Bagi Andreas Harsono[8], mantan wartawan The Jakarta Post yang kini mengelola Yayasan Pantau, suatu lembaga nirlaba untuk kemajuan jurnalisme, keterlibatan wartawan dalam politik memang kadang tak terhindarkan. Namun, sebaiknya diberlakukan sebagai one-way ticket. Artinya, seorang wartawan boleh menjadi politikus tetapi ia sebaiknya jangan kembali menjadi wartawan. Aoer boleh masuk parlemen tapi jangan kembali ke Suara Pembaruan. Djoko Susilo boleh menjadi politikus handan di Komisi I DPR namun jangan kembali ke Jawa Pos. Bila seorang wartawan masuk politik menjadi anggota DPR, ia akan mempunyai sikap yang berbeda terhadap informasi, sehingga lebih baik bila ia tak kembali ke media. Praktik bolak-balik ini akan menimbulkan citra kurang baik dari masyarakat tehadap media di Indonesia, apalagi pada masa demokratisasi sekarang ini, di mana warga butuh informasi yang bermutu untuk mengambil sikap terhadap berbagai isu penting di Indonesia.
Pandangan Andreas Harsono di atas memang sangat ideal. Namun bagi kalangan wartawan yang kini menduduki kursi empuk di Senayan, tentu tak semua menerima pendapat Andreas. Banyak alasan yang bisa dikemukakan mengapa seseorang melakukan ganti profesi dan kembali lagi ke pekerjaan semula. Ada yang memajukan alasan ingin melakukan perubahan dari dalam, sampai yang terus terang sekedar mencari jabatan. Wajar saja wartawan sebagai korps keempat pilar demokrasi tampil sebagai anggota legislatif karena peran atau profesi apa pun punya peran sosial kemasyarakatan. Yang penting wartawan sebagai anggota DPR tidak semata membawa ambisi politik, tetapi juga membawa tekad untuk membawa perubahan dan kesegaran baru[9].
Lain Andreas lain pula Arswendo Atmowiloto[10], wartawan sekaligus budayawan. Sebuah karya jurnalistik, kata Arswendo, baik tulisan maupun gambar pada derajat tertentu mampu menyodorkan informasi menjadi fakta yang menggugah publik. “Wartawan lebih powerful daripada anggota DPR,“ ujarnya. Wartawan, lanjut Arswendo, bisa menulis tentang banyak hal dan menggerakkan banyak orang untuk melihat realita sosial yang ada dan melakukan perubahan ke arah yang lebih positif. Hal ini yang belum mampu dilakukan bahkan oleh anggota DPR sekalipun. Karya-karya jurnalistik di Indonesia seharusnya dapat memotret realita sosial yang ada sehingga dapat memberikan dampak luas bagi masyarakat. Karya-karya jurnalistik yang lebih peka dan humanis akan membawa dampak sosial kepada masyarakat luas.
Sudah bagus berperan sebagai wartawan tetapi mengapa malah pindah profesi sebagai politisi? Adalah hak setiap warga untuk berpolitik dan berganti profesi. Apa kelebihan para jurnalis ini sehingga bisa masuk dunia politik? Betulkah kehadiran para mantan jurnalis ini memberi kontribusi positif bagi dunia politik partai saat ini? Ataukah ia akan ”larut dan hanyut” gelombang perpolitikan parlemen seperti banyak dikritik? Dunia kewartawanan dan politik dapat dikatakan merupakan dua hal yang jauh berbeda. Salah satu fungsi wartawan adalah melakukan kontrol terhadap pejabat publik dan politisi. Namun, kedua profesi yang bertolak belakang itu dapat dijalani dengan baik oleh orang yang tak mudah “larut dan hanyut”.
Dibandingkan profesi lain, wartawan dianggap memiliki kelebihan dalam melobi orang lain, terutama orang penting, termasuk pejabat publik. Sebagian wartawan juga dikenal pandai berargumentasi, lihai bersilat lidah, dan—ini tak kalah penting—kemudahan akses pada informasi dan media massa. Bagi sebagian wartawan itu, dunia politik adalah bagian kehidupan sehari-hari saat menjadi jurnalis. Bagi partai politik, mungkin wartawan dianggap bisa menjadi pasukan segar untuk bertarung tahun depan.
Apakah fenomena wartawan menjadi politikus tak lebih dari para pihak yang ingin masuk politik kekuasaan untuk kepentingan sendiri atau partainya? Ini mengingatkan kita pada Friedrich Nietzsche soal the will to power. Bahasa mudahnya, ini tak lebih dari sekadar ”’mencari perbaikan nasib” saja. Masyarakat punya harapan besar jika para mantan wartawan ini bisa menjalankan fungsi legislatif dengan lebih baik—fungsi pengawasan terhadap pemerintah, pembuatan UU, budgeting dan lain-lain.
Kinerja 23 orang wartawan di tengah 550 orang anggota DPR ternyata tak bagus-bagus amat. Bahkan Anthony Zeidra Abidin, anggota Komisi IX, saat ini menjadi pesakitan karena diduga terlibat dalam skandal aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp. 500 juta. Bagaimana bisa wartawan yang mengerti hukum dan menjunjung etika dalam tugasnya, justru hanyut dan tenggelam di dasar sungai bernama kejahatan kerah putih? Memang tak semua wartawan menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugasnya, misalnya menerima amplop[11]. Ada media yang melarang keras wartawannya menerima amplop seperti harian Kompas dan majalah / koran Tempo. Organisasi jurnalis yang mengharamkan amplop bahkan berkampanye untuk itu keluar lembaga sendiri adalah AJI (Aliansi Jurnalis Independen)[12]
.Selain Anthony Z Abidin yang jelas-jelas sudah mendekam di penjara dan kasusnya tengah disidangkan. Ada nama lain, yaitu Bambang Sadono, yang justru mengadu nasib ingin meraih kursi gubernur Jawa Tengah, namun gagal. Kita tak tahu pasti apa alasan Bambang Sadono ingin menjadi gubernur, meski alasan yang standar selalu mengatakan akan membangun Jawa Tengah lebih bagus lagi, seperti yang bisa kita saksikan dalam kampanye pilgub yang dimenangkan Bibit Waluyo-Rustriningsih yang diusung PDI P.
Apa hebat dan uniknya wartawan yang menjadi politisi kalau dia tidak bisa membawa warna baru dunia politik di Indonesia. Publik sebenarnya mencatat tingkah laku yang tak terpuji para anggota DPR. Contohnya Panda Nababan.. Apa yang dia bawa dari Sinar Harapan atau majalah Forum ke PDI P sebagai jurnalis yang pernah mendapat Hadiah Adinegoro untuk karya investigasinya? Menularkan semangat? Membagi ilmu? Menyuarakan pembaruan? Nothing. Ternyata, yang dilakukan dia malah ikut-ikutan membagi-bagikan travel check BII dalam kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, Miranda Goeltom.[13]
Jika ada yang mesti diapresiasi dari beberapa wartawan yang kini aktif di DPR, setidaknya ada dua. Mereka adalah Djoko Susilo, Ketua Komisi I, dan Effendy Choirei, anggota Komisi I. Joko dan Choirie sangat aktif mengritisi pemerintah terutama soal anggaran militer dan politik luar negeri. Joko juga menjadi Wakil Ketua ASEAN Inter-Parliamanetary Myanmar Caucus (AIPMC) yang berpusat di Kuala Lumpur. Kaukus ini sangat tegas dan kritis terhadap pemerintah Indonesia dan junta militer Burma (Myanmar) agar segera mengakhiri penindasan terhadap rakyat negara itu dan membebaskan tokoh pro demokrasi Aung San Suu Kyi.
Dalam berkomunikasi politik dengan kolega maupun mitra mereka, para wartawan anggota DPR tampaknya tak menunjukkan keberbedaan mereka dibanding yang bukan berasal dari kalangan wartawan. Logikanya, wartawan yang kaya data dan mudah mendapat akses ke mana pun, memiliki ‘peluru’ untuk ‘ditembakkan’ ke pemerintah sebagai mitra. Mereka semestinya mempunyai kelebihan di atas rata-rata anggota DPR lainnya. Kenyataannya, modalitas awal ini tak dimanfaatkan. Mereka tak ada bedanya dengan anggota DPR lainnya yang berasal dari partai politik. Tugas utama DPR yaitu pengawasan, budgeting, dan legislasi, seharusnya tak menyulitkan mereka yang berlatar belakang wartawan.
Wartawan atau politisi? Siapapun dari profesi apapun, ketika mereka sudah berada di DPR maka mereka adalah politisi. Sebagai politisi, logika profesi asal mereka acap kali ditinggalkan. Politisi biasanya bekerja dengan alasan atau cara kerja politik. Dalam politik keputusan lahir dari sebuah kompromi atau pemaksaan kehendak mayoritas. Contoh nyata, rekomendasi DPR[14] yang menyatakan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo adalah disebabkan bencana alam bukan kesalahan manusia. Dengan keputusan yang dipengaruhi Lapindo ini, jelas yang diuntungkan adalah Lapindo karena menimpakan penyelesaian masalah kepada pemerintah. DPR dalam hal ini tak menggunakan logika dan nurani – apalagi tersentuh oleh ribuan korban bencana ini. Mereka murni menjadi politisi yang kompromistis demi menyelamatkan Lapindo. Entah keuntungan apa yang didapat para anggota DPR.
Berbondong-bondongnya wartawan pindah ke Senayan tampaknya tak berdampaknya secara signifikan bagi demokratisasi di Indonesia. Pasalnya para wartawan yang bermigrasi dari jurnalis menjadi politisi itu, ketika di tempat yang baru tak memaksimalkan modalitas yang ada seperti kaya data, kritis, akses luas dan ahli lobi, umumnya mereka malah tenggelam atau hanyut dalam langgam irama anggota DPR lainnya. Hanya beberapa nama yang mampu menduduki Ketua Komisi atau Ketua Fraksi, selebihnya anggota biasa. Dari 23 orang mantan wartawan, juga hanya sedikit yang namanya sering muncul menghiasi media karena kritis terhadap pemerintah atau vokal terhadap suatu masalah bangsa. Karena dampak migrasi wartawan ke anggota dewan tak cukup signifikan bagi demokratisasi di Indonesia, maka sejujurnya kehadiran mereka tak lebih dan tak kurang seperti kehadiran para artis dan selebriti ke Senayan. Seperti kita tahu, artis yang ‘manggung’ di Senayan, mereka tak seatraktif di panggung yang sebenarnya, bahkan ada yang suaranya, seperti iklan, “nyaris tak terdengar!”
4. Kesimpulan
Munculnya fenomena “caleg impor” pada Pemilu 2009 bisa dipahami dalam dua hal. Pertama adalah miskinnya kader di partai-partai politik peserta pemilu tahun depan. Kedua memberikan kesempatan kepada kalangan berkualitas di luar partai untuk ikut menjalankan kettanegaraan. “Caleg impor” yang dimaksud adalah mereka dicalonkan sebagai anggota DPR namun buka dari kader partai. Mereka diandalkan keahliannya untuk mendulang suara atau pada saat mereka menjadi legislator. Masuk dalam kategori “caleg impor” antara lain artis atau selebriti, aktivis (mahasisw atau LSM), pakar atau akademisi, dan wartawan.
Mengingat pada periode 2004-2009 ada 23 orang wartawan yang bermigrasi menjadi ‘anggota dewan”. Dan kehadiran mereka tidaklah terlalu menonjol atau mempengruhi secara signifikan kiprah DPR dalam sistem demokrasi kita. Bahkan ada satu anggota DPR dari kalangan wartawan yang menjadi pesakitan karena kasus korupsi. Maka tak bisa dimungkiri, kehadiran mantan wartawan di DPR belum mampu mewarnai kinerja lembaga itu. Yang terjadi justru mereka hanyut dan terwarnai oleh warna DPR yang telah lama coreng-moreng. Wartawan, akademisi, aktivis, bahkan artis atau selebriti sebenarnya menjadi tak penting ketika mereka sudah menjadi anggota DPR. Bukan dari mana asal profesi sebelumnya, melainkan mampukah untuk tak tergoda oleh sistem yang korup.
Daftar Bahan Bacaan:
Komunikasi Politik, Dan Nimmo, cetakan keenam Juni 2005, PT Remaja Rosdakarya
Diktat kuliah “Government and Media Relations”, Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA
Governing with The News-The Media as a Political Institution, University of Chicago, 1998
Blog Andreas Harsono, “Wartawan atau Politikus?” 7 Juni 2004.
Sembilan Elemen Jurnalisme, Bill Kovack dan Tom Rosenstiel, edisi ketiga, Yayasan Pantau 2006
Wajah DPR dan DPD 2004-2009, PT. Kompas Media Nusantara (2006)
www.Inilah.com, 27 Maret 2008
Majalah Tempo, 2 Maret 2008
[1] Fred Siebert dalam Komunikasi Politik, Dan Nimmo, cetakan keenam Juni 2005, PT Remaja Rosdakarya, hal 259
[2] Diktat kuliah “Government and Media Relations”, Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA, hal 23
[3] Governing with The News-The Media as a Political Institution, University of Chicago, 1998
[5] Blog Andreas Harsono, “Wartawan atau Politikus?” 7 Juni 2004.
[6] Sembilan Elemen Jurnalisme, Bill Kovack dan Tom Rosenstiel, edisi ketiga, Yayasan Pantau 2006, hal 6
[7] . Antony Zeidra Abidin, Bambang Sadono, Irsyad Sudiro, Musfihin Dahlan, Slamet Effendy Yusuf, (Partai Golkar); Agung Sasongko, Cyprianus Aoer, Heri Achmadi, Jacobus Mayongpadang, Panda Nababan, Rendhi Lamadjido, Supomo SW, Widada Bujuwiryono, Yoseph Umarhadi (PDI P); Max Sopacoa (PD); Dedy Djamaluddin Malik, Djoko Susilo, Totok Daryanto (PAN); Effendy Choirie, Masduki Baidlowi (PKB); Herman Benediktus Kabur (PKPI)
[8] Blog Andreas Harsono, “Wartawan atau Politisi?”, 7 Juni 2004
[9] Blog Andreas Harsono, “Wartawan atau Politikus?” 7 Juni 2004.
[10] www.Inilah.com, 27 Maret 2008
[11] Biasanya berupa uang atau hadiah barang lainnya yang diberikan sebelum atau sesudah liputannya dimuat atau ditayangkan.
[12] AJI dideklarasikan di Sirnagalih, Bogor, pada 7 Agustus 1994 oleh 58 jurnalis se Indonesia, menyusul pembredelan majalah Tempo, editor dan tabloid Detik. AJI kini beranggotakan lebih dari 500 jurnalis.
[13] Tempo Interaktif, 23 Agustus 2008
[14] Rapat Paripurna DPR, 19 Februari 2008. DPR menyebutkan lumpur yang muncrat merupakan fenomena alam (Tempo, 2 Maret 2008)
Perselingkuhan Lembaga Survei dan Konsultan Politik
Employees of the Center must avoid conflicts of interest or the appearance of conflicts of interest. They should never engage in any activity that might compromise or appear to compromise the Center's credibility or its reputation for independence or impartiality. All employees are required to seek prior approval from a supervisor before engaging in any activity that may be deemed a potential conflict of interest, including membership in groups, boards and associations that may call into question the Center's credibility or its reputation for impartiality. (Pew Research Center Code of Ethics on Conflicts of Interest)
Iklan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 16 Desember 2008 yang menegaskan bahwa “Di Negara Demokrasi Lembaga Survei (Peneliti/Pollster) dapat merangkap sebagai Konsultan Politik” sungguh sangat provokatif. Siapa sebenarnya yang ingin diprovokasi? Para calon klien? Para pesaing? Atau lembaga semacam KPU dan pemerintah?
Setelah saya membuka dua situs Pew Research Center dan Rasmussen, jelas kiranya bahwa Komunikasi Politik hanya atau terutama mengakui Pollster ini dibanding Campaign Pollster semacam LSI milik Denny J.A. Begitu banyak macam poling yang telah dilakukan Pew Research Center dan Rasmussen yang menurut saya sangat independen, atas inisiatif sendiri, dan bukan pesanan partai atau kandidat. Rasmussen terakhir (22/12) membuat poling tentang dinasti politik di AS, di mana 47% mengaku khawatir. Sementara Pew Research Center mensurvei tingkat kepercayaan publik atas transisi dari Bush ke Obama (23/12). Penjelasan tentang kebijakan Obama (72% disetujui), Pemilihan kabinet (71% disetujui), Banyaknya orang-orang di zaman Clinton (63% bagus).
Seperti kita ketahui, di negeri-negeri yang menganut sistem demokratis, metode survei digunakan untuk mengetahui pendapat publik. Atas dasar asumsi, pendapat publik amat penting bagi pembuat kebijakan, berbagai teknik canggih telah dikembangkan para ilmuwan politik. Studi tentang pendapat umum di Amerika Serikat (AS) telah mengalami perkembangan pesat sejak 1950-an, terutama untuk mengetahui sikap dan preferensi politik masyarakat umum. Pada era 1970-an, metode ini kian populer untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan publik terhadap pendapat umum atau sebaliknya, bagaimana pendapat umum memengaruhi kebijakan publik.
Selain munculnya lembaga pengumpul jajak pendapat, marak pula kehadiran konsultan politik. Seorang konsultan politik adalah seorang profesional kampanye yang terlibat dalam pemberian nasihat dan jasa-jasa kepada para kontestan pemilu, baik berupa jajak pendapat, produksi, dan penciptaan media. Di sinilah kadang konflik interes terjadi, bisa seorang pollster sekaligus konsultan politik.
Fenomena konsultan politik seperti di AS ini juga telah merambah ke tanah air, terutama sejak diterapkannya sistem pemilihan presiden secara langsung pada 2004. Setelah itu, sejak 2005 ketika pemilihan kepala daerah juga dilakukan secara langsung, ‘industri’ tim sukses dan survei ini kian marak.
Konsultan politik harus bersikap profesional dan bersikap jujur tentang aneka kelemahan dari survei yang dilakukan atau dilakukan pihak lain. Mereka juga harus mau bersikap jujur untuk memberitahukan siapa yang mensponsorisurvei dan jajak pendapat yang mereka lakukan. Di AS misalnya, salah satu kode etik yang disepakati melalui Asosiasi Amerika untuk Penelitian Pendapat Publik (American Association for Public Opinion Reserarch) telah mencantumkan keharusan bagi lembaga yang melakukan penelitian pendapat publik. Konsultan politik yang profesional adalah yang mampu mengantarkan kliennya ke tujuan dengan cara-cara yang cerdas, bermartabat, dan efisien.
Kembali soal iklan LSI di atas, tampaknya ini merupakan bagian dari upaya Denny J.A. ingin menguasai pasar pollster dan konsultan politik di Indonesia untuk mencapai rekor dunia. Entah apanya yang paling di dunia.
Dalam setahun terakhir ini banyak survei politik dilakukan lembaga yang sudah dikenal masyarakat seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Indo Barometer. Siapakah mereka itu?
Uniknya, ketiga lembaga ini dahulu berasal dari satu institusi yang sama di bawah Denny JA, yaitu Lembaga Survei Indonesia. Dalam perjalanannya, Syaiful Mujani mengundurkan diri dari LSI dan membentuk LSI baru dengan nama yang sama yaitu Lembaga Survei Indonesia, sedangkan Denny JA dan M. Qodari tetap di LSI dengan nama baru Lingkaran Survei Indonesia, baru kemudian M. Qodari pecah kongsi dengan Denny J.A dan kemudian membentuk Indo Barometer.
LSI Syaiful Mujani dan Indo Barometer M Qodari tampaknya memilih di jalur yang memisahkan antara pollster dengan konsultan politik. Hali itu diyakini akan lebih menghasilkan survei yang akurat dan kredibel. Sementara Denny J.A berpendapat lain. Sah-saja bila lembaga survei bergerak sekaligus konsultan politik partai, kandidat Presiden atau berbagai kandidat dalam Pilkada. Di AS pun sejak 1970-an konsultan politik yang sekaligus melakukan survei tumbuh bak jamur di musim hujan, yang berdampak negatif bagi fungsi mesin partai karena digantikan para konsultan politik profesional.
Nah bagaimana dengan kita? Saya jelas mendukung sikap seperti LSI Syaiful Mujani dan Indo Barometer M. Qodari. Bagaimana pun, demi profesionalitas, kita harus memisahkan antara pekerjaan pollster dengan konsultan politik. Jika kita bekerja dengan kode etik yang jelas, seperti dokter, pengacara atau wartawan, maka profesionalitas kita juga akan terjaga.
Yogyakarta, 23 Desember 2008
Iklan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 16 Desember 2008 yang menegaskan bahwa “Di Negara Demokrasi Lembaga Survei (Peneliti/Pollster) dapat merangkap sebagai Konsultan Politik” sungguh sangat provokatif. Siapa sebenarnya yang ingin diprovokasi? Para calon klien? Para pesaing? Atau lembaga semacam KPU dan pemerintah?
Setelah saya membuka dua situs Pew Research Center dan Rasmussen, jelas kiranya bahwa Komunikasi Politik hanya atau terutama mengakui Pollster ini dibanding Campaign Pollster semacam LSI milik Denny J.A. Begitu banyak macam poling yang telah dilakukan Pew Research Center dan Rasmussen yang menurut saya sangat independen, atas inisiatif sendiri, dan bukan pesanan partai atau kandidat. Rasmussen terakhir (22/12) membuat poling tentang dinasti politik di AS, di mana 47% mengaku khawatir. Sementara Pew Research Center mensurvei tingkat kepercayaan publik atas transisi dari Bush ke Obama (23/12). Penjelasan tentang kebijakan Obama (72% disetujui), Pemilihan kabinet (71% disetujui), Banyaknya orang-orang di zaman Clinton (63% bagus).
Seperti kita ketahui, di negeri-negeri yang menganut sistem demokratis, metode survei digunakan untuk mengetahui pendapat publik. Atas dasar asumsi, pendapat publik amat penting bagi pembuat kebijakan, berbagai teknik canggih telah dikembangkan para ilmuwan politik. Studi tentang pendapat umum di Amerika Serikat (AS) telah mengalami perkembangan pesat sejak 1950-an, terutama untuk mengetahui sikap dan preferensi politik masyarakat umum. Pada era 1970-an, metode ini kian populer untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan publik terhadap pendapat umum atau sebaliknya, bagaimana pendapat umum memengaruhi kebijakan publik.
Selain munculnya lembaga pengumpul jajak pendapat, marak pula kehadiran konsultan politik. Seorang konsultan politik adalah seorang profesional kampanye yang terlibat dalam pemberian nasihat dan jasa-jasa kepada para kontestan pemilu, baik berupa jajak pendapat, produksi, dan penciptaan media. Di sinilah kadang konflik interes terjadi, bisa seorang pollster sekaligus konsultan politik.
Fenomena konsultan politik seperti di AS ini juga telah merambah ke tanah air, terutama sejak diterapkannya sistem pemilihan presiden secara langsung pada 2004. Setelah itu, sejak 2005 ketika pemilihan kepala daerah juga dilakukan secara langsung, ‘industri’ tim sukses dan survei ini kian marak.
Konsultan politik harus bersikap profesional dan bersikap jujur tentang aneka kelemahan dari survei yang dilakukan atau dilakukan pihak lain. Mereka juga harus mau bersikap jujur untuk memberitahukan siapa yang mensponsorisurvei dan jajak pendapat yang mereka lakukan. Di AS misalnya, salah satu kode etik yang disepakati melalui Asosiasi Amerika untuk Penelitian Pendapat Publik (American Association for Public Opinion Reserarch) telah mencantumkan keharusan bagi lembaga yang melakukan penelitian pendapat publik. Konsultan politik yang profesional adalah yang mampu mengantarkan kliennya ke tujuan dengan cara-cara yang cerdas, bermartabat, dan efisien.
Kembali soal iklan LSI di atas, tampaknya ini merupakan bagian dari upaya Denny J.A. ingin menguasai pasar pollster dan konsultan politik di Indonesia untuk mencapai rekor dunia. Entah apanya yang paling di dunia.
Dalam setahun terakhir ini banyak survei politik dilakukan lembaga yang sudah dikenal masyarakat seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Indo Barometer. Siapakah mereka itu?
Uniknya, ketiga lembaga ini dahulu berasal dari satu institusi yang sama di bawah Denny JA, yaitu Lembaga Survei Indonesia. Dalam perjalanannya, Syaiful Mujani mengundurkan diri dari LSI dan membentuk LSI baru dengan nama yang sama yaitu Lembaga Survei Indonesia, sedangkan Denny JA dan M. Qodari tetap di LSI dengan nama baru Lingkaran Survei Indonesia, baru kemudian M. Qodari pecah kongsi dengan Denny J.A dan kemudian membentuk Indo Barometer.
LSI Syaiful Mujani dan Indo Barometer M Qodari tampaknya memilih di jalur yang memisahkan antara pollster dengan konsultan politik. Hali itu diyakini akan lebih menghasilkan survei yang akurat dan kredibel. Sementara Denny J.A berpendapat lain. Sah-saja bila lembaga survei bergerak sekaligus konsultan politik partai, kandidat Presiden atau berbagai kandidat dalam Pilkada. Di AS pun sejak 1970-an konsultan politik yang sekaligus melakukan survei tumbuh bak jamur di musim hujan, yang berdampak negatif bagi fungsi mesin partai karena digantikan para konsultan politik profesional.
Nah bagaimana dengan kita? Saya jelas mendukung sikap seperti LSI Syaiful Mujani dan Indo Barometer M. Qodari. Bagaimana pun, demi profesionalitas, kita harus memisahkan antara pekerjaan pollster dengan konsultan politik. Jika kita bekerja dengan kode etik yang jelas, seperti dokter, pengacara atau wartawan, maka profesionalitas kita juga akan terjaga.
Yogyakarta, 23 Desember 2008
Tragedi Lumpur Lapindo
Politik Komunikasi Dalam Kasus Bencana Lumpur Lapindo, Sidoarjo
PENDAHULUAN:
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – M Jusuf Kalla (SBY-JK) ditandai dengan berbagai bencana besar. Diawali gempa dan tsunami dahsyat di Aceh dan Sumatera Utara pada 26 Desember 2004, kemudian pada 27 Mei 2006 gempa besar menerpa Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Di luar itu bencana banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, terjadi dalam skala besar, sampai beberapa kali kecelakaan lalu lintas – termasuk hilangnya pesawat Adam Air dan jatuhnya Mandala Air di Polonia Medan – melengkapi masa pemerintahan SBY-JK yang penuh musibah. Umumnya bencana, seperti gempa, tsunami, kebakaran, atau banjir, berlangsung tak lama, termasuk dampak yang ditimbulkan. Namun ada satu tragedi atau bencana di mana sejak prahara itu terjadi sampai hari ini terus berlangsung, begitu juga dampak yang ditimbulkan bagi korban. Bencana atau tragedi itu tak lain adalah muncratnya lumpur panas di area pengeboran PT Lapindo Brantas, Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Mei 2006.
Dalam sepekan, lumpur itu menelan 10 hektar kawasan dan melenyapkan jalan tol Gempol-Surabaya yang berjarak 200 meter dari pusat semburan. Hari demi hari, bulan demi bulan, lumpur panas itu telah menggenangi 345 hektar di wilayah desa Jatirejo (3.420 jiwa), Siring (4.240 jiwa), Kedungbendo (22.833 jiwa), dan Renokenongo (4.753 jiwa). Wilayah bencana kemudian meluas hingga membuat mati beberapa desa termasuk Kedungcangkring (3.818 jiwa), Pejarakan (1.609 jiwa), dan Besuki (3.499 jiwa).
Skala bencana yang amat besar ini membuat Kementerian Lingkungan Hidup meminta Lapindo bertanggung jawab pada 9 Juni 2006. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, tak mau ketinggalan, pada 18 Juni 2006, mengatakan Lapindo harus bertanggung jawab. Presiden SBY pada 8 September 2006 membentuk tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo, dengan masa kerja enam bulan. Tim ini kemudian diperpanjang masa tugasnya selama sebulan, kemudian Presiden SBY membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, yang dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2007.
Di tengah maraknya aksi menentang kelambatan pemerintah dan Lapindo menangani luapan lumpur dan para korban, DPR menyetujui pembentukan Tim Pengawas Penyelesaian Kasus Lumpur Lapindo, dengan masa kerja tiga bulan. Tim DPR yang bekerja hanya tiga bulan ini – ditengarai hanya bertemu dengan ahli geologi yang pro Lapindo – bisa dipastikan hasilnya menguntungkan Lapindo. Maka tak aneh, pada 19 Februari 2008, dalam rapat paripurna DPR, setelah mendengarkan laporan dari tim tadi, DPR menyebutkan bahwa lumpur yang muncrat merupakan fenomena alam.
Tentang penyebutan bencana alam atau bencana yang diakibatkan kecerobohan manusia (Lapindo) menjadi amat penting di sini, karena konsekuensinya sangat besar dan berarti. Jika dianggap bencana alam maka pemerintahlah yang akan menanggulangi termasuk ganti rugi kepada para korban. Sebaliknya jika dianggap bencana akibat kelalaian manusia saat pengeboran terjadi, maka Lapindo harus bertanggung jawab. Pemerintah tentu tetap berkewajiban membantu memfasilitas para korban memperoleh ganti rugi yang layak, apapun penyebab tragedi lumpur panas itu.
Pada 11 November 2008 Lapindo mengaku telah mengeluarkan dana pembelian tanah/bangunan warga korban sekitar Rp 1,8 triliun, namun menurut Ketua Paguyuban Renokenongo Sunarto ada 465 berkas yang belum dibayar. Presiden SBY terakhir bertemu Lapindo dan perwakilan korban pada 1 Desember 2008. Presiden memanggil Nirwan Bakrie karena kesal penanganan ganti rugi berlarut-larut. “Saya sudah merasa tidak nyaman dengan suasana ini,” ujar SBY. “Saya kecewa, Aceh saja bisa diselesaikan, kenapa ini tidak?” tambah presiden. Sebelumnya pada 27 November 2008, Presiden SBY memanggil Nirwan Bakrie dan mendesak Lapindo melunasi uang muka 20 persen ganti rugi sebesar Rp 49 miliar.
Di sinilah permasalahaannya. Lapindo tak sepenuh hati membayar ganti rugi para korban. Bahkan ketika kekayaan keluarga Bakrie tak tertandingi se-Indonesia, malah se-Asia Tenggara, tetapi tetap saja keluarga ini enggan berbagi. Kini Bakrie berdalih krisis ekonomi global yang menghantam bisnisnya. Masyarakat diminta maklum kepada keluarga Bakrie karena pembayaran kepada para korban yang telah dua setengah tahun berkubang dengan lumpur tersendat-sendat.
Dalam perspektif politik komunikasi, Lapindo berjuang keras dengan segala daya dan upaya termasuk tipu muslihat meyakinkan pemerintah dan masyarakat bahwa penyebab muncratnya lumpur panas karena faktor alam, dipicu oleh gempa Yogyakarta dua hari sebelumnya. Para korban, baik yang langsung terkena lumpur panas maupun mereka yang desanya terisolasi, kurang menganggap penting apa penyebab keluarnya lumpur. Yang penting adalah para korban harus dibayar kerugian mereka akibat lumpur yang menerjang kehidupan mereka.
Lapindo dengan kekuatan modal berupaya menguasai informasi untuk memengaruhi publik, sementara para korban yang tak memiliki apa-apa kecuali semangat bertahan hidup, berhasil menciptakan kejutan-kejutan yang membuat publik dan pemerintah cenderung berpihak kepada mereka. Sesungguhnya, para pemain/pelaku dalam politik komunikasi kasus bencana lumpur Lapindo tak hanya keluarga Bakrie yang kaya raya dan para korban yang miskin berkubang lumpur. Melainkan masih ada sederat pemain/pelaku yang mempunyai kepentingan politik komunikasi publik yang saling berbeda. Dapat disebut di sini para pemain/pelaku lainya adalah kelompok dunia usaha, negara/pemerintah, lembaga kepentingan politik, media massa, dan publik.
PARA PEMAIN/PELAKU:
Begitu bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur terjadi, muncullah para pemain/pelaku utama yang mempunyai kepentingan politik komunikasi sesuai kepentingannya. Setiap kelompok mencakup berbagai kelompok yang dapat mempunyai kepentingan yang berlainan, tetapi dapat mempengaruhi rencana/srategi/tindak politik komunikasi.
Mari kita sebutkan satu persatu siapa saja pemain atau pelaku yang berkepentingan;
Dunia usaha. Dalam kelompok ini terbagi menjadi dua. Pertama PT Lapindo Brantas sendiri yang menjadi “pelaku” utama tragedi lumpur, dan para pengusaha yang pabrik dan tempat usahanya langsung gulung tikar karena diterjang lumpur. Pertarungan dua kepentingan yang berbeda meski keduanya pelaku dunia usaha kurang terekspos di media massa. Berbeda dengan perselisihan antara Lapindo dengan korban masyarakat biasa. Ini bisa terjadi karena suksesnya tim lobi Lapindo meyakinkan para pengusaha pemilik pabrik yang menjadi korban lumpur. Mungkin saja, para pemilik pabrik menyadari atau mengakui bencana ini termasuk bencana alam, sehingga tak menuntut macam-macam terhadap Lapindo.
Negara/pemerintah. Secara nasional pemerintah diwakili oleh Presiden SBY. Namun ada lagi pemain yaitu DPR, Mahkamah Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Pengadilan Negeri. Kelimanya kadang tak sejalan atau mempunyai kepentingan yang sama. Presiden SBY telah kita ketahui sikapnya bagaimana dia geram menyaksikan betapa lambannya penyelesaian ganti rugi yang dilakukan Lapindo terhadap para korban. Di lain pihak, DPR yang notabene adalah wakil rakyat – termasuk rakyat yang tinggal di Sidoarjo – rupanya tak sepenuhnya pro rakyat. DPR ternyata lebih pro Lapindo karena menyimpulkan bahwa bencana lumpur Lapindo adalah karena fenomena alam, bukan kelalaian manusia. DPR sangat gegabah karena hanya mendengar para ahli yang pro Lapindo. Sementara Mahkamah Agung di sini pernah memainkan perannya dalam menolak permohonan uji materi Peraturan Presiden tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang diajukan para korban. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Jakarta Utara juga menolak gugatan Walhi dan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) terhadap Lapindo, Presiden, Menteri Migas, Menteri Lingkungan, pemerintah provinsi Jawa Timur, dan pemerintah kabupaten Sidoarjo.
Lembaga kepentingan politik. Di sini yang paling banyak berperan adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan atau koalisi LSM yang kemudian membentuk jaringan kerja (network). Selain itu, di kelompok ini ada pemain lain yaitu organisasi ahli geologi. Kelompok kepentingan dari kalangan LSM pada mulanya diperankan oleh LSM yang peduli lingkungan seperti Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan Greenpeace Indonesia. Mereka baik sendiri-sendiri maupun bersama para korban melakukan aksi menentang kecerobohan Lapindo dan menuntut perusahaan itu segera mengganti rugi para korban dan memperbaiki lingkungan yang rusak. Beberapa aksi yang menyedot perhatian publik misalnya mereka membawa lumpur dari Sidoarjo dan disebar di depan kantor Menko Kesra tempat Aburizal Bakrie berkantor. Sementara itu, para ahli geologi antara lain Rudi Rubiandini mantan Ketua Tim Investigasi Independen Lumpur Sidoarjo. Menurut Rudi, sesungguhnya saat awal bencana, masih ada kesempatan bagi Lapindo untuk mematikan semburan lumpur. Faktanya, semburan sempat teredam oleh lumpur berat yang dipompa ke dalam sumur. Belum semburan itu benar-benar dimatikan, sumur ditutup dengan semen dan bor dipotong, “Itu tindakan ceroboh dan teledor,” ujar Rudi. Prof. Richard Davies, ahli mud volcano Universitas Durham, Inggris, juga menyebut bencana lumpur Lapindo akibat kecelakaan, seperti yang ditulis di majalah Geological Society of America (GSA) edisi Maret 2008. Andang Bachtiar, mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia, juga menyebut bukan bencana alam. “Limpur yang digunakan untuk meredam kick terlalu kental sehingga tekanannya membikin dinding sumur pecah,” ujar Andang.
Media. Di sini juga terbelah menjadi dua atau bahkan tiga kelompok. Ada media yang sangat pro Lapindo karena mayoritas sahamnya dimiliki langsung oleh keluarga Bakrie yaitu – TV-One dan ANTV. Ada juga media yang anti-Lapindo, dan media yang berada di tengah (independen). Pada awal 2008 Lapindo melakukan kampanye besar-besaran. Tujuannya satu, meyakinkan publik bahwa bencana lumpur itu adalah karena fenomena alam yang dipicu gempa Yogyakarta. Sejumlah seminar di perguruan tinggi digelar. Iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik ditayangkan. Tak lupa beberapa geolog yang bisa ‘bekerjasama’ dihimpun untuk menyuarakan tragedi ini semata-mata bencana alam. Setidaknya dua stasiun televisi dikuasai Bakrie dan bersuara untuk kepentingan sang pemilik saham. Ada juga beberapa media yang bisa ‘dibeli’ atau ‘dibina’ oleh Lapindo. Salah satunya adalah media internet dan sms Newslink. Media non konvensional ini secara rutin mengirimkan pesan pendek yang isinya baik-baik tentang Lapindo ke sekitar 5.000 orang terpilih. Istilah yang digunakan Newslink bukan lumpur Lapindo melainkan lumpur Sidoarjo. Penyebutan istilah ini menandakan keberpihakan suatu media. Berbeda dengan Newslink, majalah Tempo adalah media independen yang telah beberapa kali menurunkan laporan utama mengenai bencana lumpur Lapindo dan bisnis keluarga Bakrie (“Sidoarjo Kritis” edisi 21-27 Agustus 2006, “Bermain Lumpur Lapindo” edisi 25 Februari-2 Maret 2008, “Siapa Peduli Bakrei” edisi 17-23 November 2008, dan “Korban Lumpur Lapindo Menagih Bukti Bukan Janji” edisi 8-14 Desember 2008). Sebagai media kritis dan independen bahkan menjadi barometer media di Indonesia, Tempo menjalankan fungsinya sebagai penyambung lidah publik dan para korban. Karena kegigihannya, Tempo kemudian digugat Aburizal Bakrie, saat menurunkan laporan utama “Siapa Peduli Bakrei” 17-23 November 2008, dengan gambar sampul wajah Aburizal Bakrie yang penuh angka berjatuhan seolah menandakan keruntuhannya. Salah satu yang menjadi keberatan Bakrie adalah adanya angka tripel 6 yang konon melambangkan setan! Tempo juga mengulas mengapa pemerintah perlu membantu Group Bakrie yang diterjang krisis finansial, sementara pada saat ia menjadi orang terkaya di Asia Tenggara, tak mempunyai itikad yang baik untuk menyelesaikan ganti rugi korban lumpur Lapindo yang menjadi tanggung jawab kelompok usaha itu.
Korban. Mereka warga Sidoarjo yang secara langsung maupun tak langsung terkena dampak semburan lumpur panas Lapindo. Mereka tinggal di wilayah desa Jatirejo (3.420 jiwa), Siring (4.240 jiwa), Kedungbendo (22.833 jiwa), dan Renokenongo (4.753 jiwa). Wilayah bencana kemudian meluas ke beberapa desa termasuk Kedungcangkring (3.818 jiwa), Pejarakan (1.609 jiwa), dan Besuki (3.499 jiwa). Ketika pada 30 November 2008 seribuan warga Siring, Jatirejo, Kedungbendo, dan Renokenongo berangkat ke Jakarta untuk mengelar unjuk rasa di depan Istana Negara, itu berarti telah dua setengah tahun para korban terkatung-katung. Selama itu banyak korban berjatuhan. Ada yang jadi sakit-sakitan lalu meninggal. Ada yang menjadi stres dan sakit jiwa. Ada pula yang kini menjadi pengemis karena tak ada pilihan. Sungguh lumpur telah mengubur masa depan mereka. Sebagai korban yang tak memiliki apa-apa kecuali semangat bertahan hidup, kadang menimbulkan kreativitas dalam melakukan unjuk rasa. Karena itu tak heran mereka tak bosan-bosannya berunjukrasa dengan berbagai cara dan gaya. Tujuannya satu, agar proses pembayaran ganti rugi dipercepat. Aksi mereka dari unjuk rasa di lokasi lumpur Lapindo sembari menutup jalan akses di situ, demo ke kantor bupati atau gubernur, sampai ‘nglurug’ ke Istana di Jakarta. Demo unik agar media massa memberitakan juga sering dilakukan misalnya mandi lumpur di dekat lokasi semburan, dan menyambangi rumah Aburizal Bakrie di Jakarta. Korban memang tak satu suara alias terpecah dalam beberapa kelompok. Namum mereka tetap didampingi oleh koalisi LSM, terutama yang bergerak di bidang lingkungan dan bantuan hukum.
PEMERINTAH VS LAPINDO:
Lapindo Kian Terdesak:
Sesungguhnya yang membuat akibat dari semburan lumpur Lapindo menjadi lebih parah dan semakin parah lagi adalah kesombongan para pakar geologi Indonesia (terutama yang pro-Lapindo), yang menolak semua tawaran dari luar negeri (ketika itu masih dapat ditangani dengan baik), dengan mengatakan bahwa bangsa Indonesia jangan dihina karena dapat menyelesaikan masalah itu sendiri.
Nasi sudah menjadi bubur. Mari kita simak Laporan dari DEC (Drilling Engineers Club). Laopran ini membawa kabar baik dan menggembirakan terutama buat para korban lumpur panas, dan mungkin juga buat pemerintah. Kabar itu datang dari jauh, negerinya Nelson Mandela, Afrika Selatan. Adalah keputusan AAPG (American Association of Petroleum Geologists) 2008 International Conference & Exhibition yang dilaksanakan di Cape Town, 26-29 Oktober 2008, yang dihadiri oleh ahli geologi seluruh dunia. Pada acara bergengsi ini disampaikan sekitar 600 makalah dalam 97 tema yang berbeda, dan terdapat 6 buah tema khusus yang sangat dianggap penting yaitu “Lusi Mud Volcano: Earthquake or Drilling Trigger”.
Apa keputusan konperensi terpandang bagi para ahli geologi seluruh dunia itu? Ternyata 42 ahli dunia berpendapat lumpur Lapindo Sidoarjo diakibatkan oleh kesalahan pemboran dan hanya 3 ahli yang setuju karena gempa bumi. Peserta konperensi sekitar 90 ahli tersebut tentunya memberikan opini yang netral dan obyektif datang tepat waktu. Pada pertemuan itu ahli geologi pro Lapindo juga hadir, mereka bahkan membagi-bagikan brosur enam halaman berwarna dengan kualitas luks yang menjelaskan tentang seluruh kegiatan yang telah dilakukan di lapangan kepada peserta konferensi.
Selama pertemuan, terdapat 4 (empat) pembicara yaitu :
1. Dr. Adriano Mazzini dari Unversitas Oslo seorang ahli Mud Vulcano yang selama ini sangat yakin dengan teori bahwa lumpur lapindo disebabkan oleh gempa Yogyakarta. 2. Nurrochmat Sawolo sebagai ahli pemboran dari Lapindo yang mengetahui seluk beluk pemboran di sumur Banjarpanji1 sejak persiapan, pelaksanaan sampai semburan terjadi di Sidoardjo, yang dibantu Bambang Istadi.
3. Seorang pembicara dari Universitas Curtin Australia yaitu Dr. Mark Tingay ahli gempa yang berpendapat bahwa energi gempa Yogyakarta terlalu kecil sebagai penyebab terjadinya semburan di Sidoardjo.
4. Prof. Richard Davies dari Universitas Durham Inggris ahli geologi yang bekerjasama dengan ahli pemboran Indonesia yang diwakili oleh Susila Lusiaga dan Rudi Rubiandini dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyampaikan secara detail dan jelas data-data dan bukti selama proses kejadian dilihat dari sisi operasi pemboran.
Tidak kurang 20 penanya ikut mempertajam materi diskusi yang mengarah pada penyebab yang sebenarnya, kemudian dilanjutkan dengan sesi perdebatan yang melibatkan seluruh opini yang berkembang dan dimoderatori oleh ahli geologi senior dari Australia. Acara berjalan sekitar 2,5 jam tersebut diakhiri dengan voting (pengambilan pendapat) oleh seluruh peserta yang hadir untuk memperoleh kepastian pendapat para ahli dunia tersebut dengan menggunakan metoda langsung angkat tangan.
Hasil dari voting tersebut menghasilkan 3 (tiga) suara yang mendukung gempa Yogya sebagai penyebab, 42 (empat puluh dua) suara menyatakan pemboran sebagai penyebab, 13 (tiga belas) suara menyatakan kombinasi gempa dan pemboran sebagai penyebab, dan 16 (enam belas suara) menyatakan belum bisa mengambil opini. Dengan kesimpulan ahli dunia seperti ini, tidak perlu diragukan dan didiskusikan lagi bahwa penyebab semburan lumpur di Sidoardjo adalah akibat kegiatan pemboran.
"Ini merupakan kesimpulan tertinggi tingkat dunia yang tak bisa dibantah," kata Rudi Rubiandini, geolog petroleum dari ITB, salah satu peserta. Rudi berpendapat, pemerintah Indonesia dapat menggunakan hasil konferensi itu sebagai bahan dalam menyelesaikan kasus lumpur Lapindo. Dia menegaskan, lembaga yang menyebabkan terjadinya semburan lumpur harus bertanggung jawab. Sejauh ini proses hukum kasus Lapindo menemui jalan buntu di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena tak cukup bukti.
Bagaimana tanggapan pemerintah dan Lapindo? Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Legowo, mengatakan pemerintah terbuka untuk menerima hasil rekomendasi terbaru itu. "Kami selalu terbuka untuk itu," kata Evita. Sementara itu, Senior Vice President PT Energi Mega Persada Lapindo, Bambang Istadi, menolak kesimpulan konferensi. Alasannya, pendapat tersebut tidak dikeluarkan seluruh geolog dunia. "Itu tidak mempresentasikan pendapat seluruh geolog di dunia," ujar Bambang
Sebelum hasil pertemuan geolog dunia di Cape Town, PT Lapindo Brantas pada 22 Oktober 2008 merilis siara pers, yang menyebutkan bahwa para geolog dalam pertemuan The Geological Society di London, Inggris (sebelum pertemuan Cape Town) menyimpulkan semburan lumpur Lapindo diakibatkan oleh mud volcano. Menurut Rudi, pertemuan London itu tak menghasilkan kesimpulan apa-apa. "Ahli geologi umum itu hanya berdiskusi, tidak menghasilkan kesimpulan." Menanggapi hal ini, Walhi menuding Lapindo telah berbohong kepada publik. "Ini proses pembohongan publik luar biasa," kata Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Walhi Muhammad Teguh Surya.
Pemerintah Menyerah?
Bagaimana membaca krisis keuangan global, menguntungkan atau merugikan Group Bakrie? Krisis finansial dunia ini tentu membuat kekayaan Bakrie terkuras, setidaknya dari orang paling kaya di Indonesia (2007), turun menjadi urutan keenam pada 2008. Namun dengan alasan krisis keuangan global ini pula, membuat PT Lapindo Brantas hanya mampu membayar uang ganti rugi kepada para korban lumpur Lapindo sebesar Rp 30 juta per bulan secara mencicil dan uang sewa rumah sebesar Rp 2,5 juta. Meskipun pemerintah sudah menekan Lapindo supaya harus membayar ganti rugi kepada para korban luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur, tetapi akhirnya pemerintah menyerah.
Ini adalah kompromi antara pemerintah, masyarakat, dan Lapindo, kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. “Kita sudah tekan Lapindo, kamu harus bisa membayar. Tapi memang dia sudah buka kartu, inilah semampu kami, bayar Rp 30 juta per bulan. Ya sudah harus kita terima," ujar Djoko Kirmanto di Istana Negara Jakarta.
Menurut Djoko, kesepakatan yang dicapai di Sekretariat Negara 2 Desember 2008 --antara warga korban dan Nirwan Bakrie disaksikan Presiden SBY -- itu diterima semua oleh warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas). Sedangkan, kepada warga di luar itu yang menolak kesepakatan tersebut diimbaunya untuk menerima kesepakatan tersebut. Dia khawatir, bila kesepakatan itu ditolak, maka maksimum yang diterima para korban lumpur Lapindo tidak akan lebih dari yang sudah mereka terima. Apalagi, setelah kesepakatan itu, tidak akan ada negosiasi ulang.
Itulah yang bisa dilakukan oleh Lapindo untuk membayar kepada masyarakat. Kesepakatan yang dicapai itu, masih menurut Djoko, sudah sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No 14 Tahun 2007. Sedangkan, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa yang hadir pada negosiasi itu menjelaskan, pemerintah tidak bisa memaksa Lapindo untuk membayar lebih dari yang disepakati itu. Pasalnya, perusahan milik keluarga Bakrie itu sedang mengalami kesulitan akibat krisis keuangan global saat ini.
Tampaknya usaha Group Bakrie melakukan kampanye besar-besaran ke publik bahwa penyebab bencana lumpur yang muncrat di Sidoarjo adalah karena fenomena alam belaka tak berhasil meyakinkan publik dan pemerintah. Karena itu pemerintah, dalam hal ini Presiden SBY, tetap konsisten menekan Lapindo membayar ganti rugi kepada para korban. “Beruntung” Lapindo terkena dampak krisis finansial internasional sehingga ada alasan pundi-pundinya berkurang drastis dan pemerintah memaklumi keadaan itu. Konsekuensinya terjadi kesepakatan win-win solution antara Lapindo dan korban yang difasilitasi pemerintah.
KESIMPULAN
Politik komunikasi yang dilakukan Lapindo dengan mengaburkan fakta sebenarnya tentang kejadian muncratnya lumpur panas Lapindo adalah demi kepentingan bisnis Group Bakrie. Meskipiun kelompok usaha ini sangat kaya, bahkan dari sisi politik mempunyai jaringan di pusat kekuasaan, namun mengingat dahsyatnya dampak yang ditimbulkan dari bencana lumpur Lapindo, menjadikan modal kapital dan kekuasaan tetap kurang. Kampanye Bakrie pada mulanya efektif, termasuk mempengaruhi DPR, namun akhirnya tak mampu membendung kenyataan bahwa itu semua karena kecerobohan Lapindo bukan bencana alam.
Pemerintah yang baik tentu akan berpihak kepada rakyatnya, meski sebagai pribadi dan kelompok usaha, Bakrie adalah salah satu penyumbang terbesar bari kemenangan pasangan SBY-JK saat mereka meraih kursi Presiden 2004. Pada akhirnya toh Presiden SBY harus memilih untuk lebih tegas kepada Group Bakrie ketika korban tak tertanggulangi selama dua setengah tahun. Bagi Presiden SBY, menekan Bakrie dan mengahasilkan kesepakatan dengan para korban, selain sudah merupakan tugasnya sebagai presiden, juga credit point tersendiri pada saat menjelang akhir jabatannya. Dalam perspektif komunikasi politik, memerintah adalah kampanye. Artinya, bagi incumbent, melakukan sesuatu yang baik pada masa jabatan berlangsung adalah kampanye untuk pemilu berikutnya.
Kasus Lapindo memberi pelajaran kepada kita bahwa politik komunikasi dunia usaha selalu mencari untung. Politik komunikasi pemerintah adalah menjaga kestabilan dan keamanan demi pelaksanaan pembangunan. Pemerintah tak ingin kasus Lapindo menjadi sumber keresahan. Di luar itu, kelompok penekan seperti LSM selalu mengkritisi jalannya pemerintahan dan dunia usaha agar transparan, akuntable dan good governance (good corporete governance, unuk perusahaan). Media massa yang dianggap sebagai pilar keempat demokrasi, ternyata ada yang masih ideal dan independen, namun banyak yang sudah menjadi institusi bisnis semata-mata. Yang terakhir ini akan membela kepentingan bisnis pemilik modal. Bagaimana dengan publik dan korban? Mereka masih rentan, namun kini mereka bebas bersuara termasuk melakukan aksi unjuk rasa dengan segala cara dan rupa!
Daftar Bacaan:
Fotokopian dan power point bahan kuliah Politik Komunikasi.
“Bermain Lumpur Lapindo” Majalah Tempo edisi 25 Februari-2 Maret 2008
“Mencari Indonesia” Majalah Tempo edisi 27 Oktober-2 November 2008
“Siapa Peduli Bakrei” Majalah Tempo edisi 17-23 November 2008“Korban Lumpur Lapindo Menagih Bukti Bukan Janji” Majalah Tempo edisi 8-14
PENDAHULUAN:
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – M Jusuf Kalla (SBY-JK) ditandai dengan berbagai bencana besar. Diawali gempa dan tsunami dahsyat di Aceh dan Sumatera Utara pada 26 Desember 2004, kemudian pada 27 Mei 2006 gempa besar menerpa Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Di luar itu bencana banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, terjadi dalam skala besar, sampai beberapa kali kecelakaan lalu lintas – termasuk hilangnya pesawat Adam Air dan jatuhnya Mandala Air di Polonia Medan – melengkapi masa pemerintahan SBY-JK yang penuh musibah. Umumnya bencana, seperti gempa, tsunami, kebakaran, atau banjir, berlangsung tak lama, termasuk dampak yang ditimbulkan. Namun ada satu tragedi atau bencana di mana sejak prahara itu terjadi sampai hari ini terus berlangsung, begitu juga dampak yang ditimbulkan bagi korban. Bencana atau tragedi itu tak lain adalah muncratnya lumpur panas di area pengeboran PT Lapindo Brantas, Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Mei 2006.
Dalam sepekan, lumpur itu menelan 10 hektar kawasan dan melenyapkan jalan tol Gempol-Surabaya yang berjarak 200 meter dari pusat semburan. Hari demi hari, bulan demi bulan, lumpur panas itu telah menggenangi 345 hektar di wilayah desa Jatirejo (3.420 jiwa), Siring (4.240 jiwa), Kedungbendo (22.833 jiwa), dan Renokenongo (4.753 jiwa). Wilayah bencana kemudian meluas hingga membuat mati beberapa desa termasuk Kedungcangkring (3.818 jiwa), Pejarakan (1.609 jiwa), dan Besuki (3.499 jiwa).
Skala bencana yang amat besar ini membuat Kementerian Lingkungan Hidup meminta Lapindo bertanggung jawab pada 9 Juni 2006. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, tak mau ketinggalan, pada 18 Juni 2006, mengatakan Lapindo harus bertanggung jawab. Presiden SBY pada 8 September 2006 membentuk tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo, dengan masa kerja enam bulan. Tim ini kemudian diperpanjang masa tugasnya selama sebulan, kemudian Presiden SBY membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, yang dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2007.
Di tengah maraknya aksi menentang kelambatan pemerintah dan Lapindo menangani luapan lumpur dan para korban, DPR menyetujui pembentukan Tim Pengawas Penyelesaian Kasus Lumpur Lapindo, dengan masa kerja tiga bulan. Tim DPR yang bekerja hanya tiga bulan ini – ditengarai hanya bertemu dengan ahli geologi yang pro Lapindo – bisa dipastikan hasilnya menguntungkan Lapindo. Maka tak aneh, pada 19 Februari 2008, dalam rapat paripurna DPR, setelah mendengarkan laporan dari tim tadi, DPR menyebutkan bahwa lumpur yang muncrat merupakan fenomena alam.
Tentang penyebutan bencana alam atau bencana yang diakibatkan kecerobohan manusia (Lapindo) menjadi amat penting di sini, karena konsekuensinya sangat besar dan berarti. Jika dianggap bencana alam maka pemerintahlah yang akan menanggulangi termasuk ganti rugi kepada para korban. Sebaliknya jika dianggap bencana akibat kelalaian manusia saat pengeboran terjadi, maka Lapindo harus bertanggung jawab. Pemerintah tentu tetap berkewajiban membantu memfasilitas para korban memperoleh ganti rugi yang layak, apapun penyebab tragedi lumpur panas itu.
Pada 11 November 2008 Lapindo mengaku telah mengeluarkan dana pembelian tanah/bangunan warga korban sekitar Rp 1,8 triliun, namun menurut Ketua Paguyuban Renokenongo Sunarto ada 465 berkas yang belum dibayar. Presiden SBY terakhir bertemu Lapindo dan perwakilan korban pada 1 Desember 2008. Presiden memanggil Nirwan Bakrie karena kesal penanganan ganti rugi berlarut-larut. “Saya sudah merasa tidak nyaman dengan suasana ini,” ujar SBY. “Saya kecewa, Aceh saja bisa diselesaikan, kenapa ini tidak?” tambah presiden. Sebelumnya pada 27 November 2008, Presiden SBY memanggil Nirwan Bakrie dan mendesak Lapindo melunasi uang muka 20 persen ganti rugi sebesar Rp 49 miliar.
Di sinilah permasalahaannya. Lapindo tak sepenuh hati membayar ganti rugi para korban. Bahkan ketika kekayaan keluarga Bakrie tak tertandingi se-Indonesia, malah se-Asia Tenggara, tetapi tetap saja keluarga ini enggan berbagi. Kini Bakrie berdalih krisis ekonomi global yang menghantam bisnisnya. Masyarakat diminta maklum kepada keluarga Bakrie karena pembayaran kepada para korban yang telah dua setengah tahun berkubang dengan lumpur tersendat-sendat.
Dalam perspektif politik komunikasi, Lapindo berjuang keras dengan segala daya dan upaya termasuk tipu muslihat meyakinkan pemerintah dan masyarakat bahwa penyebab muncratnya lumpur panas karena faktor alam, dipicu oleh gempa Yogyakarta dua hari sebelumnya. Para korban, baik yang langsung terkena lumpur panas maupun mereka yang desanya terisolasi, kurang menganggap penting apa penyebab keluarnya lumpur. Yang penting adalah para korban harus dibayar kerugian mereka akibat lumpur yang menerjang kehidupan mereka.
Lapindo dengan kekuatan modal berupaya menguasai informasi untuk memengaruhi publik, sementara para korban yang tak memiliki apa-apa kecuali semangat bertahan hidup, berhasil menciptakan kejutan-kejutan yang membuat publik dan pemerintah cenderung berpihak kepada mereka. Sesungguhnya, para pemain/pelaku dalam politik komunikasi kasus bencana lumpur Lapindo tak hanya keluarga Bakrie yang kaya raya dan para korban yang miskin berkubang lumpur. Melainkan masih ada sederat pemain/pelaku yang mempunyai kepentingan politik komunikasi publik yang saling berbeda. Dapat disebut di sini para pemain/pelaku lainya adalah kelompok dunia usaha, negara/pemerintah, lembaga kepentingan politik, media massa, dan publik.
PARA PEMAIN/PELAKU:
Begitu bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur terjadi, muncullah para pemain/pelaku utama yang mempunyai kepentingan politik komunikasi sesuai kepentingannya. Setiap kelompok mencakup berbagai kelompok yang dapat mempunyai kepentingan yang berlainan, tetapi dapat mempengaruhi rencana/srategi/tindak politik komunikasi.
Mari kita sebutkan satu persatu siapa saja pemain atau pelaku yang berkepentingan;
Dunia usaha. Dalam kelompok ini terbagi menjadi dua. Pertama PT Lapindo Brantas sendiri yang menjadi “pelaku” utama tragedi lumpur, dan para pengusaha yang pabrik dan tempat usahanya langsung gulung tikar karena diterjang lumpur. Pertarungan dua kepentingan yang berbeda meski keduanya pelaku dunia usaha kurang terekspos di media massa. Berbeda dengan perselisihan antara Lapindo dengan korban masyarakat biasa. Ini bisa terjadi karena suksesnya tim lobi Lapindo meyakinkan para pengusaha pemilik pabrik yang menjadi korban lumpur. Mungkin saja, para pemilik pabrik menyadari atau mengakui bencana ini termasuk bencana alam, sehingga tak menuntut macam-macam terhadap Lapindo.
Negara/pemerintah. Secara nasional pemerintah diwakili oleh Presiden SBY. Namun ada lagi pemain yaitu DPR, Mahkamah Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Pengadilan Negeri. Kelimanya kadang tak sejalan atau mempunyai kepentingan yang sama. Presiden SBY telah kita ketahui sikapnya bagaimana dia geram menyaksikan betapa lambannya penyelesaian ganti rugi yang dilakukan Lapindo terhadap para korban. Di lain pihak, DPR yang notabene adalah wakil rakyat – termasuk rakyat yang tinggal di Sidoarjo – rupanya tak sepenuhnya pro rakyat. DPR ternyata lebih pro Lapindo karena menyimpulkan bahwa bencana lumpur Lapindo adalah karena fenomena alam, bukan kelalaian manusia. DPR sangat gegabah karena hanya mendengar para ahli yang pro Lapindo. Sementara Mahkamah Agung di sini pernah memainkan perannya dalam menolak permohonan uji materi Peraturan Presiden tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang diajukan para korban. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Jakarta Utara juga menolak gugatan Walhi dan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) terhadap Lapindo, Presiden, Menteri Migas, Menteri Lingkungan, pemerintah provinsi Jawa Timur, dan pemerintah kabupaten Sidoarjo.
Lembaga kepentingan politik. Di sini yang paling banyak berperan adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan atau koalisi LSM yang kemudian membentuk jaringan kerja (network). Selain itu, di kelompok ini ada pemain lain yaitu organisasi ahli geologi. Kelompok kepentingan dari kalangan LSM pada mulanya diperankan oleh LSM yang peduli lingkungan seperti Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan Greenpeace Indonesia. Mereka baik sendiri-sendiri maupun bersama para korban melakukan aksi menentang kecerobohan Lapindo dan menuntut perusahaan itu segera mengganti rugi para korban dan memperbaiki lingkungan yang rusak. Beberapa aksi yang menyedot perhatian publik misalnya mereka membawa lumpur dari Sidoarjo dan disebar di depan kantor Menko Kesra tempat Aburizal Bakrie berkantor. Sementara itu, para ahli geologi antara lain Rudi Rubiandini mantan Ketua Tim Investigasi Independen Lumpur Sidoarjo. Menurut Rudi, sesungguhnya saat awal bencana, masih ada kesempatan bagi Lapindo untuk mematikan semburan lumpur. Faktanya, semburan sempat teredam oleh lumpur berat yang dipompa ke dalam sumur. Belum semburan itu benar-benar dimatikan, sumur ditutup dengan semen dan bor dipotong, “Itu tindakan ceroboh dan teledor,” ujar Rudi. Prof. Richard Davies, ahli mud volcano Universitas Durham, Inggris, juga menyebut bencana lumpur Lapindo akibat kecelakaan, seperti yang ditulis di majalah Geological Society of America (GSA) edisi Maret 2008. Andang Bachtiar, mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia, juga menyebut bukan bencana alam. “Limpur yang digunakan untuk meredam kick terlalu kental sehingga tekanannya membikin dinding sumur pecah,” ujar Andang.
Media. Di sini juga terbelah menjadi dua atau bahkan tiga kelompok. Ada media yang sangat pro Lapindo karena mayoritas sahamnya dimiliki langsung oleh keluarga Bakrie yaitu – TV-One dan ANTV. Ada juga media yang anti-Lapindo, dan media yang berada di tengah (independen). Pada awal 2008 Lapindo melakukan kampanye besar-besaran. Tujuannya satu, meyakinkan publik bahwa bencana lumpur itu adalah karena fenomena alam yang dipicu gempa Yogyakarta. Sejumlah seminar di perguruan tinggi digelar. Iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik ditayangkan. Tak lupa beberapa geolog yang bisa ‘bekerjasama’ dihimpun untuk menyuarakan tragedi ini semata-mata bencana alam. Setidaknya dua stasiun televisi dikuasai Bakrie dan bersuara untuk kepentingan sang pemilik saham. Ada juga beberapa media yang bisa ‘dibeli’ atau ‘dibina’ oleh Lapindo. Salah satunya adalah media internet dan sms Newslink. Media non konvensional ini secara rutin mengirimkan pesan pendek yang isinya baik-baik tentang Lapindo ke sekitar 5.000 orang terpilih. Istilah yang digunakan Newslink bukan lumpur Lapindo melainkan lumpur Sidoarjo. Penyebutan istilah ini menandakan keberpihakan suatu media. Berbeda dengan Newslink, majalah Tempo adalah media independen yang telah beberapa kali menurunkan laporan utama mengenai bencana lumpur Lapindo dan bisnis keluarga Bakrie (“Sidoarjo Kritis” edisi 21-27 Agustus 2006, “Bermain Lumpur Lapindo” edisi 25 Februari-2 Maret 2008, “Siapa Peduli Bakrei” edisi 17-23 November 2008, dan “Korban Lumpur Lapindo Menagih Bukti Bukan Janji” edisi 8-14 Desember 2008). Sebagai media kritis dan independen bahkan menjadi barometer media di Indonesia, Tempo menjalankan fungsinya sebagai penyambung lidah publik dan para korban. Karena kegigihannya, Tempo kemudian digugat Aburizal Bakrie, saat menurunkan laporan utama “Siapa Peduli Bakrei” 17-23 November 2008, dengan gambar sampul wajah Aburizal Bakrie yang penuh angka berjatuhan seolah menandakan keruntuhannya. Salah satu yang menjadi keberatan Bakrie adalah adanya angka tripel 6 yang konon melambangkan setan! Tempo juga mengulas mengapa pemerintah perlu membantu Group Bakrie yang diterjang krisis finansial, sementara pada saat ia menjadi orang terkaya di Asia Tenggara, tak mempunyai itikad yang baik untuk menyelesaikan ganti rugi korban lumpur Lapindo yang menjadi tanggung jawab kelompok usaha itu.
Korban. Mereka warga Sidoarjo yang secara langsung maupun tak langsung terkena dampak semburan lumpur panas Lapindo. Mereka tinggal di wilayah desa Jatirejo (3.420 jiwa), Siring (4.240 jiwa), Kedungbendo (22.833 jiwa), dan Renokenongo (4.753 jiwa). Wilayah bencana kemudian meluas ke beberapa desa termasuk Kedungcangkring (3.818 jiwa), Pejarakan (1.609 jiwa), dan Besuki (3.499 jiwa). Ketika pada 30 November 2008 seribuan warga Siring, Jatirejo, Kedungbendo, dan Renokenongo berangkat ke Jakarta untuk mengelar unjuk rasa di depan Istana Negara, itu berarti telah dua setengah tahun para korban terkatung-katung. Selama itu banyak korban berjatuhan. Ada yang jadi sakit-sakitan lalu meninggal. Ada yang menjadi stres dan sakit jiwa. Ada pula yang kini menjadi pengemis karena tak ada pilihan. Sungguh lumpur telah mengubur masa depan mereka. Sebagai korban yang tak memiliki apa-apa kecuali semangat bertahan hidup, kadang menimbulkan kreativitas dalam melakukan unjuk rasa. Karena itu tak heran mereka tak bosan-bosannya berunjukrasa dengan berbagai cara dan gaya. Tujuannya satu, agar proses pembayaran ganti rugi dipercepat. Aksi mereka dari unjuk rasa di lokasi lumpur Lapindo sembari menutup jalan akses di situ, demo ke kantor bupati atau gubernur, sampai ‘nglurug’ ke Istana di Jakarta. Demo unik agar media massa memberitakan juga sering dilakukan misalnya mandi lumpur di dekat lokasi semburan, dan menyambangi rumah Aburizal Bakrie di Jakarta. Korban memang tak satu suara alias terpecah dalam beberapa kelompok. Namum mereka tetap didampingi oleh koalisi LSM, terutama yang bergerak di bidang lingkungan dan bantuan hukum.
PEMERINTAH VS LAPINDO:
Lapindo Kian Terdesak:
Sesungguhnya yang membuat akibat dari semburan lumpur Lapindo menjadi lebih parah dan semakin parah lagi adalah kesombongan para pakar geologi Indonesia (terutama yang pro-Lapindo), yang menolak semua tawaran dari luar negeri (ketika itu masih dapat ditangani dengan baik), dengan mengatakan bahwa bangsa Indonesia jangan dihina karena dapat menyelesaikan masalah itu sendiri.
Nasi sudah menjadi bubur. Mari kita simak Laporan dari DEC (Drilling Engineers Club). Laopran ini membawa kabar baik dan menggembirakan terutama buat para korban lumpur panas, dan mungkin juga buat pemerintah. Kabar itu datang dari jauh, negerinya Nelson Mandela, Afrika Selatan. Adalah keputusan AAPG (American Association of Petroleum Geologists) 2008 International Conference & Exhibition yang dilaksanakan di Cape Town, 26-29 Oktober 2008, yang dihadiri oleh ahli geologi seluruh dunia. Pada acara bergengsi ini disampaikan sekitar 600 makalah dalam 97 tema yang berbeda, dan terdapat 6 buah tema khusus yang sangat dianggap penting yaitu “Lusi Mud Volcano: Earthquake or Drilling Trigger”.
Apa keputusan konperensi terpandang bagi para ahli geologi seluruh dunia itu? Ternyata 42 ahli dunia berpendapat lumpur Lapindo Sidoarjo diakibatkan oleh kesalahan pemboran dan hanya 3 ahli yang setuju karena gempa bumi. Peserta konperensi sekitar 90 ahli tersebut tentunya memberikan opini yang netral dan obyektif datang tepat waktu. Pada pertemuan itu ahli geologi pro Lapindo juga hadir, mereka bahkan membagi-bagikan brosur enam halaman berwarna dengan kualitas luks yang menjelaskan tentang seluruh kegiatan yang telah dilakukan di lapangan kepada peserta konferensi.
Selama pertemuan, terdapat 4 (empat) pembicara yaitu :
1. Dr. Adriano Mazzini dari Unversitas Oslo seorang ahli Mud Vulcano yang selama ini sangat yakin dengan teori bahwa lumpur lapindo disebabkan oleh gempa Yogyakarta. 2. Nurrochmat Sawolo sebagai ahli pemboran dari Lapindo yang mengetahui seluk beluk pemboran di sumur Banjarpanji1 sejak persiapan, pelaksanaan sampai semburan terjadi di Sidoardjo, yang dibantu Bambang Istadi.
3. Seorang pembicara dari Universitas Curtin Australia yaitu Dr. Mark Tingay ahli gempa yang berpendapat bahwa energi gempa Yogyakarta terlalu kecil sebagai penyebab terjadinya semburan di Sidoardjo.
4. Prof. Richard Davies dari Universitas Durham Inggris ahli geologi yang bekerjasama dengan ahli pemboran Indonesia yang diwakili oleh Susila Lusiaga dan Rudi Rubiandini dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyampaikan secara detail dan jelas data-data dan bukti selama proses kejadian dilihat dari sisi operasi pemboran.
Tidak kurang 20 penanya ikut mempertajam materi diskusi yang mengarah pada penyebab yang sebenarnya, kemudian dilanjutkan dengan sesi perdebatan yang melibatkan seluruh opini yang berkembang dan dimoderatori oleh ahli geologi senior dari Australia. Acara berjalan sekitar 2,5 jam tersebut diakhiri dengan voting (pengambilan pendapat) oleh seluruh peserta yang hadir untuk memperoleh kepastian pendapat para ahli dunia tersebut dengan menggunakan metoda langsung angkat tangan.
Hasil dari voting tersebut menghasilkan 3 (tiga) suara yang mendukung gempa Yogya sebagai penyebab, 42 (empat puluh dua) suara menyatakan pemboran sebagai penyebab, 13 (tiga belas) suara menyatakan kombinasi gempa dan pemboran sebagai penyebab, dan 16 (enam belas suara) menyatakan belum bisa mengambil opini. Dengan kesimpulan ahli dunia seperti ini, tidak perlu diragukan dan didiskusikan lagi bahwa penyebab semburan lumpur di Sidoardjo adalah akibat kegiatan pemboran.
"Ini merupakan kesimpulan tertinggi tingkat dunia yang tak bisa dibantah," kata Rudi Rubiandini, geolog petroleum dari ITB, salah satu peserta. Rudi berpendapat, pemerintah Indonesia dapat menggunakan hasil konferensi itu sebagai bahan dalam menyelesaikan kasus lumpur Lapindo. Dia menegaskan, lembaga yang menyebabkan terjadinya semburan lumpur harus bertanggung jawab. Sejauh ini proses hukum kasus Lapindo menemui jalan buntu di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena tak cukup bukti.
Bagaimana tanggapan pemerintah dan Lapindo? Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Legowo, mengatakan pemerintah terbuka untuk menerima hasil rekomendasi terbaru itu. "Kami selalu terbuka untuk itu," kata Evita. Sementara itu, Senior Vice President PT Energi Mega Persada Lapindo, Bambang Istadi, menolak kesimpulan konferensi. Alasannya, pendapat tersebut tidak dikeluarkan seluruh geolog dunia. "Itu tidak mempresentasikan pendapat seluruh geolog di dunia," ujar Bambang
Sebelum hasil pertemuan geolog dunia di Cape Town, PT Lapindo Brantas pada 22 Oktober 2008 merilis siara pers, yang menyebutkan bahwa para geolog dalam pertemuan The Geological Society di London, Inggris (sebelum pertemuan Cape Town) menyimpulkan semburan lumpur Lapindo diakibatkan oleh mud volcano. Menurut Rudi, pertemuan London itu tak menghasilkan kesimpulan apa-apa. "Ahli geologi umum itu hanya berdiskusi, tidak menghasilkan kesimpulan." Menanggapi hal ini, Walhi menuding Lapindo telah berbohong kepada publik. "Ini proses pembohongan publik luar biasa," kata Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Walhi Muhammad Teguh Surya.
Pemerintah Menyerah?
Bagaimana membaca krisis keuangan global, menguntungkan atau merugikan Group Bakrie? Krisis finansial dunia ini tentu membuat kekayaan Bakrie terkuras, setidaknya dari orang paling kaya di Indonesia (2007), turun menjadi urutan keenam pada 2008. Namun dengan alasan krisis keuangan global ini pula, membuat PT Lapindo Brantas hanya mampu membayar uang ganti rugi kepada para korban lumpur Lapindo sebesar Rp 30 juta per bulan secara mencicil dan uang sewa rumah sebesar Rp 2,5 juta. Meskipun pemerintah sudah menekan Lapindo supaya harus membayar ganti rugi kepada para korban luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur, tetapi akhirnya pemerintah menyerah.
Ini adalah kompromi antara pemerintah, masyarakat, dan Lapindo, kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. “Kita sudah tekan Lapindo, kamu harus bisa membayar. Tapi memang dia sudah buka kartu, inilah semampu kami, bayar Rp 30 juta per bulan. Ya sudah harus kita terima," ujar Djoko Kirmanto di Istana Negara Jakarta.
Menurut Djoko, kesepakatan yang dicapai di Sekretariat Negara 2 Desember 2008 --antara warga korban dan Nirwan Bakrie disaksikan Presiden SBY -- itu diterima semua oleh warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas). Sedangkan, kepada warga di luar itu yang menolak kesepakatan tersebut diimbaunya untuk menerima kesepakatan tersebut. Dia khawatir, bila kesepakatan itu ditolak, maka maksimum yang diterima para korban lumpur Lapindo tidak akan lebih dari yang sudah mereka terima. Apalagi, setelah kesepakatan itu, tidak akan ada negosiasi ulang.
Itulah yang bisa dilakukan oleh Lapindo untuk membayar kepada masyarakat. Kesepakatan yang dicapai itu, masih menurut Djoko, sudah sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No 14 Tahun 2007. Sedangkan, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa yang hadir pada negosiasi itu menjelaskan, pemerintah tidak bisa memaksa Lapindo untuk membayar lebih dari yang disepakati itu. Pasalnya, perusahan milik keluarga Bakrie itu sedang mengalami kesulitan akibat krisis keuangan global saat ini.
Tampaknya usaha Group Bakrie melakukan kampanye besar-besaran ke publik bahwa penyebab bencana lumpur yang muncrat di Sidoarjo adalah karena fenomena alam belaka tak berhasil meyakinkan publik dan pemerintah. Karena itu pemerintah, dalam hal ini Presiden SBY, tetap konsisten menekan Lapindo membayar ganti rugi kepada para korban. “Beruntung” Lapindo terkena dampak krisis finansial internasional sehingga ada alasan pundi-pundinya berkurang drastis dan pemerintah memaklumi keadaan itu. Konsekuensinya terjadi kesepakatan win-win solution antara Lapindo dan korban yang difasilitasi pemerintah.
KESIMPULAN
Politik komunikasi yang dilakukan Lapindo dengan mengaburkan fakta sebenarnya tentang kejadian muncratnya lumpur panas Lapindo adalah demi kepentingan bisnis Group Bakrie. Meskipiun kelompok usaha ini sangat kaya, bahkan dari sisi politik mempunyai jaringan di pusat kekuasaan, namun mengingat dahsyatnya dampak yang ditimbulkan dari bencana lumpur Lapindo, menjadikan modal kapital dan kekuasaan tetap kurang. Kampanye Bakrie pada mulanya efektif, termasuk mempengaruhi DPR, namun akhirnya tak mampu membendung kenyataan bahwa itu semua karena kecerobohan Lapindo bukan bencana alam.
Pemerintah yang baik tentu akan berpihak kepada rakyatnya, meski sebagai pribadi dan kelompok usaha, Bakrie adalah salah satu penyumbang terbesar bari kemenangan pasangan SBY-JK saat mereka meraih kursi Presiden 2004. Pada akhirnya toh Presiden SBY harus memilih untuk lebih tegas kepada Group Bakrie ketika korban tak tertanggulangi selama dua setengah tahun. Bagi Presiden SBY, menekan Bakrie dan mengahasilkan kesepakatan dengan para korban, selain sudah merupakan tugasnya sebagai presiden, juga credit point tersendiri pada saat menjelang akhir jabatannya. Dalam perspektif komunikasi politik, memerintah adalah kampanye. Artinya, bagi incumbent, melakukan sesuatu yang baik pada masa jabatan berlangsung adalah kampanye untuk pemilu berikutnya.
Kasus Lapindo memberi pelajaran kepada kita bahwa politik komunikasi dunia usaha selalu mencari untung. Politik komunikasi pemerintah adalah menjaga kestabilan dan keamanan demi pelaksanaan pembangunan. Pemerintah tak ingin kasus Lapindo menjadi sumber keresahan. Di luar itu, kelompok penekan seperti LSM selalu mengkritisi jalannya pemerintahan dan dunia usaha agar transparan, akuntable dan good governance (good corporete governance, unuk perusahaan). Media massa yang dianggap sebagai pilar keempat demokrasi, ternyata ada yang masih ideal dan independen, namun banyak yang sudah menjadi institusi bisnis semata-mata. Yang terakhir ini akan membela kepentingan bisnis pemilik modal. Bagaimana dengan publik dan korban? Mereka masih rentan, namun kini mereka bebas bersuara termasuk melakukan aksi unjuk rasa dengan segala cara dan rupa!
Daftar Bacaan:
Fotokopian dan power point bahan kuliah Politik Komunikasi.
“Bermain Lumpur Lapindo” Majalah Tempo edisi 25 Februari-2 Maret 2008
“Mencari Indonesia” Majalah Tempo edisi 27 Oktober-2 November 2008
“Siapa Peduli Bakrei” Majalah Tempo edisi 17-23 November 2008“Korban Lumpur Lapindo Menagih Bukti Bukan Janji” Majalah Tempo edisi 8-14
Senin, 03 November 2008
Stockhlom Syndrome atau Sleeping with Enemy?
Pada sebuah acara debat di SCTV sekitar sebulan lalu, berhadapan dua kelompok aktivis. Kelompok pertama, aktivis calon anggota DPR, Budiman Sujatmiko (PDI-P), Dita Indah Sari (PBR), dan Pius Lustrilanang (Partai Gerindra). Kelompok kedua, aktivis yang masih di ‘jalan’, Yeni Rosa Damayanti (aktivis perempuan), Hendrik Sirait (Ketua PBHI Jakarta), dan Sanggap (mantan aktivis Forkot).
Kelompok pertama menganggap masuknya aktivis ke senayan tak akan mampu mengubah keadaan, dan dipastikan mereka akan larut dalam budaya Senayan, tak mementingkan rakyat melainkan partai dan kekuasaan. Kelompok kedua berdalih justru perjuangan paling tepat adalah di parlemen. “Senayan adalah perluasan medan perjuangan, bukan meninggalkan rakyat di jalan”, kata Dita Indah Sari. Yang menarik adalah ketika Hendrik Sirait menyatakan keberadaan Pius Lustrilanang di Partai Gerindra (kendaraan politik Prabowo Subianto) merupakan praktek Stockhlom Syndrome. Betulkah?
Para psikolog mengidentifikasikan Stockhlom Syndrome sebagai peristiwa di mana korban penculikan, penindasan, atau penganiayaan jatuh cinta kepada orang yang melakukan kekerasan terhadapnya. Menurut teori psikoanalisa, ini adalah salah satu bentuk upaya pembelaan diri sang korban. Sandera memberikan tanda-tanda kesetiaan kepada penyandera, tidak memedulikan bahaya (atau risiko) yang telah dialami sandera itu.
Sindrom ini dinamai berdasarkan kejadian perampokan Kreditbanken di Stockholm. Perampok bank menyandera karyawan bank dari 23 Agustus sampai 28 Agustus pada 1973. Dalam kasus ini, korban menjadi secara emosional menyayangi penyandera, bahkan membela mereka. Istilah sindrom Stockholm pertama kali dicetuskan kriminolog dan psikiater Nils Bejerot, yang membantu polisi saat perampokan. Ada lagi istilah Lima Syndrome. Sindrom Lima adalah kebalikan dari sindrom Stockholm, di mana justru penyandera yang memiliki ketertarikan emosional terhadap sandera-nya. Penyandera menjadi lebih simpatik, dan bahkan merasa membutuhkan sandera-nya.
Apakah hubungan Pius Lustrilanang dan Prabowo Subianto Stockhlom Syndrome? Pius diculik oleh Tim Mawar Kopassus. Ia cukup ‘beruntung’ karena dibebaskan dalam keadaan hidup. Setelah sempat berkampanye anti militerisme di Eropa, Pius kemudian kembali ke Indonesia. Mantan aktivis Aldera ini lalu bergabung dengan PDI-P, PDP dan pada akhirnya menjadi calon anggota DPR dari Partai Gerindra. Pertemuan dengan Prabowo pertama bukan di Partai Gerindra melainkan pada akhir 1999, di Kuala Lumpur. Saat itu mantan komandan Kopassus itu berkata kepada Pius, “Saya hanya prajurit. Tugas saya memenuhi perintah. Diantaranya adalah menculik kamu”.
Kini antara korban dan ‘dalang’ penculikan itu bergabung di partai yang sama. Dalam berbagai kesempatan Pius ‘membela’ Prabowo, misalnya mengatakan bahwa tugas tentara adalah menjaga keutuhan negara, siapa-pun mungkin akan melakukan hal yang sama dilakukan Prabowo. Penghilangan orang secara paksa 1998/1999 bukan tindakan koboi petinggi militer saat itu, tetapi merupakan konsekuensi logis posisi politik TNI sebagai penopang utama rezim Soeharto.
Pius selalu mengedepankan upaya proses KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi), karena korban dan keluarga korban mendapat kompensasi, serta pelaku mendapat amnesti. KKR lebih baik ketimbang proses hukum yang akan membuka luka lama bangsa ini. Mengenai keinginan Pansus Penghilangan Orang secara Paksa 1998/1999 memanggil para jenderal, Pius menganggap DPR mengambil alih fungsi Komnas HAM sebagai institusi penyelidik. Sebagai lembaga politi sebaiknya DPR tinggal memutuskan perlu tidaknya dibentuk Pengadilan HAM.
Fenomena Stockhlom Syndrome mungkin bukan monopoli Pius dan aktivis korban penculikan lainnya yang bergabung dengan Partai Gerindra. Hubungan Megawati Soekarnoputri dan Sutiyoso, mantan Pangdam Jaya, pada kasus Penyerangan gedung, PDI 27 Juli 1996 juga mirip Stochlom Syndrome. Megawati dan PDI yang menjadi korban (meski bukan langsung Megawati tetapi massa PDI), kemudian mendukung mati-matian pencalonan Sutiyoso sebagai gubernur DKI Jakarta, demi mengamankan Jakarta mendukung Megawati dalam Pilpres 2004.
Dalam politik ada pameo tak ada musuh abadi dan kawan kekal, yang ada adalah kepentingan. Kasus Pius dan Prabowo dan mungkin Megawati dan Sutiyoso bisa kita baca melalui kacamata ini. Selain kepentingan politik yang dominan bermain dalam hubungan antara pelaku politik, tak dapat dimungkiri unsur Stockhlom Syndrome juga ada di situ. Ada kekaguman satu sama lain antara korban dan pelaku. Tetapi saat ini mereka berpikir ke depan, bersatu dalam satu partai, seraya melupakan masa lalu.
Stochlhom Syndrome atau bukan dalam hubungan antara mantan korban dan pelaku sesungguhnya tak begitu penting. Masalahnya adalah apakah mereka menolak impunity atau tidak. Apakah mereka percaya demokrasi yang anti-kekerasan atau tidak? Selain itu, apakah kemesraan mereka bermanfaat buat korban penculikan lainnya dan bangsa pada umumnya atau tidak? Jika kemesraan itu hanya demi kepentingan mereka sendiri, apalagi untuk menutupi atau menghapus kesalahan masa lalu, maka yang terjadi bukan saja Stockhlom Syndrome, juga sleeping with enemy!
(Tri Agus S Siswowiharjo, mantan aktivis Pijar dan Solidamor)
Kelompok pertama menganggap masuknya aktivis ke senayan tak akan mampu mengubah keadaan, dan dipastikan mereka akan larut dalam budaya Senayan, tak mementingkan rakyat melainkan partai dan kekuasaan. Kelompok kedua berdalih justru perjuangan paling tepat adalah di parlemen. “Senayan adalah perluasan medan perjuangan, bukan meninggalkan rakyat di jalan”, kata Dita Indah Sari. Yang menarik adalah ketika Hendrik Sirait menyatakan keberadaan Pius Lustrilanang di Partai Gerindra (kendaraan politik Prabowo Subianto) merupakan praktek Stockhlom Syndrome. Betulkah?
Para psikolog mengidentifikasikan Stockhlom Syndrome sebagai peristiwa di mana korban penculikan, penindasan, atau penganiayaan jatuh cinta kepada orang yang melakukan kekerasan terhadapnya. Menurut teori psikoanalisa, ini adalah salah satu bentuk upaya pembelaan diri sang korban. Sandera memberikan tanda-tanda kesetiaan kepada penyandera, tidak memedulikan bahaya (atau risiko) yang telah dialami sandera itu.
Sindrom ini dinamai berdasarkan kejadian perampokan Kreditbanken di Stockholm. Perampok bank menyandera karyawan bank dari 23 Agustus sampai 28 Agustus pada 1973. Dalam kasus ini, korban menjadi secara emosional menyayangi penyandera, bahkan membela mereka. Istilah sindrom Stockholm pertama kali dicetuskan kriminolog dan psikiater Nils Bejerot, yang membantu polisi saat perampokan. Ada lagi istilah Lima Syndrome. Sindrom Lima adalah kebalikan dari sindrom Stockholm, di mana justru penyandera yang memiliki ketertarikan emosional terhadap sandera-nya. Penyandera menjadi lebih simpatik, dan bahkan merasa membutuhkan sandera-nya.
Apakah hubungan Pius Lustrilanang dan Prabowo Subianto Stockhlom Syndrome? Pius diculik oleh Tim Mawar Kopassus. Ia cukup ‘beruntung’ karena dibebaskan dalam keadaan hidup. Setelah sempat berkampanye anti militerisme di Eropa, Pius kemudian kembali ke Indonesia. Mantan aktivis Aldera ini lalu bergabung dengan PDI-P, PDP dan pada akhirnya menjadi calon anggota DPR dari Partai Gerindra. Pertemuan dengan Prabowo pertama bukan di Partai Gerindra melainkan pada akhir 1999, di Kuala Lumpur. Saat itu mantan komandan Kopassus itu berkata kepada Pius, “Saya hanya prajurit. Tugas saya memenuhi perintah. Diantaranya adalah menculik kamu”.
Kini antara korban dan ‘dalang’ penculikan itu bergabung di partai yang sama. Dalam berbagai kesempatan Pius ‘membela’ Prabowo, misalnya mengatakan bahwa tugas tentara adalah menjaga keutuhan negara, siapa-pun mungkin akan melakukan hal yang sama dilakukan Prabowo. Penghilangan orang secara paksa 1998/1999 bukan tindakan koboi petinggi militer saat itu, tetapi merupakan konsekuensi logis posisi politik TNI sebagai penopang utama rezim Soeharto.
Pius selalu mengedepankan upaya proses KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi), karena korban dan keluarga korban mendapat kompensasi, serta pelaku mendapat amnesti. KKR lebih baik ketimbang proses hukum yang akan membuka luka lama bangsa ini. Mengenai keinginan Pansus Penghilangan Orang secara Paksa 1998/1999 memanggil para jenderal, Pius menganggap DPR mengambil alih fungsi Komnas HAM sebagai institusi penyelidik. Sebagai lembaga politi sebaiknya DPR tinggal memutuskan perlu tidaknya dibentuk Pengadilan HAM.
Fenomena Stockhlom Syndrome mungkin bukan monopoli Pius dan aktivis korban penculikan lainnya yang bergabung dengan Partai Gerindra. Hubungan Megawati Soekarnoputri dan Sutiyoso, mantan Pangdam Jaya, pada kasus Penyerangan gedung, PDI 27 Juli 1996 juga mirip Stochlom Syndrome. Megawati dan PDI yang menjadi korban (meski bukan langsung Megawati tetapi massa PDI), kemudian mendukung mati-matian pencalonan Sutiyoso sebagai gubernur DKI Jakarta, demi mengamankan Jakarta mendukung Megawati dalam Pilpres 2004.
Dalam politik ada pameo tak ada musuh abadi dan kawan kekal, yang ada adalah kepentingan. Kasus Pius dan Prabowo dan mungkin Megawati dan Sutiyoso bisa kita baca melalui kacamata ini. Selain kepentingan politik yang dominan bermain dalam hubungan antara pelaku politik, tak dapat dimungkiri unsur Stockhlom Syndrome juga ada di situ. Ada kekaguman satu sama lain antara korban dan pelaku. Tetapi saat ini mereka berpikir ke depan, bersatu dalam satu partai, seraya melupakan masa lalu.
Stochlhom Syndrome atau bukan dalam hubungan antara mantan korban dan pelaku sesungguhnya tak begitu penting. Masalahnya adalah apakah mereka menolak impunity atau tidak. Apakah mereka percaya demokrasi yang anti-kekerasan atau tidak? Selain itu, apakah kemesraan mereka bermanfaat buat korban penculikan lainnya dan bangsa pada umumnya atau tidak? Jika kemesraan itu hanya demi kepentingan mereka sendiri, apalagi untuk menutupi atau menghapus kesalahan masa lalu, maka yang terjadi bukan saja Stockhlom Syndrome, juga sleeping with enemy!
(Tri Agus S Siswowiharjo, mantan aktivis Pijar dan Solidamor)
Langganan:
Postingan (Atom)