Kasus Wartawan Menjadi Anggota DPR 2004-2009
Pendahuluan:
Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mendatang, ada sekitar 120 wartawan atau mantan wartawan di seluruh Indonesia ikut berkompetisi menjadi calon anggota legislatif. Ada wajah lama yang kembali mencalonkandiri atau dicalegkan parpol, seperti Cyprianus Aoer, Alfridel Djinu, Yoseph Umar Hadi, Panda Nababan dari PDI P, dan Effendy Chorie (PKB). Ada pula wajah-wajah baru yang mencoba menjadi politisi yang katanya sebagai panggilan seperti Helmi Fauzi dan Hamid Basyaib (PDI P), Bruno Kakawao (PKPI), Teguh Djuwarno (PAN), Mutia Hafild (Partai Golkar). Terdapat juga nama Manuel Kasiepo (PDI P). Dari kalangan kolumnis terdapat nama Zuhairi Misrawi (PDI P), Abdul Rohim Ghozali (PAN).
Munculnya wartawan sebagai caleg mendapat perhatian publik yang kurang lebih sama dengan kehadiran artis dan aktivis pada kontestasi Pemilu 2009. Wartawan, artis dan aktivis seolah dianggap sekelompok manusia yang kurang elok masuk dunia politik di parlemen yang penuh intrik. Wartawan seharusnya independen, artis sejatinya menghibur masyarakat, dan aktivis pantasnya berjuang secara imparsial dan tak mengharap kekuasaan. Itulah sorotan publik dengan kacamata yang kurang positif, yang pada intinya makhluk jenis wartawan, artis, dan aktivis tak pantas berada di lembaga legislatif.
Fenomena wartawan menjadi politikus bukanlah hal baru. Sejarah mencatat para jurnalis perintis menggunakan surat kabarnya sebagai bagian propaganda politik untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Pada masa kemerdekaan, kita melihat sejumlah surat kabar dan wartawan ikut dalam politik melawan rekolonialisasi sekutu. Pada periode 1950-1960-an, ada banyak wartawan menjadi anggota partai politik dan ada beberapa wartawan menjadi duta besar. BM Diah, misalnya, adalah salah satu dari sejumlah wartawan yang menjadi duta bangsa.
Semasa Orde Baru hingga Orde Reformasi kita mengenal sejumlah wartawan senior yang juga diangkat jadi duta besar, seperti Sabam Siagian (Australia), Djafar Assegaff (Vietnam), dan Susanto Pudjomartono (Rusia). Mantan Wakil Presiden Adam Malik dan mantan Menteri Penerangan dan Ketua DPR/MPR Harmoko juga adalah wartawan senior. Pada era reformasi, kian banyak wartawan masuk dunia politik dan beberapa menjadi anggota parlemen. Nama-nama seperti Hery Akhmadi, Cyprianus Aoer, Aco Manafe, Panda Nababan (PDI Perjuangan), Effendie Choirie (PKB), Djoko Susilo (PAN), Benny Harman (PKPI), Max Sopacoa (PD), Antoni Z Abidin, Bambang Sadono (Golkar) adalah sebagian dari sejumlah wartawan yang banting setir masuk dunia politik. Mereka adalah para anggota DPR RI periode 2004-2009.
Mengapa kehadiran wartawan di parlemen menarik perhatian? Hal itu tak lepas posisi wartawan sebagai bagian masyarakat media atau pers yang dalam negara demokrasi dianggap sebagai salah satu dari empat pilarnya. Pilar lain demokrasi adalah eksekutuf, yudikatif, dan legislatif. Menjadi wartawan sebagai penyampai berita dan pengritik pemerintah, sebenarnya sudah cukup, karena mereka telah menjalankan peran sebagai salah satu pilar demokrasi. Namun, toh tiap lima tahun sekali, sesuai periode pemilu di Indonesia, selalu ada migrasi profesi, dari wartawan ke poltitisi atau anggota parlemen.
Tilisan “Government and Media Relations” ini mengajukan sejumlah pertanyaan. Pertanyaan yang kemudian mengemuka, antara lain adalah 1) Mengapa sejumlah wartawan pindah profesi menjadi politikus di Senayan? 2) Apa kelebihan wartawan sehingga dianggap layak masuk ke dunia politik terutama menjadi anggota DPR? 3) Adakah peluang ‘menggiurkan’ atau ‘menantang’ dalam dunia politik yang membuat mereka pindah profesi? 4) Adakah kontribusi positif kepada demokrasi kita dari masuknya wartawan ke politik formal. 5) Bagaimana komunikasi politik wartawan anggota DPR dengan sesama anggota DPR, pemerintah, dan masyarakat? 6) Betulkah mereka telah memberikan perbedaan signifikan (dalam arti positif) dibandingkan profesi lain terhadap kinerja parlemen di masa lalu?
Agar pembahasan “Government and Media Relations” ini lebih fokus, maka yang kami dipilih sebagai obyek pengamatan, adalah para wartawan yang terjun menjadi anggota DPR periode 2004-2009. Mengapa periode 2004-2009? Karena anggota DPR periode ini tengah berjalan dan hampir selesai masa tugasnya, sehingga lebih mudah data yang akan kita peroleh untuk diteliti dan dianalisa.
2. Kerangka Teori:
Pers merupakan pilar keempat demokrasi (the fourth estate of democracy). Anggapan umum yang selama ini beredar di tengah-tengah masyarakat mengatakan demikian. Bahkan pernyataan "media merupakan kekuatan keempat setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif" telah menjadi aksioma politik, sebuah kebenaran cara berpikir politis yang tidak perlu dibantah lagi. Meski demikian, media atau pers tak hidup di ruang hampa. Ia berada dalam sebuah negara yang mempunyai sistem tertentu.
Dalam karyanya yang ditulis tiga dasa warsa lampau Fred Siebert dan rekan-rekan mengemukakan ada empat teori utama tentang hubungan antara pemerintah dan pers: 1) teori otoriter bahwa kekuasaan pemerintah harus dipusatkan pada satu orang atau elit, dan pers harus berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk memelihara ketertiban dan pemerintahan golongan elit; 2) teori libertarian yang berargumentasi bahwa pers harus berjalan dengan cara laissez faire, tidak dikekang, untuk menciptakan pluralisme titik pandang yang memberikan pengujian independen terhadap pemerintah dan peluang untuk menelaah semua opini secara bebas dan terbuka; 3) teori komunis yang melihat pers sebagai alat untuk menyampaikan kebijakan sosial untuk kepentingan ideologi dan tujuan yang diwakili oleh partai komunis; dan 4) teori pertanggungjawaban sosial yang menerima prinsip pers bebas, tetapi pers yang melaksanakan pelayanan masyarakat melalui kritik sosial dan pendidikan masyarakat yang bertanggungjawab, dengan anggapan bahwa jaminan atas pers bebas adalah jaminan kepada warga negara nasion, bukan yang pada dasarnya merupakan perlindungan atas hak pemilikan bagi pemilikan pers[1]
Teori pers libertarian paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia ini. Hal ini tak lepas dari kemenangan kapitalisme atas komunisme pascaperang dingin akhir 1980an. Sistem Pers Bebas menurut Walter Lippman[2] sesungguhnya merupakan ekspresi suatu kebenaran yang muncul dari cara “Free reporting” dan “Free discussion” dan sama sekali bukan dari apa yang disajikan secara sempurna dan instan yang diucapkan oleh seseorang. Pada sistem ini, pers layak disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Karena kebebasannya, pers mampu menjadi “wacthdog” pemerintah.
Kini, di tengah tekanan kapitalisasi dan iklim kebebasan, peran sentral pers dalam konteks demokrasi dan politik masih kokoh. Pers yang terletak pada dua entitas—organisasi pemberitaan (news organization) dan organisasi bisnis (business organization)—diharapkan mampu menyeimbangkan perannya sebagai pilar keempat demokrasi.
Menarik menyimak pemikiran yang diungkapkan oleh pakar media politik asal Amerika Serikat (AS), Timothy E Cook[3] (1998). Dia menyebut term media sebagai political actor (aktor politik) atau institusi politik. Cook berargumen bahwa media merupakan salah satu aktor atau institusi politik yang dapat menggunakan haknya sendiri secara independen, ”political actor / institution in its own right.” Selama ini ketika berbicara tentang media dan politik, kita kerap terjebak pada tataran komunikasi politik. Artinya, dalam perspektif ini media hanya dijadikan salah satu medium pasif bagi para spin doctor untuk menyampaikan pesan-pesan (kampanye) politik demi meraih kekuasaan.
Dalam sistem yang kini dianut Indonesia memungkinkan institusi media dan awak media menjadi sangat berperan dalam perubahan, dan karenanya sangat dikenal oleh masyarakat. Institusi media mungkin lebih dikenal publik daripada para wartawan yang tiap hari bekerja mengais berita. Interaksi antara partai politik dan media menjadikan dua pelaku demokrasi yang sama-sama mengklaim penyambung lidah masyarakat itu berinteraksi saling menghormati dan menguntungkan. Mereka saling mengagumi satu sama lain, meski terkadang saling mengritisi. Banyaknya anggota DPR yang terkuak skandalnya-- baik korupsi maupun perselingkuhan seks—tak lepas dari peran wartawan. Sebaliknya, banyak kejadian yang mungkin tak terungkap, meski bisa diungkap ke publik, karena para politisi mampu “membeli” atau “memelihara” wartawan. Simbiosis mutualisma atau perselingkuhan antara wartawan dan politisi ini tentu sangat [4]merugikan publik, baik sebagai konstituen partai politik, maupun pembaca media yang berhak untuk mendapatkan informasi.
Bill Kovach, kurator Nieman Foundation on Journalism, Universitas Harvard, salah satu guru wartawan yang paling dihormati dari Amerika Serikat, berpendapat mengenai makna informasi buat seorang politikus dan seorang wartawan. Kovach menutip Presiden Jimmy Carter (1975), "Ketika Anda memiliki kekuasaan, Anda menggunakan informasi untuk membuat orang mengikuti kepemimpinan Anda. Namun kalau Anda wartawan, Anda menggunakan informasi untuk membantu orang mengambil sikap mereka sendiri."[5]
Informasi yang sama dipakai untuk dua tujuan yang berbeda. Bahkan berlawanan. Inilah yang membuat Kovach mengambil sikap teguh untuk independen dari dunia politik maupun politisi. Kovach setia pada jurnalisme dan tak pernah mau menerima tawaran masuk ke dunia politik.
Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat. Sembilan elemen jurnalisme Kovack dan Tom Rosenstiel sangat terkenal di kalangan jurnalis. Delapan elemen lainnya adalah; kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran; intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi; praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita; jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan; jurnalisme harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat; jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting menarik dan relevan; jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional; dan praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka[6].
Loyalitas utama seorang wartawan adalah kepada warga masyarakat tempatnya berada. Wartawan bisa melayani warga dengan sebaik-baiknya apabila mereka bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput. Independen baik dari institusi pemerintah, bisnis, sosial maupun politik. Wartawan bahkan harus independen dari pemilik media tempatnya bekerja.
3. Pembahasan: Politisi Wartawan atau Wartawan Politisi?
Dalam buku “Wajah DPR dan DPD 2004-2009” terbitan PT. Kompas Media Nusantara (2006), terdapat sekitar 23 mantan waratawan[7]. Mereka berasal dari enam partai yaitu Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia. Di antara wartawan yang menjadi politisi Senayan 2004-2009, ada yang telah lama meninggalkan profesi wartawan, ada pula yang masih berstatus wartawan ketika migrasi menjadi politisi.
Wartawan termasuk warga negara biasa yang punya hak politik dan sering diharapkan ikut memimpin masyarakatnya. Mereka sah melakukannya. Cyprianus Aoer sangat memrihatinkan warga Flores karena kurang diperjuangkan di Jakarta. Tidakkah pilihan Aoer sah untuk terjun ke Parlemen?Bisa jadi alasan wartawan lainnya terjun ke parlemen berbeda. Ada yang seperti Aoer untuk memperjuangkan daerah asalnya, ada pula yang ingin memperjuangkan suatu isu tertentu misalnya pemberantasan korupsi atau transparansi pemerintahan.
Bagi Andreas Harsono[8], mantan wartawan The Jakarta Post yang kini mengelola Yayasan Pantau, suatu lembaga nirlaba untuk kemajuan jurnalisme, keterlibatan wartawan dalam politik memang kadang tak terhindarkan. Namun, sebaiknya diberlakukan sebagai one-way ticket. Artinya, seorang wartawan boleh menjadi politikus tetapi ia sebaiknya jangan kembali menjadi wartawan. Aoer boleh masuk parlemen tapi jangan kembali ke Suara Pembaruan. Djoko Susilo boleh menjadi politikus handan di Komisi I DPR namun jangan kembali ke Jawa Pos. Bila seorang wartawan masuk politik menjadi anggota DPR, ia akan mempunyai sikap yang berbeda terhadap informasi, sehingga lebih baik bila ia tak kembali ke media. Praktik bolak-balik ini akan menimbulkan citra kurang baik dari masyarakat tehadap media di Indonesia, apalagi pada masa demokratisasi sekarang ini, di mana warga butuh informasi yang bermutu untuk mengambil sikap terhadap berbagai isu penting di Indonesia.
Pandangan Andreas Harsono di atas memang sangat ideal. Namun bagi kalangan wartawan yang kini menduduki kursi empuk di Senayan, tentu tak semua menerima pendapat Andreas. Banyak alasan yang bisa dikemukakan mengapa seseorang melakukan ganti profesi dan kembali lagi ke pekerjaan semula. Ada yang memajukan alasan ingin melakukan perubahan dari dalam, sampai yang terus terang sekedar mencari jabatan. Wajar saja wartawan sebagai korps keempat pilar demokrasi tampil sebagai anggota legislatif karena peran atau profesi apa pun punya peran sosial kemasyarakatan. Yang penting wartawan sebagai anggota DPR tidak semata membawa ambisi politik, tetapi juga membawa tekad untuk membawa perubahan dan kesegaran baru[9].
Lain Andreas lain pula Arswendo Atmowiloto[10], wartawan sekaligus budayawan. Sebuah karya jurnalistik, kata Arswendo, baik tulisan maupun gambar pada derajat tertentu mampu menyodorkan informasi menjadi fakta yang menggugah publik. “Wartawan lebih powerful daripada anggota DPR,“ ujarnya. Wartawan, lanjut Arswendo, bisa menulis tentang banyak hal dan menggerakkan banyak orang untuk melihat realita sosial yang ada dan melakukan perubahan ke arah yang lebih positif. Hal ini yang belum mampu dilakukan bahkan oleh anggota DPR sekalipun. Karya-karya jurnalistik di Indonesia seharusnya dapat memotret realita sosial yang ada sehingga dapat memberikan dampak luas bagi masyarakat. Karya-karya jurnalistik yang lebih peka dan humanis akan membawa dampak sosial kepada masyarakat luas.
Sudah bagus berperan sebagai wartawan tetapi mengapa malah pindah profesi sebagai politisi? Adalah hak setiap warga untuk berpolitik dan berganti profesi. Apa kelebihan para jurnalis ini sehingga bisa masuk dunia politik? Betulkah kehadiran para mantan jurnalis ini memberi kontribusi positif bagi dunia politik partai saat ini? Ataukah ia akan ”larut dan hanyut” gelombang perpolitikan parlemen seperti banyak dikritik? Dunia kewartawanan dan politik dapat dikatakan merupakan dua hal yang jauh berbeda. Salah satu fungsi wartawan adalah melakukan kontrol terhadap pejabat publik dan politisi. Namun, kedua profesi yang bertolak belakang itu dapat dijalani dengan baik oleh orang yang tak mudah “larut dan hanyut”.
Dibandingkan profesi lain, wartawan dianggap memiliki kelebihan dalam melobi orang lain, terutama orang penting, termasuk pejabat publik. Sebagian wartawan juga dikenal pandai berargumentasi, lihai bersilat lidah, dan—ini tak kalah penting—kemudahan akses pada informasi dan media massa. Bagi sebagian wartawan itu, dunia politik adalah bagian kehidupan sehari-hari saat menjadi jurnalis. Bagi partai politik, mungkin wartawan dianggap bisa menjadi pasukan segar untuk bertarung tahun depan.
Apakah fenomena wartawan menjadi politikus tak lebih dari para pihak yang ingin masuk politik kekuasaan untuk kepentingan sendiri atau partainya? Ini mengingatkan kita pada Friedrich Nietzsche soal the will to power. Bahasa mudahnya, ini tak lebih dari sekadar ”’mencari perbaikan nasib” saja. Masyarakat punya harapan besar jika para mantan wartawan ini bisa menjalankan fungsi legislatif dengan lebih baik—fungsi pengawasan terhadap pemerintah, pembuatan UU, budgeting dan lain-lain.
Kinerja 23 orang wartawan di tengah 550 orang anggota DPR ternyata tak bagus-bagus amat. Bahkan Anthony Zeidra Abidin, anggota Komisi IX, saat ini menjadi pesakitan karena diduga terlibat dalam skandal aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp. 500 juta. Bagaimana bisa wartawan yang mengerti hukum dan menjunjung etika dalam tugasnya, justru hanyut dan tenggelam di dasar sungai bernama kejahatan kerah putih? Memang tak semua wartawan menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugasnya, misalnya menerima amplop[11]. Ada media yang melarang keras wartawannya menerima amplop seperti harian Kompas dan majalah / koran Tempo. Organisasi jurnalis yang mengharamkan amplop bahkan berkampanye untuk itu keluar lembaga sendiri adalah AJI (Aliansi Jurnalis Independen)[12]
.Selain Anthony Z Abidin yang jelas-jelas sudah mendekam di penjara dan kasusnya tengah disidangkan. Ada nama lain, yaitu Bambang Sadono, yang justru mengadu nasib ingin meraih kursi gubernur Jawa Tengah, namun gagal. Kita tak tahu pasti apa alasan Bambang Sadono ingin menjadi gubernur, meski alasan yang standar selalu mengatakan akan membangun Jawa Tengah lebih bagus lagi, seperti yang bisa kita saksikan dalam kampanye pilgub yang dimenangkan Bibit Waluyo-Rustriningsih yang diusung PDI P.
Apa hebat dan uniknya wartawan yang menjadi politisi kalau dia tidak bisa membawa warna baru dunia politik di Indonesia. Publik sebenarnya mencatat tingkah laku yang tak terpuji para anggota DPR. Contohnya Panda Nababan.. Apa yang dia bawa dari Sinar Harapan atau majalah Forum ke PDI P sebagai jurnalis yang pernah mendapat Hadiah Adinegoro untuk karya investigasinya? Menularkan semangat? Membagi ilmu? Menyuarakan pembaruan? Nothing. Ternyata, yang dilakukan dia malah ikut-ikutan membagi-bagikan travel check BII dalam kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, Miranda Goeltom.[13]
Jika ada yang mesti diapresiasi dari beberapa wartawan yang kini aktif di DPR, setidaknya ada dua. Mereka adalah Djoko Susilo, Ketua Komisi I, dan Effendy Choirei, anggota Komisi I. Joko dan Choirie sangat aktif mengritisi pemerintah terutama soal anggaran militer dan politik luar negeri. Joko juga menjadi Wakil Ketua ASEAN Inter-Parliamanetary Myanmar Caucus (AIPMC) yang berpusat di Kuala Lumpur. Kaukus ini sangat tegas dan kritis terhadap pemerintah Indonesia dan junta militer Burma (Myanmar) agar segera mengakhiri penindasan terhadap rakyat negara itu dan membebaskan tokoh pro demokrasi Aung San Suu Kyi.
Dalam berkomunikasi politik dengan kolega maupun mitra mereka, para wartawan anggota DPR tampaknya tak menunjukkan keberbedaan mereka dibanding yang bukan berasal dari kalangan wartawan. Logikanya, wartawan yang kaya data dan mudah mendapat akses ke mana pun, memiliki ‘peluru’ untuk ‘ditembakkan’ ke pemerintah sebagai mitra. Mereka semestinya mempunyai kelebihan di atas rata-rata anggota DPR lainnya. Kenyataannya, modalitas awal ini tak dimanfaatkan. Mereka tak ada bedanya dengan anggota DPR lainnya yang berasal dari partai politik. Tugas utama DPR yaitu pengawasan, budgeting, dan legislasi, seharusnya tak menyulitkan mereka yang berlatar belakang wartawan.
Wartawan atau politisi? Siapapun dari profesi apapun, ketika mereka sudah berada di DPR maka mereka adalah politisi. Sebagai politisi, logika profesi asal mereka acap kali ditinggalkan. Politisi biasanya bekerja dengan alasan atau cara kerja politik. Dalam politik keputusan lahir dari sebuah kompromi atau pemaksaan kehendak mayoritas. Contoh nyata, rekomendasi DPR[14] yang menyatakan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo adalah disebabkan bencana alam bukan kesalahan manusia. Dengan keputusan yang dipengaruhi Lapindo ini, jelas yang diuntungkan adalah Lapindo karena menimpakan penyelesaian masalah kepada pemerintah. DPR dalam hal ini tak menggunakan logika dan nurani – apalagi tersentuh oleh ribuan korban bencana ini. Mereka murni menjadi politisi yang kompromistis demi menyelamatkan Lapindo. Entah keuntungan apa yang didapat para anggota DPR.
Berbondong-bondongnya wartawan pindah ke Senayan tampaknya tak berdampaknya secara signifikan bagi demokratisasi di Indonesia. Pasalnya para wartawan yang bermigrasi dari jurnalis menjadi politisi itu, ketika di tempat yang baru tak memaksimalkan modalitas yang ada seperti kaya data, kritis, akses luas dan ahli lobi, umumnya mereka malah tenggelam atau hanyut dalam langgam irama anggota DPR lainnya. Hanya beberapa nama yang mampu menduduki Ketua Komisi atau Ketua Fraksi, selebihnya anggota biasa. Dari 23 orang mantan wartawan, juga hanya sedikit yang namanya sering muncul menghiasi media karena kritis terhadap pemerintah atau vokal terhadap suatu masalah bangsa. Karena dampak migrasi wartawan ke anggota dewan tak cukup signifikan bagi demokratisasi di Indonesia, maka sejujurnya kehadiran mereka tak lebih dan tak kurang seperti kehadiran para artis dan selebriti ke Senayan. Seperti kita tahu, artis yang ‘manggung’ di Senayan, mereka tak seatraktif di panggung yang sebenarnya, bahkan ada yang suaranya, seperti iklan, “nyaris tak terdengar!”
4. Kesimpulan
Munculnya fenomena “caleg impor” pada Pemilu 2009 bisa dipahami dalam dua hal. Pertama adalah miskinnya kader di partai-partai politik peserta pemilu tahun depan. Kedua memberikan kesempatan kepada kalangan berkualitas di luar partai untuk ikut menjalankan kettanegaraan. “Caleg impor” yang dimaksud adalah mereka dicalonkan sebagai anggota DPR namun buka dari kader partai. Mereka diandalkan keahliannya untuk mendulang suara atau pada saat mereka menjadi legislator. Masuk dalam kategori “caleg impor” antara lain artis atau selebriti, aktivis (mahasisw atau LSM), pakar atau akademisi, dan wartawan.
Mengingat pada periode 2004-2009 ada 23 orang wartawan yang bermigrasi menjadi ‘anggota dewan”. Dan kehadiran mereka tidaklah terlalu menonjol atau mempengruhi secara signifikan kiprah DPR dalam sistem demokrasi kita. Bahkan ada satu anggota DPR dari kalangan wartawan yang menjadi pesakitan karena kasus korupsi. Maka tak bisa dimungkiri, kehadiran mantan wartawan di DPR belum mampu mewarnai kinerja lembaga itu. Yang terjadi justru mereka hanyut dan terwarnai oleh warna DPR yang telah lama coreng-moreng. Wartawan, akademisi, aktivis, bahkan artis atau selebriti sebenarnya menjadi tak penting ketika mereka sudah menjadi anggota DPR. Bukan dari mana asal profesi sebelumnya, melainkan mampukah untuk tak tergoda oleh sistem yang korup.
Daftar Bahan Bacaan:
Komunikasi Politik, Dan Nimmo, cetakan keenam Juni 2005, PT Remaja Rosdakarya
Diktat kuliah “Government and Media Relations”, Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA
Governing with The News-The Media as a Political Institution, University of Chicago, 1998
Blog Andreas Harsono, “Wartawan atau Politikus?” 7 Juni 2004.
Sembilan Elemen Jurnalisme, Bill Kovack dan Tom Rosenstiel, edisi ketiga, Yayasan Pantau 2006
Wajah DPR dan DPD 2004-2009, PT. Kompas Media Nusantara (2006)
www.Inilah.com, 27 Maret 2008
Majalah Tempo, 2 Maret 2008
[1] Fred Siebert dalam Komunikasi Politik, Dan Nimmo, cetakan keenam Juni 2005, PT Remaja Rosdakarya, hal 259
[2] Diktat kuliah “Government and Media Relations”, Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA, hal 23
[3] Governing with The News-The Media as a Political Institution, University of Chicago, 1998
[5] Blog Andreas Harsono, “Wartawan atau Politikus?” 7 Juni 2004.
[6] Sembilan Elemen Jurnalisme, Bill Kovack dan Tom Rosenstiel, edisi ketiga, Yayasan Pantau 2006, hal 6
[7] . Antony Zeidra Abidin, Bambang Sadono, Irsyad Sudiro, Musfihin Dahlan, Slamet Effendy Yusuf, (Partai Golkar); Agung Sasongko, Cyprianus Aoer, Heri Achmadi, Jacobus Mayongpadang, Panda Nababan, Rendhi Lamadjido, Supomo SW, Widada Bujuwiryono, Yoseph Umarhadi (PDI P); Max Sopacoa (PD); Dedy Djamaluddin Malik, Djoko Susilo, Totok Daryanto (PAN); Effendy Choirie, Masduki Baidlowi (PKB); Herman Benediktus Kabur (PKPI)
[8] Blog Andreas Harsono, “Wartawan atau Politisi?”, 7 Juni 2004
[9] Blog Andreas Harsono, “Wartawan atau Politikus?” 7 Juni 2004.
[10] www.Inilah.com, 27 Maret 2008
[11] Biasanya berupa uang atau hadiah barang lainnya yang diberikan sebelum atau sesudah liputannya dimuat atau ditayangkan.
[12] AJI dideklarasikan di Sirnagalih, Bogor, pada 7 Agustus 1994 oleh 58 jurnalis se Indonesia, menyusul pembredelan majalah Tempo, editor dan tabloid Detik. AJI kini beranggotakan lebih dari 500 jurnalis.
[13] Tempo Interaktif, 23 Agustus 2008
[14] Rapat Paripurna DPR, 19 Februari 2008. DPR menyebutkan lumpur yang muncrat merupakan fenomena alam (Tempo, 2 Maret 2008)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

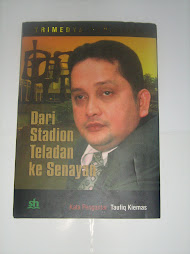













1 komentar:
INI BUKTINYA : PUTUSAN SESAT PERADILAN INDONESIA
Putusan PN. Jkt. Pst No. 551/Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan demi hukum atas Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
Sebaliknya, putusan PN Surakarta No. 13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan. Padahal di samping tidak memiliki Seritifikat Jaminan Fidusia, Pelaku Usaha (PT. Tunas Financindo Sarana) terindikasi melakukan suap di Polda Jateng.
Sungguh ajaib. Di zaman terbuka ini masih ada hakim yang berlagak 'bodoh', lalu seenaknya membodohi dan menyesatkan masyarakat, sambil berlindung dibawah 'dokumen dan rahasia negara'. Lihat saja statemen KAI bahwa hukum negara ini berdiri diatas pondasi suap. Sayangnya sebagian hakim negara ini sudah jauh terpuruk sesat dalam kebejatan moral suap. Quo vadis Hukum Indonesia?
David
Posting Komentar