MENGAPA JUNTA MILITER BURMA BISA BERTAHAN LAMA
DI PANGGUNG KEKUASAAN
Pendahuluan:
Dunia menyaksikan aksi yang dimotori para biksu dan aktivis Gerakan 88 pada September 2007 di Burma. Gerakan itu sendiri ditumpas dengan tindakan represif junta militer. Menurut pengakuan resmi junta militer, setidaknya 15 orang tewas, termasuk biksu dan seorang wartawan asal Jepang. Sementara para aktivis percaya, lebih dari 70 orang tewas. Ratusan bahkan ribuan biksu ditangkap dan ditahan di beberapa kampus dan biara. Apa yang terjadi di Burma membuat dunia marah. Aksi solidaritas dan dukungan terhadap perubahan politik di Burma digelar di kota-kota di seluruh dunia, dari Oslo sampai Solo, termasuk di Jakarta.
Pertumpahan darah dalam usaha mengakhiri otorianisme di negeri seribu pagoda kali ini bukanlah yang pertama. Sejak militer berkuasa pada 1962, setidaknya ada tiga pembantaian dan penangkapan besar-besaran terhadap aktivis pro demokrasi. Pertama, aksi up rising pada 8 Agustus 1988 (dikenal dengan aksi 8888) diduga militer menewaskan 3.000 aktivis mahasiswa. Kedua, usai partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi memenangkan secara mutlak pemilu 1990, junta menangkapi mahasiswa, aktivis, bahkan anggota parlemen terpilih. Ribuan aktivis dipenjara, banyak yang tewas dalam penjara yang kondisinya sangat buruk. Ketiga, aksi September 2007 yang dipelopori para biksu, menyusul kenaikan BBM sebesar 500 persen.
Mengapa reaksi dunia begitu keras terhadap punguasa Burma, sehingga aksi solidaritas merata di seluruh belahan dunia? Sebenarnya tak sulit menjawab dua pertanyaan di atas. Peristiwa demo September 2007 oleh para biksu dan aktivis ditonton langsung oleh jutaan pemirsa di berbagai penjuru dunia. Sedangkan peristiwa 1988 baru tersiar dalam bentuk foto dan tayangan video, dalam hitungan hari, minggu, bahkan bulan. Hampir mustahil untuk mengungkapkan kebenaran ketika mata-mata pemerintah berkeliaran di mana-mana. Pengawasan yang ketat terhadap media massa terus dilakukan junta militer. Wartawan, terutama wartawan asing, sulit untuk bisa mencari berita di negara paling tertutup di dunia itu.
Namun, berkat teknologi baru dan kerja keras aktivis, serta orang biasa yang peduli dan berani, semua ketertutupan itu bisa dibuka. Keberadaan internet, sambungan satelit, dan telepon kamera secara tidak langsung membantu perjuangan para aktivis untuk mengabarkan apa yang sedang terjadi di Burma saat ini. Menurut Dominic Faulder, wartawan Inggris yang bertugas di Bangkok, Thailand, situasi saat ini sangat berbeda. “Sekarang, seluruh warga bisa menjadi wartawan. Mereka melaporkan apa yang sedang terjadi dengan menggunakan telepon dan video yang tidak dapat dilakukan pada 1998," tambah Faulder.[1]
Berkat teknologi warga Kota Rangoon bisa menjadi wartawan. Mereka menjadi citizen journalist yang melaporkan secara langsung peristiwa yang terjadi di jalanan, termasuk foto dan video, kepada jaringan berita internasional, seperti CNN dan BBC. Laporan warga juga disebarluaskan oleh Democratic Voice of Burma (DVB) yang berada di Oslo, Norwegia. Jaringan berita yang dijalankan oleh para pelarian Burma itu kini menjadi sumber berita bagi jutaan warga Burma di luar negeri. Menurut Pemimpin Redaksi DVB Aye Chan Naing jaringan berita yang didirikan pada 1992 itu memperoleh foto dan gambar secara langsung tentang situasi di Burma. Gambar-gambar dramatis tentang bentrokan aparat dan pengunjuk rasa dikirim melalui email (surat elektronik) oleh warga dan aktivis di dalam negeri.
Vincent Brossel, Direktur Desk Asia organisasi Reporters Without Borders mengatakan junta militer Burma mulai mengendus cara-cara para aktivis dan berusaha mencegah aliran berita dari dalam negeri. Mereka memperlambat koneksi internet dan berusaha mematikan pelayanan telepon seluler. Junta militer Burma sudah tidak bisa lagi membendung arus informasi dari dalam negeri ke seluruh penjuru dunia. Sudah tidak ada lagi yang bisa ditutupi di era informasi seperti sekarang ini, termasuk perilaku otoriter penguasa.
Junta militer tak tinggal diam. Mereka lalu merusak kabel bawah air ini untuk menghentikan jaringan internet. Sebelum perusakan jaringan internet, junta Burma menuduh media asing menerbitkan "kebohongan" soal penumpasan aksi protes antijunta. "Media Barat tertentu dan media antipemerintah menyiarkan berita utama dan berita yang menyimpang guna mendorong protes massa," tulis media cetak pemerintah, New Light of Myanmar, di tajuknya.[2]
Selain jaringan internet dilumpuhkan, sejumlah media cetak juga diberangus. Langkah ini bagian dari upaya menghentikan seluruh informasi soal aksi protes di Burma tidak saja bagi dunia luar, tetapi juga di dalam negeri. Warung internet yang ada di Rangoon juga diberangus, kata Aung Zaw[3] dari majalah Irrawaddy, majalah kelompok perlawanan yang berbasis di Chiang Mai, Thailand. Militer menyerbu Myanmar Info-Tech yang banyak memasok foto dan video soal aksi protes, kata Aung Saw kepada wartawan Kompas di Bangkok. Pemberangusan ini diharapkan dapat menghentikan pengiriman foto dan video oleh wartawan, aktivis, dan bloger ke luar Burma kian berkurang atau berhenti total.
Tekanan juga dilakukan junta atas para penerbit surat kabar swasta. Media massa dipaksa tutup karena menolak menyiarkan propaganda militer. Sembilan surat kabar mingguan ditutup di Rangoon. Selain karena dipaksa militer, juga karena jaringan distribusi yang lumpuh akibat kerusuhan.
Kebrutalan militer Burma tak berhenti di situ. Selain merusak jaringan dan penyediaan warung internet, junta juga memerintahkan tentara untuk secara khusus memukul dan merampas siapa saja yang membawa kamera video atau telepon seluler (ponsel) berkamera di tengah aksi brutal tentara menghalau para pemrotes. Wartawan kantor berita APF Jepang, Kenji Nagai, yang tewas saat mengambil gambar aksi brutal junta, merupakan korban dari sikap militer memukul siapa saja yang membawa kamera video. Nagai tewas dengan luka tembak menembus bagian bawah dada. Dia sedang menenteng kamera video saat ditembak.
Biksu adalah pelopor aksi yang dipicu oleh kenaikan BBM 500 persen, namun ada sejumlah organisasi massa dan mahasiswa. Mereka tergabung dalam sebuah kelompok besar yang diberi nama Mahasiswa Generasi 88. Beberapa orang yang aktif dalam organisasi itu pernah terlibat dalam aksi unjuk rasa besar-besaran pada 1988. Organisasi yang bergabung dalam Mahasiswa Generasi 88 antara lain All Burma Students Democratic Front (ABSDF), Democratic People for a New Society (DPNS), National League for Democracy (Liberated Area) atau NLD-LA, National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB), Arakan Liberation Party (ALP), Federation of Trade Union-Burma (FTUB), dan Democratic Alliance of Burma (DAB).[4]
Biksu, aktivis Generasi 88 serta masyarakat lain yang menjadi citizen journalist telah menoreh sejarah bahwa perlawanan rakyat Burma itu masih ada. Sejak junta militer berkuasa pada 1962, perlawanan tak hanya sampai pada up rising 8 Agustus 1988 dan kemenangan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada 1990, tetapi pada September 2007 dunia menyaksikan masih ada benih-benih perlawanan terhadap rezim anti demokrasi di Burma.
Pada 8 Agustus 1988, para mahasiswa memimpin pemberontakan dan para biksu memberikan dukungan. Sekarang para biksu berada di depan, kita seakan berharap junta segera tumbang. Tampaknya terlalu banyak faktor yang dipertaruhkan dalam menghadapi junta militer. Dari Jakarta sampai New York, bahkan Beijing, hanya seruan yang bisa dilakukan agar para penguasa di sana menahan diri dan mencari sebuah penyelesaian politik untuk kembali melakukan rekonsiliasi nasional.
Berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia pada 1998, di mana gerakan mahasiswa dan rakyat didukung dunia internasional, mampu melengserkan Soeharto, tampaknya, kita bakal kecewa menunggu junta militer Burma jatuh. Harapan itu kian jauh manakala China, India bahkan Rusia masih setia berada di belakang junta. Selama masih ada negara kuat yang membela, dan di internal junta masih kukuh bersatu, demokrasi dan hak asasi manusia masih merupakan barang haram. Media massa dan peran wartawan warga memang mampu membuka mata dunia, namum itu belum cukup untuk menggulingkan junta dan mengubah Burma menjadi negara demokratis.
Permasalahan:
Makalah ini tak akan membahas mengenai peran media massa, melainkan tentang bagaimana junta militer mempertahankan kekuasaan mereka. Banyak topik yang bisa dibahas di sini, namun makalah ini harus fokus pada satu atau dua topik. Karena itu sengaja dipilih permasalahan; Mengapa junta militer bisa bertahan lama dan tetap berkuasa di Burma? Apa yang membedakan karakteristik junta militer Burma dengan rezim-rezim militer negara lainnya, terutama di Indonesia?
Pembahasan:
Penulisan makalah berdasarkan studi pustaka ini akan diawali dengan penjabaran tentang istilah, lalu dibahas beberapa teori yang mendukung, sekilas militer Burma, peluang dan tantangan demokratisasi, dan kesimpulan.
Sebelum masuk lebih jauh ke pembahasan ini ada baiknya dijelaskan beberapa istilah di bawah ini. Pertama, makalah ini menggunakan istilah Burma, bukan Myanmar untuk menyebut sebuah negara di Asia Tenggara yang kini sedang bergejolak. Pada mulanya nama resmi negeri ini adalah Union of Burma, yang merdeka dari Inggris pada 4 Januari 1948. Namun pada 1989, junta militer – tentu saja tanpa persetujuan rakyat – mengubah mana negeri ini menjadi Myanmar. Burma sendiri diambil dari nama suku bangsa mayoritas dalam bahasa Inggris, sementara Myanmar adalah pengucapan lokal dari istilah Burma. Selain nama negara, junta juga mengubah nama kota terbesar (dulu ibukota) Rangoon menjadi Yangon. Meski secara resmi di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Myanmar dan ASEAN dipakai, namun Amerika Serikat, Uni Eropa dan kelompok oposisi pro-demokrasi (termasuk Aung San Suu Kyi) dan aktivis solidaritas internasional tetap menggunakan istilah Burma.
Kedua, istilah Junta militer berasal dari bahasa Spanyol yang berarti dewan militer. Menurut Oxford Concise Dictionary of Politics[5] junta mengacu pada abad 16 saat komite konsultasi pemerintah yang dijabat oleh para jenderal. Pada era modern sekarang istilah ini mengacu kepada dewan militer yang menguasai sebuah negara menyusul kudeta, sebelum konstitusi baru berlaku. Di Amerika Latin biasanya diketuai oleh Panglima Angkatan Bersenjata yang membawahi ketiga angkatan yakni darat, laut dan udara. Begitu juga di Thailand dan Pakistan yang baru-baru ini mengambil kekuasaan.
Ketiga, statistik Burma[6]. Saat ini negeri seluas 676.578 kilometer persegi ini, berpenduduk 53 juta (Juli 2007), mayoritas beragama Budha (89%) ditambah Kristen (4%), Islam (4%) dan lainnya (3%). Pada 2005 PDB per Kapita 1.691 dolar Amerika Serikat. Etnik yang menghuni negeri ini mayoritas Burma (68%), disusul Shan (9%), Kayin (7%), Rakhine (4%), Mon (2%), selain itu masih ada Karen, Kareni, Kayah, dan Kachin. Berikut statistik pengungsi Burma[7]. Di Burma sendiri atau Internal Displaced Persons (IDP) sejumlah 500.000 orang. Di Thailand, 10 kamp pengungsi 154.000, di luar kamp pengungsi 200.000, dan pekerja imigran 2.000.000 orang. Di Bangladesh 200.000 orang (mayoritas etnis Rohingya yang beragama Islam), di India 60.000 orang dan Malaysia 20.000 orang. Selain itu beberapa negara yang menampung pekerja migran maupun aktivis Burma adalah Jepang, Australia, Amerika serikat dan Uni Eropa.
Kerangka Teori
Eric A. Nordlinger, menjelaskan fenomena campur tangan militer dalam politik. “Seorang pretorian coba menunjukkan kalau mereka adalah perwira yang bertanggung jawab dan berjiwa nasional. Rasa kebangsaan yang mementingkan orang banyak ini menyebabkan mereka tidak punya pilihan lain kecuali mempertahankan konstitusi dan negara dari pengaruh pemerintahan sipil yang sangat labil. Pihak militer menganggap bahwa mereka perlu menentukan apakah konstitusi telah diubah atau kepentingan negara telah terancam dan menentukan apakah campur tangan dibutuhkan atau tidak.” (Nordlimer, 1990:30)[8] Amos Perlmutter membagi militer pretorian menjadi dua yaitu, modern pretorian dan historical pretorian (Perlmutter, 1969:383)[9] Sementara Samuel Huntington mengungkap sebab terjunnya militer dalam politik dengan cara mengamati beberapa tindakan kudeta dalam suatu sistem politik (Sjamsuddin, etall, 1980) [10].
Militer pretorian adalah militer yang memekarkan peranannya dengan menyalahi etika profesionalisme militer. Yaitu dengan memainkan fungsi pertahanan keamanan sekaligus fungsi sosial politik. Tentu saja peranan militer ini berbeda dengan militer revolusioner yang memainkan fungsi hankam dan sosial politik atas dasar kebutuhan revolusi. Dan, jauh berbeda dengan militer profesional di barat yang memainkan peran hankam dengan bermodalkan keahlian, tanggung jawab dan karakter korporasi.
Sekilas Burma:
Burma dikuasai secara penuh oleh kolonial Inggris sejak 1885. Negara itu kemudian dijadikan sebagai sebuah provinsi dari India yang juga dijajah Inggris. Pada 1937, Inggris memisahkan Burma dari India. Selama Perang Dunia Kedua, Burma diduduki Jepang melawan tentara sekutu dan dibantu Burma Independence Army (BIA), Tentara Kemerdekaan Burma yang dilatih oleh tentara Jepang. Hal ini sama dengan yang dilakukan Jepang di Indonesia dengan mendirikan antara lain Peta.
Pada Maret 1945, beberapa tentara dari Burma Independence Army yang dipimpin Jenderal Aung San – ayah Aung San Suu Kyi – mengubah tentara ini menjadi pendukun Anti-Fascist People’s Freedom League (AFPFL), sebuah gerakan perlawanan anti Jepang. Kekuatan koalisi ini didukung oleh kelompok etnis termasuk Karen dan lainnya, pada akhirnya mampu merebut kemerdekaan dari Jepang.
Setelah bebas dari tentara Jepang, Aung San mewakili kelompok perlawanan dan pemerintah Inggris di Burma menyepakati perjanjian di mana Inggris memberi kemerdekaan kepada Burma yang secara efektif pada 4 Januari 1948. Namun sebelum Burma merdeka, Aung San dan enam orang pendiri negeri ini dibunuh pada 19 Juli 1947.[11] Konstitusi Burma merdeka menganut bikameral dengan perdana menteri yang memimpin kabinet. Wilayah yang mayoritas etnik seperti Shan, Kachin, Kayin, Kaya, dan Chin memiliki otonomi sendiri, meskipun tetap mengakui Union of Burma yang berpusat di Rangoon. Dari 1948 sampai 1962 pemerintahan sipil Burma dilakukan secara demokratis berdasarkan perwakilan rakyat. Meski demikian, konflik internal terus berlangsung berdasar alasan politik, sosial, dan etnik.
Pada 1962[12], pemerintahan sipil pimpinan Perdana Menteri U Nu dikudeta oleh kekuatan militer yang dipimpin Jenderal Ne Win. Ne Win kemudian memilih jalan sosialis “Burmees Way to Socialism” dan menjauhkan Burma dari dunia internasional. Selain itu, Ne Win juga mengembangkan pemerintahan militer yang anti-asing (A xenophobic military government). Ne Win membubarkan semua partai politik, lalu mendirikan Burma Sosialist Programme Party sebagai partai tunggal negeri itu. Selama Ne Win berkuasa perlawanan dari partai Komunis Burma dan kelompok-kelompok etnis terus berlangsung. Situasi ekonomi memburuk, meski pemerintah menasionalisasi beberapa perusaan asing dan swasta. Negara menuju kepada kebangkrutan. Menurut Ne Win The Bumese Way to socialism merupakan gabungan dari Budhism, Marxism, xenophobia, nasionalist dan megalomania. [13]
Pada 1987, ekonomi Burma ambruk. Nilai mata uang jatuh, banyak tabungan masyarakat di bank dihapus. Burma yang sebelumnya tingkat kesejahteraan di Asia berada di bawah Jepang, antara lain karena menjadi negara pengekspor beras terbesar sedunia, terjun bebas menjadi negara termiskin dan terkorup di dunia. Muncullah aksi-aksi demonstrasi menentang pemerintah yang gagal. Demostrasi terjadi di beberapa kota termasuk di Rangoon. Kali ini aktivis mahasiswa bersama biksu memimpin gerakan. Namun gerakan ini diakhiri dengan pembantaian pada 8 Agustus 1988, atau dikenal 8.8.88, di mana sekitar 3.000 aktivis tewas. Saat menyampaikan pengunduran dirinya, Ne Win mengatakan “Jika tentara diturunkan menghadapi pengunjuk rasa mereka akan menggunakan senjatanya. Diarahkan langsung membidik sasaran. Tentara tidak mengenal tradisi menembak ke udara” (1988)[14] Militer kemudian membentuk SLORC (State Law and Order Restoration Council). SLORC memerintah dengan darurat militer dan terus mematahkan gerakan anti-pemerintah militer. Pada tahun 1989, junta militer menggati nama negara menjadi Myanmar.
SLORC menyetujui pemilihan umum dengan multi partai. Maka pada 27 Mei 1990 digelar pemilu untuk memilih anggota parlemen. Liga Nasional untuk Demokrasi (the National League for Democracy, NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi memenangi 80 persen suara. Junta militer terkejut, partai yang didukungnya kalah telak. SLORC akhirnya tak mengakui hasil pemilu, bahkan menangkapi para anggota parlemen terpilih dan memenjarakan mereka, mengisolasi Aung San Suu Kyi dengan menahannya di rumah, serta memberangus semua gerakan pro-demokrasi baik di kampus maupun di luar kampus. Kebebasan pers, berkumpul dan berpendapat dibatasi.
Pada 1997 SLORC mengubah nama menjadi SPDC (State Peace and Development Council). SPDC terdiri dari 19 jenderal – termasuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara - dengan empat jenderal Angkatan Darat yang menjadi pengendali utama. Than Swee sejak 1992 menjadi jenderal senior yang merupakan pemimpin junta militer Burma. Sejak 1988 sampai 2007, kekuatan militer meningkat dari 200.000 personel menjadi 480.000 personel.
Arogansi junta militer Burma mirip dengan TNI ketika zaman Soeharto. Tatmadaw, sebutan angkatan bersenjata Burma, selalu mengklaim dirinya sebagai institusi yang paling berjasa dalam memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan. Menonjolkan prestasinya menyelamatkan negara, yang nyaris tercabik-cabik oleh pemberontakan Partai komunis Burma dan lebih dari 50 kelompok etnis sejak tahun 1950an. Di sisi lain sipil di nilai gagal, tak becus memimpin negara, karena konflik di tingkat elit politik. Ketika situasi genting, sipil menyerahkan tanggung jawab pada militer. Seperti dilakukan Perdana Menteri U Nu ketika menunjuk Kepala Staf Angkatan Bersenjata Ne Win sebagai pelaksana sementara PM (1958-1960).
Seperti Soeharto menggulingkan Soekarno berbekal Surat Perintah Sebelas Maret 1966, Ne Win juga melakukan hal yang sama terhadap U Nu (yang kebetulan sahabat Soekarno bersama PM Jawaharlal Nehru dari India, PM Chou En Lai dari China dan PM Gamal Abdul-Nasser dari Mesir sebagai tokoh Asia Afrika). Junta militer semakin kuat pada saat yang sama kekuatan sipil makin melemah. Inilah hal utama yang menyebabkan kekuatan sipil tak mampu mengimbangi tentara yang secara sistematis menguasai negara di segala aspek.
SPDC meskipun mulai membuka diri terhadap asing antara lain mengundang wisatawan dan investor namun hasilnya hanya untuk kepentingan militer semata. Dua lembaga bisnis yang berkuasa adalah Union of Myanmar Economic Holding (UMEH) dan the Myanman Economic Corporation (MEC). Bisnis yang seluruhnya dikuasai militer itu bergerak di bidang perhotelan, pariwisata, migas, batu mulia, perbankan, perkapalan, real estate dan kehutanan. Beberapa negara yang menjadi pendukung junta militer adalah China, India dan Rusia. Selain itu banyak perusahaan berinvestasi di sana terutama dari Thailand, Singapura, bahkan dari Perancis (Total).
Untuk menjelaskan betapa bisnis junta hanya untuk kepentingan militer, berikut data-data anggaran yang dikeluarkan untuk berbagai bidang. Anggaran militer berkisar antara 30-50%. Kesehatan 3%, pendidikan 8%. Pada 1990-1999 Burma menempati urutan lima terbawah dari 128 negara sebagai negara termiskin yang mengalokasikan 3% dari GDP untuk pendidikan, namun pada 1990/2000 menyusut menjadi 0,3% dari GDP untuk pendidikan. WHO menempatkan Burma sebagai negara terburuk kedua setelah Sierra Leone dari 191 negara. UNICEF mencatat 36% anak di bawah 5 tahun menderita kurang makan. HIV/AIDS menjadi ancaman serius, UNAIDS melaporkan rata-rata HIV inveksi di Burma adalah 1,3% bahkan survei lain mencatat 3,46% [15]. UNDP mencatat 75% populasi rakyat Burma hidup di bawah garis kemiskinan.Dengan estimasi GDP US$ 74,3 miliar dan GDP per kapita US$ 1.700. Pada 2003 GDP Burma lebih rendah dari Bangladesh. Laos, Thailand dan Malaysia. Inflasi pada tahun yang sama 49,7%, ini menempatkan diri menjadi negara kedua tertinggi inflasinya dari 176 negara.
Di samping masalah-masalah di atas, Burma juga negara yang dikecam dunia karena menggunakan anak di bawah umur untuk tentara, penerapan kerja paksa, pelegalan narkoba, penggunaan sistem perkosaan untuk etnis minoritas. Dengan kata lain sejak mencampakkan pemenang pemilu pada 1990, junta militer makin melanggengkan kekuasaannya dengan berbagai pelanggaran HAM. Termasuk di bidang pendidikan, yaitu menutup universitas yang dianggap pusat gerakan mahasiswa sejak 1988. Hanya universitas yang berbubungan langsung dengan junta militer yang masih dibuka.
Ada hubungan antara militer Burma dengan TNI era Soeharto. Pada tahun 1993-1995 hubungan antara Indonesia dan Burma sangat erat terutama militernya. Hubungan ini bisa digambarkan sebagai “Two nation with Common Identity”. Indonesia seperti sebagai big brother bagi Burma. Duta Besar RI di Rangoon pada 1996 A. Poerwanto Lenggono mengatakan junta militer akan mempelajari konstitusi RI UUD 1945, ideologi Pancasila dan Dwifungsi TNI[16].
Aung San Suu Kyi percaya bahwa tak ada pemerintah yang mampu mengadopsi gaya pemerintah lainnya seperti SLORC (SPDC) terhadap Orde Baru. “Indonesia has a national language which is spoken by most of its people but not here in Burma. We do not have a national language.” [17] Selain itu, kata Suu Kyi, Orde Baru dipenuhi oleh teknokrat, ekonom dan insinyur lulusan dari barat. “The SLORC (SPDC) does not trust intellectuals. Intellectuals who are trying to say something rational could be easily accused of planning a plot againt them. They could end up in jail.” [18] Indonesia mempunyai Widjojo Nitisastro dan Mafia Barkley-nya sementara Burma tak punya seorang pun. Karena itu tak heran jika pada suatu masa Orde Baru pernah sukses dengan “Widjojonomic” sementara Burma sebaliknya.
Meski sama-sama militer, yang menurut teori masuk dalam kategori pretorian, Orde Baru jauh lebih sukses, termasuk melahirkan kelas menengah baru, masyarakat sipil yang kritis dan media massa, meskipun pada akhirnya mereka justru bersama-sama menjatuhkan Orde Baru. Burma tak melahirkan kelas menengah yang mandiri, media massa dan masyarakat sipil yang kuat, karena telah diberangus sejak 1988 dan sengaja dimandulkan. Burma benar-benar menumpas dan mengharamkan kelas menengah tumbuh. Para aktivis pro-demokrasi Burma tak leluasa bergerak di dalam negeri, mereka lebih leluasa di luar negeri seperti di Thailand.
Perbedaan lain antara militer Burma dan Indonesia, TNI lebih terbuka dengan mengikuti undangan atau pelatihan yang dilakukan di negara barat misalnya Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan lainnnya. Dengan munculnya generasi baru perwira yang dipengaruhi cara pandang militer profesional, maka sedikit demi sedikit dapat mewarnai militer di Indonesia. Selain itu, TNI mempunyai kesempatan mengikuti latihan bersama militer dengan negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, Philipina, Australia, bahkan dengan Amerika Serikat. Juga, kesempatan TNI bergabung dengan Pasukan PBB melalui keikutsertaan Pasukan Garuda di berbagai wilayah konflik dunia seperti Timur Tengah, Balkan, hingga Kamboja. Pengalaman ini jelas mempengaruhi para perwira yang beruntung mengikuti pasukan PBB termasuk mantan perwira Susilo Bambang Yudhoyono yang kini Presiden RI.
Kesimpulan:
Letjen (Purn) Agus Widjojo, utusan Presiden RI sempat bertemu PM Thein Sein dan Menteri Tenaga Kerja Aung Kyi yang ditunjuk mewakili junta, ketika kunjungan dalam rangka menghadiri pemakaman mantan PM Soe Win Oktober 2007. Menurut Agus Widjojo, “Belum terlihat indikasi konkret untuk bergerak maju menuju proses demokratisasi.”[19] Kesimpulan Agus Widjojo mungkin didasari pengamatan bahwa junta masih solid, tak ada tanda-tanda konflik internal, seperti yang dibayangkan banyak pengamat, karena itu junta tetap kurang serius bekerja sama dengan PBB yang mendesak agar proses rekonsiliasi nasional dan demokratisasi harus dipercepat. Junta masih belum tamat selagi kekuatan pro-demokrasi bisa di atasi dengan cara apapun dan beberapa negara kunci – China, India dan Rusia – masih setia menopang roda ekonomi negri itu. Meski Amerika Serikat, Australia dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi, junta tetap kompak tak kolap.
Indonesia sebenarnya mampu, meski belum tentu mau, berperan lebih aktif untuk mempercepat demokratisasi di Burma. Pertama, kedekatan para pejabat RI dan Burma, terutama kalangan militer. Kedua, Indonesia mempunyai pengalaman menyelesaiakan konflik internal di Kamboja dan Philippina Selatan (Mindanau) yang berakhir suskses di meja perundingan. Namun karena Indonesia bersama ASEAN memiliki langkah yang sama; yaitu keras menekan namun tetap mengandeng Burma, sehingga junta militer secara internal ASEAN tetap aman dilindungi oleh kumpulan negara-negara yang lebih dari separuhnya merupakan negara tidak demokratis.
Indonesia dan Burma, keduanya memiliki militer yang pretorian. Militer Indonesia bisa dipaksa menjadi profesional karena kombinasi tekanan oposisi (mahasiswa dan aktivis) menduduki DPR RI, perpecahan di kalangan elit (mundurnya beberapa menteri penopang Orde Baru), dan dukungan masyarakat internasional. Burma hanya memiliki unsur yang terakhir. Perubahan harus berasal dari dalam negeri, unsur eksternal hanyalah pendukung perubahan itu.
Jakarta, 18 Nopember 2007
Daftar Pustaka:
Aung San Suu Kyi, Freedom from Fear, Penguin Books, 1995
Altsean Burma, From Consensus to Controversi, Bangkok 1997
DLA Piper Rudnick Gray Cary, Threat to The Peace, A Call for the UN Security Council to Act in Burma, 2005
Diktat Kuliah “Militer dan Politik di Indonesia”, disusun tim dosen Komunikasi Politik, Pascasarjana UI, 2007
Ian McLean, Oxford Concise Dictionary of Politics, Oxford University Press, 1996
Jan Donkers dan Minka Nijhuis, Burma Behind the Mask, Burma Centrum Netherland, 1996
Kompas (11 Oktober 2007, 29 September 2007, dan 29 Oktober 2007)
Suara Pembaruan (14 September 2007 dan 28 September 2007)
The Nation (18 Oktober 2007)
Tempo (18 Nopember 2007)
[1] Suara Pembaruan, 28 September 2007
[2] Kompas, 29 September 2007
[3] The Nation, 18 Oktober 2007, “Freedom flows in The Irrawaddy’ wawancara dengan Aung Zaw, editor dan pendiri majalah Irrawaddy
[4] Suara Pembaruan, 14 September 2007
[5] Oxford Concise Dictionary of Politcs, Oxford University Press, 1996, hal 261
[6] Kompas, 11 Oktober 2007
[7] Tempo, 18 November 2007, hal 133 dikutip dari Burma Human Right Yearbook 2006, Home of Common, Inggris 2007
[8] Diktat Mata Kuliah “Militer dan Politik di Indonesia”, Manajemen Komunikasi Politik UI, 2007
[9] ibid
[10] ibid
[11] Aung San Suu Kyi, Freedom from Fear, Penguin Book, 1995, hal 35
[12] Threat to The Peace, A Call for the UN Security Council to Act in Burma, DLA Piper Rudnick Gray Cary, 20 September 2005, hal 8
[13] Jan Donkers dan Minka Nijhuis, Burma Behind the Mask, Burma Centrum Netherland, 1996, hal 58
[14] Kompas, 29 Oktober 2007
[15] Threat to The Peace, A Call for the UN Security Council to Act in Burma, DLA Piper Rudnick Gray Cary, 20 September 2005, hal 25-26
[16] Andreas Harsono, dalam From Consensus to Controversi, Alternative Asean Network on Burma (Altsean), 1997, hal 57
[17] Ibid hal 59
[18] Ibid hal 59
[19] Tempo, 18 November 2007
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

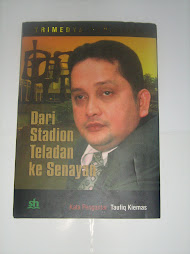













Tidak ada komentar:
Posting Komentar