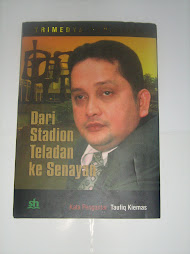Pada sebuah acara debat di SCTV sekitar sebulan lalu, berhadapan dua kelompok aktivis. Kelompok pertama, aktivis calon anggota DPR, Budiman Sujatmiko (PDI-P), Dita Indah Sari (PBR), dan Pius Lustrilanang (Partai Gerindra). Kelompok kedua, aktivis yang masih di ‘jalan’, Yeni Rosa Damayanti (aktivis perempuan), Hendrik Sirait (Ketua PBHI Jakarta), dan Sanggap (mantan aktivis Forkot).
Kelompok pertama menganggap masuknya aktivis ke senayan tak akan mampu mengubah keadaan, dan dipastikan mereka akan larut dalam budaya Senayan, tak mementingkan rakyat melainkan partai dan kekuasaan. Kelompok kedua berdalih justru perjuangan paling tepat adalah di parlemen. “Senayan adalah perluasan medan perjuangan, bukan meninggalkan rakyat di jalan”, kata Dita Indah Sari. Yang menarik adalah ketika Hendrik Sirait menyatakan keberadaan Pius Lustrilanang di Partai Gerindra (kendaraan politik Prabowo Subianto) merupakan praktek Stockhlom Syndrome. Betulkah?
Para psikolog mengidentifikasikan Stockhlom Syndrome sebagai peristiwa di mana korban penculikan, penindasan, atau penganiayaan jatuh cinta kepada orang yang melakukan kekerasan terhadapnya. Menurut teori psikoanalisa, ini adalah salah satu bentuk upaya pembelaan diri sang korban. Sandera memberikan tanda-tanda kesetiaan kepada penyandera, tidak memedulikan bahaya (atau risiko) yang telah dialami sandera itu.
Sindrom ini dinamai berdasarkan kejadian perampokan Kreditbanken di Stockholm. Perampok bank menyandera karyawan bank dari 23 Agustus sampai 28 Agustus pada 1973. Dalam kasus ini, korban menjadi secara emosional menyayangi penyandera, bahkan membela mereka. Istilah sindrom Stockholm pertama kali dicetuskan kriminolog dan psikiater Nils Bejerot, yang membantu polisi saat perampokan. Ada lagi istilah Lima Syndrome. Sindrom Lima adalah kebalikan dari sindrom Stockholm, di mana justru penyandera yang memiliki ketertarikan emosional terhadap sandera-nya. Penyandera menjadi lebih simpatik, dan bahkan merasa membutuhkan sandera-nya.
Apakah hubungan Pius Lustrilanang dan Prabowo Subianto Stockhlom Syndrome? Pius diculik oleh Tim Mawar Kopassus. Ia cukup ‘beruntung’ karena dibebaskan dalam keadaan hidup. Setelah sempat berkampanye anti militerisme di Eropa, Pius kemudian kembali ke Indonesia. Mantan aktivis Aldera ini lalu bergabung dengan PDI-P, PDP dan pada akhirnya menjadi calon anggota DPR dari Partai Gerindra. Pertemuan dengan Prabowo pertama bukan di Partai Gerindra melainkan pada akhir 1999, di Kuala Lumpur. Saat itu mantan komandan Kopassus itu berkata kepada Pius, “Saya hanya prajurit. Tugas saya memenuhi perintah. Diantaranya adalah menculik kamu”.
Kini antara korban dan ‘dalang’ penculikan itu bergabung di partai yang sama. Dalam berbagai kesempatan Pius ‘membela’ Prabowo, misalnya mengatakan bahwa tugas tentara adalah menjaga keutuhan negara, siapa-pun mungkin akan melakukan hal yang sama dilakukan Prabowo. Penghilangan orang secara paksa 1998/1999 bukan tindakan koboi petinggi militer saat itu, tetapi merupakan konsekuensi logis posisi politik TNI sebagai penopang utama rezim Soeharto.
Pius selalu mengedepankan upaya proses KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi), karena korban dan keluarga korban mendapat kompensasi, serta pelaku mendapat amnesti. KKR lebih baik ketimbang proses hukum yang akan membuka luka lama bangsa ini. Mengenai keinginan Pansus Penghilangan Orang secara Paksa 1998/1999 memanggil para jenderal, Pius menganggap DPR mengambil alih fungsi Komnas HAM sebagai institusi penyelidik. Sebagai lembaga politi sebaiknya DPR tinggal memutuskan perlu tidaknya dibentuk Pengadilan HAM.
Fenomena Stockhlom Syndrome mungkin bukan monopoli Pius dan aktivis korban penculikan lainnya yang bergabung dengan Partai Gerindra. Hubungan Megawati Soekarnoputri dan Sutiyoso, mantan Pangdam Jaya, pada kasus Penyerangan gedung, PDI 27 Juli 1996 juga mirip Stochlom Syndrome. Megawati dan PDI yang menjadi korban (meski bukan langsung Megawati tetapi massa PDI), kemudian mendukung mati-matian pencalonan Sutiyoso sebagai gubernur DKI Jakarta, demi mengamankan Jakarta mendukung Megawati dalam Pilpres 2004.
Dalam politik ada pameo tak ada musuh abadi dan kawan kekal, yang ada adalah kepentingan. Kasus Pius dan Prabowo dan mungkin Megawati dan Sutiyoso bisa kita baca melalui kacamata ini. Selain kepentingan politik yang dominan bermain dalam hubungan antara pelaku politik, tak dapat dimungkiri unsur Stockhlom Syndrome juga ada di situ. Ada kekaguman satu sama lain antara korban dan pelaku. Tetapi saat ini mereka berpikir ke depan, bersatu dalam satu partai, seraya melupakan masa lalu.
Stochlhom Syndrome atau bukan dalam hubungan antara mantan korban dan pelaku sesungguhnya tak begitu penting. Masalahnya adalah apakah mereka menolak impunity atau tidak. Apakah mereka percaya demokrasi yang anti-kekerasan atau tidak? Selain itu, apakah kemesraan mereka bermanfaat buat korban penculikan lainnya dan bangsa pada umumnya atau tidak? Jika kemesraan itu hanya demi kepentingan mereka sendiri, apalagi untuk menutupi atau menghapus kesalahan masa lalu, maka yang terjadi bukan saja Stockhlom Syndrome, juga sleeping with enemy!
(Tri Agus S Siswowiharjo, mantan aktivis Pijar dan Solidamor)
Senin, 03 November 2008
Langganan:
Komentar (Atom)