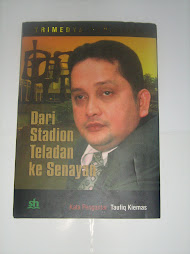Oleh: Tri Agus S. Siswowiharjo
Pendahuluan:
Salah satu pekerjaan rumah perjuangan reformasi sejak digulirkan pada tahun 1998 adalah mereposisi peran Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI diarahkan menjadi profesional sebagai kekuatan pertahanan, tak bermain di ranah politik dan berada di bawah supremasi sipil. Upaya-upaya membangun TNI profesional dan supremasi sipil ditempuh melalui semua cara di tingkat legislasi dan institusi. Meski demikian, arah yang sudah cukup bagus tersebut ternyata masih terkesan lamban.
Menjadikan TNI sebagai tentara profesional ternyata juga merupakan cita-cita Panglima Besar Jenderal Soedirman. Jenderal asal Purbalingga itu juga telah meletakkan dasar penting ke arah terwujudnya tentara profesional. Menjauhi ranah politik dengan kepatuhan kepada otoritas sipil pada masa itu dan pilihan hidup sederhana bersama rakyat yang selalu dibela, menjadikan perjuangannya dikenang hingga kini. Cita-cita Soedirman jika saat ini dijabarkan lebih lanjut berarti tentara tidak berpolitik, tidak berbisnis, taat kepada hukum lokal, nasional, dan internasional, patuh kepada otoritas sipil yang berdaulat, dan menghargai hak asasi manusia. Tentu itu semua memerlukan ongkos sosial politik yang tak kecil. Negara harus memenuhi dan melengkapi kebutuhan TNI, peralatan atau alutsistanya, ataupun kebutuhan untuk menjadi tentara yang terlatih dan terampil dalam tugas, terutama jaminan kesejahteraan prajuritnya.
Pada pidato peringatan Hari TNI 5 Oktober 2007 lalu, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar semua jalan baru bagi TNI
untuk terlibat dalam dunia politik ditiadakan. Keadaan ini, menurut Cornelis Lay, dosen Pascasarjana Universitas Gadjah Mada amat berbeda dengan masa Orde Baru, di mana perwira TNI memang diproyeksikan menjadi tentara bisnis atau politik. Kebijakan tentara politik membuat banyak perwira berpangkat letnan kolonel atau kolonel yang menjadi kepala daerah tingkat II. Sedangkan mantan Panglima Kodam (Pangdam) biasanya menjadi gubernur. Tentara bisnis terlihat dari banyaknya perwira TNI yang menjadi komisaris berbagai perusahaan.
Politik Orde Baru yang sentralistik dan otoritarian membuat kebijakan "tentara politik dan tentara bisnis" itu dapat dengan mudah dijalankan. Apalagi pada saat yang sama, aktivitas politik masyarakat sipil juga dibatasi dengan politik massa mengambang. Selanjutnya, kebijakan itu membuat para purnawirawan dianggap lebih siap memegang jabatan politik dibandingkan orang sipil.
Sekarang situasi sudah berubah. Pemilihan kepala daerah dan presiden yang sebelumnya dilakukan oleh DPRD atau MPR, sekarang dilaksanakan secara langsung. Kondisi ini membuat popularitas seorang calon di mata masyarakat menjadi amat penting bagi pemenang dalam pemilu atau pilkada. Saat yang sama, reformasi TNI membuat kesempatan para perwira saat ini untuk diperhatikan masyarakat menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan para seniornya ketika mereka menduduki jabatan penting di era Orde Baru. Sebab, reformasi TNI telah membatasi kiprah mereka dalam bidang sosial dan politik.
Kondisi ini menyulitkan para perwira TNI yang baru menyelesaikan tugasnya di kemiliteran pada era reformasi ketika akan terjun ke politik praktis. Sebab, mereka tidak memiliki banyak waktu untuk mengenalkan diri di masyarakat dan merintis karier serta keterampilan berpolitik praktis seperti yang dahulu dialami para seniornya. Namun, waktu akan membuat kiprah para purnawirawan yang sudah dikenal sejak saat-saat akhir Orde Baru itu semakin berkurang. Peran mereka pada 2009 diperkirakan tidak akan sekuat 2004 dan pada 2014 tidak akan sekuat 2009.
Betulkah demikian? Tentu belum bisa kita pastikan, karena ada beberapa sebab yang membuat prediksi di atas meleset. Pertama, politisi sipil ternyata belum terlalu siap berdemokrasi atau kurang percaya diri, sehingga masih saja berusaha menyeret TNI dalam ranah politik, meski hanya sekadar dukungan moril. Para purnawirawan jenderal justru menjadi incaran partai politik, tak peduli yang mengaku berideologi nasional atau Islam Kedua, sistem politik kita makin memungkinkan seseorang purnawirawan baik yang telah mempunyai partai politik sendiri atau pun belum, mempersiapkan diri menjadi presiden Republik Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono, Wiranto, Sutiyoso, dan Prabowo Subijanto adalah beberapa nama mantan jenderal TNI yang masuk bursa calon presiden pada 2009.
Permasalahan:
Makalah ini membahas mengenai citra dan popularitas mantan jenderal TNI. Banyak topik yang bisa dibahas di sini, namun makalah ini harus fokus pada satu topik yang berkaitan dengan pemasaran politik (political marketing). Karena itu sengaja dipilih permasalahan; Mengapa mantan purnawirawan militer masih mendapat tempat di hati para pemilih di Indonesia? Bagaimana peluang mantan jenderal TNI pada pemilihan presiden RI 2009? Masihkah citra dan popularitas mereka tetap stabil sampai menjelang hari pencoblosan?
Pembahasan:
Sebelum membahas lebih lanjut tentang citra dan peluang mantan TNI dalam pentas politik pemilu 2009, ada baiknya menengok sebentar sejarah kekaryaan TNI (dulu ABRI). Dari kilas balik ini kita akan mengetahui pengalaman kalangan TNI di pentas politik di masa lalu meski sistem politik waktu itu belum demokratis seperti sekarang ini.
Istilah kekaryaan pertama kali muncul sekitar 1958, ketika terjadi nasionalisasi perusahaan swasta Belanda dan Inggris. AH Nasution yang waktu itu sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, berinisiatif untuk mengambil tindakan strategis. Langkah ini dilakukan karena Partai Komunis Indonesia (PKI) mencoba merebut posisi-posisi kosong di perusahaan swasta tersebut. Beberapa perwira segera ditempatkan sebagai manajer menggantikan orang Belanda. Saat itu, lahirlah apa yang disebut dengan “Operasi Kekaryaan TNI”.
Dalam Seminar TNI AD III tahun 1972, muncul sebuah kesepakatan mengenai motivasi dan intensitas hadirnya peran kekaryaan TNI-ABRI dalam kehidupan politik di Indonesia. Forum sepakat untuk menegaskan peran kekaryaan ABRI terdorong untuk mengamankan dan menyelamatkan kemerdekaan, kedaulatan dan integritas RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Intensitas kekaryaan dipandang terkait dengan tingkat dan luasnya ancaman terhadap nilai-nilai nasional.
Pada masa menjelang dan setelah peristiwa G30S, ABRI mengambil inisiatif dengan menempatkan perwira TNI pada jabatan sipil yang kosong. Maka tak heran kalau jabatan gubernur, bupati, duta besar, menteri, dan jabatan-jabatan puncak di banyak departemen banyak diisi oleh perwira TNI. Sementara itu peran sipil hanya diposisikan sebagai pendukung. Dasar pemikiran kekaryaan adalah untuk memberikan peluang bagi personel TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil, tetapi dengan syarat apabila mereka dibutuhkan atau diminta oleh pihak nonmiliter dan mendapat persetujuan dari pimpinan TNI. Semua dilakukan menurut mekanisme yang berlaku pada setiap jabatan.
Pada masa Ord Baru, salah satu wujud fungsi TNI sebagai kekuatan sosial politik adalah dengan menugaskan prajurit dalam lembaga pemerintah di luar militer. Maka tidaklah aneh jika di setiap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif banyak ditemukan tentara yang menduduki jabatan penting. Menduduki suatu jabatan penting bukan otomatis sebagai pengambil keputusan. Karena, mereka masih harus selalu berkoordinasi dengan pimpinan TNI. Maka, bukan suatu yang aneh ketika soal perizinan, kontrak bisnis, dan keputusan tender pun harus melalui jalur birokrasi di tubuh TNI.
Jumlah personel TNI yang terjun dalam tugas kekaryaan mengalami pasang surut. Pada tahun 1968, 34 persen jabatan menteri dipegang TNI. Persentasi ini menyusut pada tahun 1995, yang tinggal 24 pesen. Untuk jabatan gubernur pada awal pemerintahan Orde Baru, 70 persen dijabat oleh militer, sedangkan pada 1995 masih menyisakan 40 persen. Begitu pula dengan jabatan duta besar, pada tahun 1968 sekitar 44 persen jabatan diisi oleh tentara, dan 27 tahun kemudian tinggal 17 persen.
Lain halnya dengan kedudukan militer di lembaga legislatif. Tahun 1960, 12 persen dari 283 anggota DPR Gotong Royong berasal dari lingkungan militer. Meski demikian pada tahun 1967 jumlah anggota TNI di legislatif mencapai 43 orang. Setahun kemudian jumlah anggota militer di parlemen mencapai 75 orang. Melalui UU Nomor 2 Tahun 1985 komposisi anggota TNI di DPR menjadi 100 orang.
Pada era reformasi, segala bentuk penyimpangan dalam tugas kekaryaan yang merupakan perwujudan dari salah satu dwifungsi ABRI mulai terkuak. Peran sosial politik yang dirasa dominan makin mendapat sorotan yang pada akhirnya adanya tuntutan untuk penghapusan dwifungsi ABRI. Salah satu reaksi dari TNI adalah dengan melikuidasi jabatan kepala sosial politik dan menggantinya menjadi kepala staf teritorial. Secara kuantitas, anggota TNI yang yang di legislatif dikurangi menjadi 38 personel.
Panglima TNI Wiranto mengeluarkan perintah kepada sekitar 4.000 perwira yang menduduki jabatan sipil untuk memilih pensiun dini dan tetap di jabatan sipilnya atau kembali ke Mabes TNI. Kemudian pada tahun 2000, 127 jenderal aktif mendadak dipensiunkan. Hal ini merupakan dampak dari penyempitan beberapa lembaga pemerintah yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada akhirnya, TNI harus rela bahwa untuk urusan politik praktis di parlemen diserahkan sepenuhnya kepada kalangan sipil. Meskipun harus tetap diakui bahwa peranan purnawirawan militer masih cukup kentara di lembaga legislatif ini.
Komposisi Militer di Jabatan Pemerintahan (dalam persen)
Jabatan 1968 1995 2002
Kabinet 34 24 20
Gubernur 70 40 28
Duta Besar 44 17 12
(Kompas, 16 Agustus 2004)
Komposisi Militer Aktif dan Purnawirawan dalam Jabatan Pemerintahan (dalam persen)
Tahun 1968 1995 2002 (purnawirawn
Kabinet 30 24 20
Gubernur 70 40 28
Duta Besar 44 17 12
(Kompas, 16 Agustus 2004)
Setelah sempat terpuruk akibat citra buruknya, kandidat presiden dengan latar belakang militer mulai dinantikan kehadirannya pada menjelang pemilu 2004. Cerminan ketegasan, dan kedisiplinan, tampaknya diperlukan untuk menghadirkan perubahan pada kondisi bangsa.
Pemilu legislatif 5 April 2004 rupanya bukan hanya menghasilkan perubahan peta kekuatan partai politik baru, tetapi juga mengubah persepsi sebagian besar publik perkotaan terhadap calon pemimpin mendatang. Sosok pemimpin yang berlatar belakang militer dan akademisi menjadi harapan yang ingin diwujudkan.
Jajak Pendapat 2004
Hasil jajak pendapat Kompas yang dilakukan pada 6-8 April 2004 di 32 ibu kota provinsi menunjukkan mantan tentara masih menjadi idola untuk memimpim negeri ini. Figur berlatar belakang militer ternyata dapat diterima sebagian besar responden (58,7%) untuk menjadi presiden yang dipilih pada tahun itu juga. Setelah mantan tentara, kepercayaan publik dipercayakan kepada tokoh-tokoh politik dari kalangan perguruan tinggi. Menyusul di belakang tentara dan akademisi antara lain agamawan, pengusaha, kemudian tokoh dari keluarga Soekarno dan Soeharto.
Munculnya sosok presiden dari kalangan berlatar belakang militer dan akademisi yang terekam dalam benak publik perkotaan pada 2004 tersebut sebenarnya tak berdiri sendiri. Kemunculan pemimpin yang diidamkan sedikit banyak dipengaruhi oleh munculnya dua partai fenomenal yaitu Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mampu bersaing di papan tengah dalam perolehan suara di pemilu legislatif 2004. Fenomena kedua partai tersebut jelas mencitrakan adanya perubahan politik disertai dengan pemimpin yang bersih dari korupsi, disiplin, tertib, dan tegas sehingga diharapkan mampu membereskan berbagai masalah bangsa.
Fenomena populernya tokoh berlatar belakan prajurit ternyata bertolak belakang dari kondisi saat reformasi mulai digulirkan pada 1998. Setelah mundurnya Presiden Soeharto, gerakan antimiliter begitu menguat membuat citra TNI benar-benar terpuruk di mata publik. Jajak pendapat Kompas pada 6 September 1998, sebanyak 62 persen responden menilai citra militer buruk. Buruknya citra militer ini pun akhirnya berdampak pada sikap ‘alergi’ publik terhadap tokoh-tokoh politik dari kalangan bersenjata ini. Tak heran apabila penolakan publik terhadap tokoh-tokoh dari militer untuk duduk di struktur lembaga tinggi negara pun cukup tinggi. Saat itu tak kurang 59 persen responden menolak presiden dari militer, baik masih aktif atau purnawirawan. Hanya 35 persen yang masih mengidolakan sosok militer layak memimpin Indonesia pada 1998. Pada jajak pendapat Kompas September 2003, peningkatan citra militer mulai terasa dengan 63 persen responden menilai citra TNI membaik dan berkontribusi pada preferensi masyarakat akan sosok pemimpin negeri ini.
Kecenderungan lemahnya kemampuan sipil mengelola republik ini, atau dengan kata lain kegagagalan Presiden B.J. Habibie, Abdurahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri, menjadikan posisi kekuatan militer kembali mendapatkan tempat. Naik turunnya citra TNI dan penerimaan mantan tentara tak lepas dari pandangan ketegasan dan kedisiplinan yang melekat pada tentara, ditambah lemahnya atau kegagalan beberapa tokoh sipil yang telah diberi kesempatan memimpin negeri ini.
Dalam pemilu presiden/wakil presiden mendatang, tertarik atau tidak tertarikkah Anda untuk memilih calon presiden yang berasal dari latar belakang:
Tertarik Tidak Tertarik Tidak Jawab
Militer 58,7 % 21,8 % 19,5 %
Akademisi 40,1 % 37,1 % 22,8 %
Agamawan 32,6 % 46,8 % 20,6 %
Pengusaha 20,7 % 57,3 % 22,0 %
Keturunan Soekarno 18,2 % 58,4 % 23,4 %
Keturunan Soeharto 13,1 % 63,5 % 23,4 %
N: 2.006 (Litbang Kompas)
Jakak Pendapat 2007
Dikotomi sipil dan militer dalam kepemimpinan nasional memang harus
diakhiri. Sebab, yang lebih dipentingkan adalah pemimpin yang kuat dan
bukan latar belakangnya. Namun, tetap sulit untuk meninggalkan TNI. Sejarah membuktikan, dari institusi tersebut banyak lahir calon pemimpin.
Masyarakat juga masih memberi perhatian besar terhadap calon pemimpin berlatar belakang TNI. Ini terlihat, misalnya, ketika Sutiyoso menyatakan diri akan maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2009, 1 Oktober 2007 lalu. Meski mantan Pangdam Jaya ini belum punya kendaraan politik untuk mewujudkan niatnya, beberapa media massa memberi tempat pada peristiwa itu dan ini merupakan pemasaran politik sendiri bagi Sutiyoso.
Besarnya perhatian terhadap kiprah para purnawirawan seiring dengan makin positifnya persepsi masyarakat terhadap kiprah TNI di panggung politik. Hal ini, antara lain, tercermin dalam jajak pendapat Kompas yang dimuat 8 Oktober 2007, di mana sebanyak 46,6 persen responden memilih tokoh militer sebagai presiden dan 43,5 persen lainnya memilih tokoh sipil.
Padahal, pada jajak pendapat Kompas tahun 1998, sebanyak 64,1 persen
responden menolak kemungkinan militer sebagai presiden. Bahkan, pada
jajak pendapat tahun 2000, hanya 5,3 persen responden yang menginginkan jabatan setingkat menteri diduduki purnawirawan TNI.
Jika kita dicermati, purnawirawan yang sekarang meramaikan wacana
panggung kepemimpinan nasional umumnya para senior Presiden Yudhoyono
yang merupakan alumnus Akabri 1973. Mereka juga sudah aktif atau
setidaknya namanya mulai disebut di panggung politik sejak Orde Baru.
Ini terlihat dari sosok Wiranto dan Sutiyoso yang adalah alumnus Akademi Militer Nasional 1968. Ada lagi sosok yang lebih muda, Prabowo Subijanto. Sedangkan perwira TNI yang memasuki masa purnawirawan atau menduduki
jabatan penting pada era reformasi, belum terlalu terdengar di panggung politik. Mereka, misalnya, mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto (alumnus Akabri 1971) atau mantan KSAD Ryamizard Ryacudu (alumnus Akabri 1974).
Pada saat yang sama, purnawirawan yang menduduki jabatan penting di
daerah, seperti gubernur, juga tampak berkurang. Dari enam provinsi di
Pulau Jawa, hanya Jawa Timur yang sekarang dipimpin purnawirawan,
yaitu Imam Utomo. Padahal, pada masa Orde Baru, dari lima provinsi
yang ada di Pulau Jawa, hanya Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh orang sipil, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono.
Jajak Pendapat Januari 2008
Bangsa Indonesia mudah sekali lupa. Selain itu juga dikenal sebagai masyarakat yang mudah memaafkan terhadap kesalahan masa lalu seseorang atau institusi. Itulah yang terjadi ketika era reformasi menginjak umur yang ke 10 tahun pada 2008.
Penunjukkan dan pengangkatan Mayjen TNI Achmad Tanribali Lamo menjadi Pejabat Sementara Gubernur Sulawesi Selatan pada awal 2008 bisa ditafsirkan beragam. Di satu sisi ada yang menganggap ini merupakan langkah mundur bagi proses demokrasi di Indonesia terutama reformasi di tubuh TNI. Hal ini sekaligus juga menggambarkan ketidakkonsistenan dalam memosisikan TNI. Dulu TNI diminta mundur dari wilayah politik, sekarang diundang masuk.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah militer memang merupakan pihak yang mampu menyelesaikan konflik, terutama yang mengarah pada kekerasan dan perusakan? Jika memang iya, apakah harus dengan menjabat sebagai kepala daerah dan bukan tetap pada jalur profesionalnya?
Terhadap pertanyaan ini, dalam jajak pendapat Kompas, publik di 10 kota yang dijajaki pendapatnya pada 23-24 Januari 2008 lalu menyatakan yakin dengan kemampuan pejabat dari mititer atau TNI yang ditunjuk akan dapat meredakan konflik. Hal ini disampaikan oleh lebih dari separuh responden (62,6 persen). Hanya sepertiga responden (33,5 persen) yang menyatakan tidak yakin militer mampu meredakan konflik. Responden yang berada di wilayah konflik saat ini pun memiliki sikap afirmatif yang sama. Sebanyak 82,5 persen responden di Kota Makassar setuju seandainya anggota militer ditempatkan sebagai pejabat sementara kepala daerah di wilayah konflik pilkada.
Namun sikap publik seperti di atas hanya respon sesaat terhadap situasi aktual yang dihadapi di daerah-daerah konflik pilkada. Gagasan ideal masyarakat terhadap reformasi TNI belumlah pupus. Tuntutan agar sipil lebih diutamakan dalam jabatan publik tetap menjadi keinginan yang tertanam kuat. Terbukti, hanya 37,7 persen responden yang menginginkan posisi jabatan kepala daerah dipegang oleh orang berlatar belakang militer. Sebaliknya, 53,6 persen lebih memilih pejabat dari kalangan sipil.
Mengapa publik saat ini kian permisif terhadap kehadiran TNI? Sikap afirmatif publik terhadap kehadiran militer tersebut bukan tanpa landasan. Setelah reformasi bergulir, citra TNI semakin baik dalam proses demokrasi di negeri ini. Hal ini disebabkan TNI melepaskan dwifungsi ABRI-nya dengan meninggalkan parlemen dan tidak lagi mengisi jabatan pimpinan di pemerintahan. Citra TNI di mata publik melonjak hampir dua kali lipat dari 31,5 persen pada tahun 1998 menjadi 57,8 persen pada tahun 2001.
Secara umum responden jajak pendapat Januari 2008 puas terhadap kinerja TNI (56,6 persen). Kepuasan tertinggi terutama terkait dengan kinerja TNI dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan RI (61,6 persen) dan peran mereka dalam membantu masyarakat di wilayah yang terkena bencana alam (70,2 persen).
Jika kinerja TNI dinilai memuaskan, sebaliknya kepuasan terhadap kinerja dan kepemimpinan dari kalangan sipil masih jauh dari harapan. Sejauh ini publik belum puas dengan kinerja kalangan sipil dalam berbagai hal, baik itu dalam mendukung reformasi dan demokrasi, meningkatkan perekonomian, menjamin keamanan dan ketertiban, meningkatkan pelayanan publik, ataupun menjalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kepuasan yang menurun terhadap kepemimpinan kalangan sipil berpotensi membuka peluang tumbuhnya harapan baru yang diletakkan ke pundak militer.
Hasil Jajak Pendapat Kompas
“Setuju atau tidak setujukah Anda terhadap langkah pemerintah menempatkan orang berlatar belakang TNI sebagai pejabat kepala daerah di wilayah konflik pilkada?” (dalam persen)
Kota Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu
Jakarta 69,0 27,9 3,1
Yogyakarta 56,4 38,6 5,1
Surabaya 71,6 23,6 4,8
Medan 65,6 31,3 3,1
Padang 87,5 8,3 4,2
Banjarmasin 50,0 42,9 7,1
Pontianak 66,7 29,2 4,1
Makassar 80,7 12,3 7,0
Manado 87,0 8,7 4,3
Jayapura 76,0 24,0 0
Kompas, 4 Februari 2008
“Sejauh ini, puas atau tidak puaskah Anda terhadap kinerja dan kepemimpinan dari kalangan sipil dalam beberapa hal berikut?” (dalam persen)
Pertanyaan Puas Tidak puas Tidak Tahu
Mendukung reformasi dan demokrasi 38,4 58,7 2,9
Meningkatkan perekonomian 20,7 78,6 0,7
Menjamin Keamanan dan Ketertiban 44,9 53,6 1,5
Meningkatkan Pelayanan Publik 45,8 52,7 1,5
Menjalankan Pemerintahan Bersih dari KKN 21,8 75,1 3,1
Kompas, 4 Februari 2008
Meskipun beberapa jajak pendapat menunjukkan bahwa citra TNI makin baik dan pemimpin dari kalangan tentara makin menjadi idola, namun ujicoba di beberapa pilkada tampaknya calon dari kalangan berlatar belakang militer masih belum banyak bersinar.
Di beberapa pilkada yang diikuti perwira TNI yang tidak aktif lagi ternyata tak menjamin kemenangan. Pilkada Jawa Barat dan Sumatera Utara misalnya, calon dari punawirawan dikalahkan popularitas artis dan kesolidan partai politik. Karena itu, para tetinggi TNI-AD gerah dan membuat pernyataan yang cukup keras. Jangan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah jika tidak siap.
"Perwira yang tidak aktif lagi tetap membawa nama baik TNI. Jika memang tidak siap maju ke pilkada, sebaiknya jangan mencalonkan diri karena akan memalukan korps TNI-AD," ujar Kepala Staf TNI-AD (Kasad) Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo.
Dalam pilkada yang berlangsung di beberapa daerah, terdapat sejumlah perwira TNI mencalonkan diri, dinyatakan kalah dan itu sangat memprihatinkan. Beberapa mantan perwira yang kalah di pilkada antara lain Agum Gumelar mantan Pangdam VII/Wirabuana, yang gagal dalam Pilkada Jawa Barat. Kasad sudah menginstruksikan kepada Staf Ahli di Mabes TNI-AD untuk mengkaji kekalahan mantan perwira di pilkada, di antaranya kekalahan Mayjen TNI (Purn) Tri Tamtomo, mantan Pangdam Bukit Barisan, yang kalah dalam Pilkada Sumatera Utara. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi pembelajaran bagi TNI-AD.
Citra Tentara Demokratis
Ketika para mantan tentara menjadi capres dan cawapres yaitu jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, Wiranto dan Agum Gumelar, nyaris mereka menghilangkan kesan sebagai purnawirawan alias mantan tentara. Sengaja mereka meminta pangkat ‘jenderal (purn)” tak dicantumkan dan sebaliknya memasang gelar H (haji), DR atau SH. Dalam berbagai pertemuan di depan rakyat maupun media berbagai olah tubuh yang berbau militer sengaja mereka simpan. Susilo Bambang Yudhoyono terkenal dengan gerak tangan saat bicara, tak pernah menunjuk seperti umumnya tentara dengan tongkat komandonya, dan sering mengutip atau menggunakan bahasa asing terutama Inggris.
Begitu juga Wiranto, dalam website resminya, ia tampak berpeci sedang menandatangani dokumen, duduk berwibawa, mengesankan sedang bertugas di kursi kepresidenan. Sementara itu Agum Gumelar yang berpasangan dengen Hamzah Haz penampilan fisiknya sportif dan santai. Baik Wiranto maupun Agum seolah menyembunyikan asal-usul mereka dari kalangan tentara yang selama ini dicap sebagai kaku, dan anti-demokrasi.
Kesuksesan pasangan SBY-JK memenangkan pemilihan presiden 2004 tentu tak lepas dari latar belakang sosok seorang tentara namun kemudian ditambah predikat intelektual, pemikir, teraniaya, ganteng dan lain-lain. Bersama SBY sekian jenderal ikut mendukung langkahnya menuju RI 1 pada 2004. Tercatat antara lain Moh Ma’ruf, Widodo AS, EE Mangindaan, Sudi Silalahi, Djali Yusuf, dan Suratto Siswodiharjo. Di kubu Wiranto juga ada taburan jenderal seperti Fahrul Razy, Suaidi Marasabessy, Tulus Sihombing, Sonny Sumarsono, dan Nurfaizy. Sementara di gerbong Agum Gumelar ada M. Yunus Yosfiah dan Abdul Wahab Mokodongan.
Menurut Ikrar Nusa Bhakti , pengamat politik dari LIPI, calon presiden dari kalangan militer yang melibatkan tim sukses dari kalangan militer lantaran kesamaan almamater dan sebagai keluarga besar TNI. Para capres berharap, terlibatan para purnawirawan mampu membawa gerbong besar mereka di masa lalu. Kelebihan yang diambil dari para prunawirawan adalah penguasaan mereka terhadap medan perpolitikan di Indonesia. Umumnya mereka sebelumnya aktif di bidang sosial politik ABRI. Sehingga mereka paham memperoleh informasi dan memanfaatkannya untuk propaganda.
Kelebihan yang hendak diperoleh dari para purnawirawan itu adalah efektifnya pelaksanaan tugas dengan sistem komando. Dari atas hingga bawah, terdapat satu bahasa yang dapat sama-sama dipahami untuk kemudian diterjemahkan pelaksanaannya di lapangan. Tidak ada kemungkinan perdebatan yang panjang mengenai hal yang tak perlu.
Kampanye Capres 2004
Mari sejenak kita menengok kampanye capres dan cawapres pada 2004 berlangsung pada 1 Juni – 1 Juli. Meskipun kurang ramai dari segi respon masyarakat, dibanding kampanye parpol Pemilu 2004, namun dari segi kreativitas dan inovasi, kampanye capres jauh lebih menarik. Dengan sistem pemilihan langsung, setiap capres musti berkampanye sebaik mungkin agar memperoleh suara sebanyak mungkin.
Kampanye parpol digerakkan semata-mata oleh pengurus partai dari pusat dan daerah yang sering disebut sebagai divisi pemenangan pemilu partai. Untuk kampanye capres, mesin penggeraknya adalah “tim sukses” yang khusus dibentuk dari lintas parpol dan individu sampai para profesional. Tim sukses inilah yang bertugas memoles capres agar rapi, cakap, ramah, murah senyum, dekat dengan rakyat. Tim sukses-lah yang mengatur jadwal kampanye, merumuskan strategi dan inovasi kampanye, menggalang dana, sampai mendekati media, termasuk dalam hal iklan media.
Persaingan iklan di media, berarti perang slogan. Agar menarik dan segera diidentifikasi khalayak, iklan disertai dengan slogan bombastis, ringkas, padat, dan yang paling penting, mudah diingat. Pasangan Wiranto-Solahuddin muncul dengan slogan “Bersatu Untuk Maju”. Melalui berbagai iklan, sosok militer dalam diri Wiranto hilang sama sekali. Wiranto berhasil disulap menjadi sipil yang murah senyum dan dekat dengan rakyat. Megawati memilih memamerkan kesuksesan pemerintahnya sebagai materi iklan. “Telah teruji, telah terbukti” begitu slogan Mega-Hasyim. Amien-Siswono dalam berbagai versi iklan mempopulerkan slogan “Jujur, cerdas, berani”. Pasangan ini bahkan memakai almarhum aktivis Munir sebagai bintang iklannya. Pasangan SBY-JK, yang keluar sebagai pemenang, mengusung slogan “Bersama Kita Bisa”. Dan terakhir, pasangan Hamzah-Agum yang berbagai iklannya tampak kaku, menyeru dengan slogan “Percaya untuk Maju”.
Kampanye negatif tak terhindarkan dalam pemilu capres 2004. Para capres dan cawapres harus siap merah telinga dan tahan emosi menghadapi isu-isu miring. Bagi lawan politik dan orang-orang yang tak suka, kelemahan kecil seorang capres/cawapres bisa digarap menjadi kampanye negatif untuk menggembosinya. Meskipun isu yang dihembuskan belum tentu benar, namun jika digarap secara teliti dan disebar terus menerus, akan bisa mempengaruhi kredibiltas dan popularitas capres. Perkembangan teknologi internet, milis, SMS, dan VCD/DVD menambah mudah aksi-aksi propaganda itu dilakukan.
SBY dan Wiranto adalah dua capres yang sering menjadi sasaran kampanye negatif terutama karena mereka berasal dari kalangan militer. Misalnya selebaran gelap muncul di Kabupaten Jember, isinya mangajak kaum muslim tak memilih SBY-JK. Alasannya mayoritas caleg Partai Demokrat, pendukung utama paangan ini, beragama non-Islam . Melalui internet juga beredar analisis tentang SBY dan perannya dalam konflik di Ambon.
Menjelang dan selama kampanye capres 2004, media tiba-tiba mendapat isu menarik tentang Wiranto dan keterlibatannya dalam Pam Swakarsa. Organisasi ini didirikan untuk membantu mengamankan Sidang Umum MPR 1998, khususnya untuk menghadapi demonstrasi mahasiswa. Media sangat antusias menangkap isu yang dilontarkan Mayor Jendral Kivlan Zen, yang diketahui sebagai mantan koordinator pembentukan Pam Swakarsa. Kivlan Zen yang kecewa karena uang pembentukan Pam Swakarsa belum dibayar Wiranto, saat itu Panglima TNI, ternyata dekat dengan Prabowo Subianto, rival Wiranto di Angkatan Darat dan konvensi Partai Golkar. Kiprah Kivlan Zen ini ditengarai sebagai kampanye negatif melalui media untuk menyudutkan Wiranto.
Usai persoalan Pam Swakarsa, Wiranto kembali ‘diserang’ dengan beredarnya VCD anti-Wiranto bersampul pagelaran Akademi Fantasi Indosiar (AFI). Dalam VCD itu mulanya delapan menit lagu Menuju Bintang yang dinyanyikan Fery, juara AFI. Setelah itu muncul gambar tragedi Semanggi dan Trisakti dan wajah Wiranto. Disusul kemudian teks berjalan dengan kalimat “Adili Jendral (purn) Wiranto. Tolak Capres dari militer” “Anda ingin peristiwa Semanggi dan Trisakti terulang kembali? Jika iya maka: pilih SBY atau Wiranto sebagai presiden kita. Dijamin Indonesia banjir darah.”
Kini, menjelang pemilu 2009, setidaknya ada empat mantan jenderal yang tampak punya keinginan kuat ingin maju menjadi presiden. Mereka adalah Susilo Bambang Yuudhoyono, kini masih menjadi presiden (incumbent), Wiranto (Partai Hati Nurani Rakyat / Hanura), Sutiyoso, dan Prabowo Subijanto (Partai Gerinda). Saat ini mereka rajin memopulerkan diri dengan berbagai cara. Presiden SBY melalui kebijakan-kebijakan merupakan kampanye tersendiri, meski kebijakan menaikkan harga BBM merupakan tindakan yang sangat tidak populer. Sementara Wiranto dengan rangkaian iklannya “menyerang” pemerintah melalui isu kemiskinan yang makin meningkat meski data yang digunakan berbeda dengan pemerintah. Isu kenaikan harga BBM juga dimanfaatkan Wiranto dengan membuat iklan tentang perlunya seorang pemimpin yang tak ingkar janji. Perdebatan mengenai etis atau tidak iklan politik Wiranto, menjadi iklan tersendiri bagi Wiranto.
Iklan politik Wiranto di sejumlah media massa membuat orang-orang dekat Presiden SBY meradang. Iklan tersebut dinilai tidak beretika. "Seharusnya semua harus dengan etika politik yang baik," ujar Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng. Andi cukup memaklumi manuver-manuver politik menjelang Pemilu 2009. Banyak tokoh yang mencari celah untuk melemahkan pihak tertentu demi mengambil keuntungan politik. Namun, Andi menyesalkan manuver yang ditempuh Wiranto tidak didasarkan kepada fakta yang benar. "Memancing di air keruh, ambisi pribadi. Dia itu seharusnya kalau mau bikin iklan harus ada kutipan dari mulut SBY," imbuhnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menuding iklan yang ditampilkan Wiranto itu dilakukan untuk menyerang dan menjatuhkan pemerintah menjelang Pemilu 2009. "Pemerintah, yang sulit itu kalau sudah menjelang pemilu. Ada dua indikatornya, kemiskinan dan pengangguran," imbuhnya. Dalam iklan Wiranto disebut bahwa saat ini banyak rakyat makan nasi aking akibat tak mampu membeli beras. Iklan tersebut menyoroti tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia dan terkesan menghakimi pemerintah SBY-JK yang dinilai tidak mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
Sejauh ini Sutiyoso telah memiliki website, menerbitkan beberapa buku, dan kini Bang Yos Center menempati markas di Jl. Proklamasi, depan bioskop Megaria Menteng, Jakarta Pusat. Di sana terpampang baliho besar sekali bergambar Sutiyoso dengan tulisan “Lebih Tegas dan Berani!” Berjuang demi rakyat! Sedangkan Prabowo melalui organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) membuat iklan dan memasangnya di beberapa stasiun TV tentang pesan dirinya agar bangsa Indonesia mencintai dan menggunakan produk pertanian dalam negeri. Minumlah susu buatan Indonesia. Makanlah buah-buahan dari petani kita. Agar Indonesia kembali menjadi macan Asia!
Ketiga penantang SBY tak satu pun yang membanggakan masa lalu mereka, melalui berbagai produk iklannya, tentang diri mereka saat bertugas sebagai militer. Mereka hanya berseru pemimpin harus tegas dan berani. Mereka menyadari saat bertugas menjadi seorang tentara atau jenderal, justeru citra tak sedap selalu melekat pada masa lalu mereka. Wiranto tak bisa dilepaskan dari peristiwa pelanggaran HAM berat di Timor Timur, dan peristiwa Semanggi I dan II. Prabowo sebagai rival Wiranto juga mempunya ‘cacat sejarah’ sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap penculikan beberapa aktivis pada akhir menjelang Soeharto jatuh. Sutiyoso juga mempunyai sejarah kelam di dunia militer, yaitu saat menjadi Pangdam Jaya, sebagai orang yang bertanggungjawab dalam peristiwa 27 Juli 1996.
Dalam survei parpol Kompas saat ditanya siapakah tokoh nasional yang Anda anggap paling layak untuk menjadi presiden mendatang?” Sebanyak 30 persen responden tak menjawab, sementara 20 persen menjawab tidak ada. Sutiyoso mendapat dukungan tertinggi yaitu 10 persen, jauh di atas SBY, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Hamengku Buwono X, masing-masing memperoleh dukungan 5 persen.
Kesimpulan:
Bangsa Indonesia selain cepat lupa, juga pemaaf. Karena itu kesalahan seberat apapun yang dilakukan institusi atau pejabat di masa lalu, mudah untuk dilupakan. Apalagi jika mereka yang mempunyai masa lalu kelam berusaha terus menerus mengubah citra tentang dirinya yang sudah berubah total. Dari seoranng jenderal menjadi seorang sipil yang demokratis atau intelektual.
Melalui berbagai survei di atas terbukti bahwa citra TNI dan para jenderal sempat terpuruk setelah era reformasi. Namun itu tak lama. Citra TNI dan kepemimpinan mantan tentara kembali menjadi harapan masyarakat manakala tiga orang presiden dari kalangan sipil terbukti tidak mampu memberikan perubahan atau kesejahteraan yang lebih baik. Karena itu pada pemilu 2004, kepemimpinan nasional kembali dipegang mantan tentara.
Bagaimana pemilu 2009. Tampaknya empat orang mantan jenderal akan meramaikan pentas pemilihan presiden. Mereka telah mempersiapkan diri dengan matang. Sebagai incumbent, Presiden SBY berkampanye melalui kebijakan-kebijakannya. Sedangkan ketiga mantan jendral penantang SBY, yang mengaku lebih tegas dan berani, saat ini terus menyerang melalui berbagai kegiatan dan iklan di media massa. Pemilu masih jauh namun genderang perang telah lama ditabuh.
Tentu saja yang menjadi juri dan menentukan siapa pemenangnya adalah para pemilih pada pemilu 2009 nanti. Siapa saja boleh beriklan, mencitrakan diri lebih indah dari aslinya, namun pemilih kadang mempunyai logikanya sendiri. Kemenangan SBY pada pemilu 2004 lalu tak terlepas dari popularitas SBY yang salah satunya dipicu oleh ‘serangan’ yang dilakukan pemerintahan Megawati.
Daftar Pustaka:
1. Media dan Pemilu 2004, Lukas Luwarso, Samsuri dan Tri Agus S Siswoiharjo, Seapa-Jakarta 2004.
2. Sang Kandidat, Analisa Psikologi Politik Lima Kandidat Presiden dan Wakil Presiden RI Pemilu 2004. Kompas Gramedia
3. Okezone, 23 Mei 2008
4. Okezone, 28 Mei 2008
5. Kompas, 12 April 2004
6. Kompas, 27 Mei 2004
7. Kompas, 1 Juli 2004
8. Kompas, 16 Agustus 2004
9. Kompas, 5 Oktober 2007
10. Kompas, 7 Nopember 2007
11. Kompas, 4 Februari 2008
12. Kompas, 19 april 2008
13. Koran Tempo, 11 Juni 2004
14. Suara Pembaruan, 26 April 2008
Senin, 30 Juni 2008
Langganan:
Komentar (Atom)