Oleh: Tri Agus S. Siswowiharjo*
Pada 10 Mei 2008, jika tak berubah karena badai yang menewaskan 20.000 orang lebih, junta militer Burma (Myanmar) mengadakan referendum. Rakyat akan menjawab ‘ya’ atau ‘tidak’ atas rancangan konstitusi baru. Menurut junta militer, referendum akan mengakhiri ketiadaan konstitusi sejak Myanmar dikuasai militer pada 1962.
Bagi rakyat Myanmar referendum kali ini mengingatkan pada pemilu 27 Mei 1990 yang dimenangi partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi tersebut sukses merebut 80 persen kursi di parlemen. Namun kemenangan itu dianulir junta militer. Akankah sejarah berulang pada Mei 2008?
Uni Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya terus melakukan berbagai tekanan. Dari embargo ekonomi, embargo senjata sampai menolak pemberian visa para pejabat militer. Puncak kecaman terjadi September 2007 saat junta militer meredam demonstrasi damai yang dipelopori para biksu. Meskipun negeri itu tertutup dan tak ada kebebasan pers namun berkat teknologi seperti telepon genggam dan internet, penindasan terhadap para biksu itu segera menduniai, dan masyarakat internasional mengecam junta militer.
Junta militer menyadari dunia tak sabar melihat demokratisasi di Myanmar. Karena itu mereka menjawab dengan referendum yang menjanjikan segera diakhiri pemerintahan militer, melalui pemilu ‘demokratis’ pada tahun 2010. Betulkah referendum merupakan pintu ke arah demokratisasi di Myanmar?
Jika referendum memenuhi syarat-syarat yang berlaku internasional, mungkin referendum penting bagi demokratisasi. Namun referendum kali ini sungguh mengandung tiga hal yang sangat tidak demokratis. Pertama, penyusunan draf konstitusi tak melibatkan kekuatan politik lain selain militer. Kedua, draf konstitusi hanya menguntungkan militer. Ketiga, pelaksanaan referendum tak mencerminkan asas transparansi dan kebebasan, karena tak dimungkinkan kampanye bagi yang tak menyetujui draf konstitusi baru tersebut. Pelaksana referendum, bukanlah lembaga independen, mereka bahkan menggunakan berbagai cara untuk menekan rakyat memilih ‘ya’, sementara beberapa aktivis yang mencoba memberi pendidikan politik agar rakyat kritis ditangkap aparat militer. Karena itu wajar banyak masyarakat berpendapat apa pun yang dipilih pasti akan keluar hasil ‘ya’.
Mari kita ambil contoh draf konstitusi setebal 194 halaman dan terdiri dari 457 pasal tersebut. Ada pasal pengganjal Suu Kyi untuk berpolitik karena ia menikah dengan warga asing. Larangan tak masuk akal itu menutup kemungkinan Suu Kyi menjadi presiden, bahkan menjadi anggota parlemen. Pasal lain, memberi jaminan bagi militer mendapatkan jatah 25 persen kursi di parlemen. Ini persis militer Indonesia era Orde Baru. Selain itu, militer juga bisa mengambilalih kekuasaan saat negara dalam keadaan darurat. Presiden dapat menyerahkan wewenangnya kepada pemimpin militer dalam waktu tak lebih dari setahun bila muncul keadaan darurat. Dinyatakan pula amandemen terhadap konstitusi hanya bisa dilakukan atas persetujuan 75 persen anggota parlemen. Amandemen tersebut hampir tak mungkin, dan tentunya harus mendapatkan dukungan dari militer.
Junta militer melarang pemantau internasional. Artinya kemungkinan terjadi kecurangan sangat besar. Kalau pun tak ada kecurangan namum rakyat memilih ‘tidak’, satu pertanyaan muncul: maukah junta militer menerima kekalahan? Bukankah pada pemilu 1990 mereka menolak kemenangan telak NLD.
Tampaknya dunia sekali lagi berharap banyak kepada citizen journalist, mereka pemakai telpon seluler dan internet. Mereka akan menjadi mata dan telinga masyarakat internasional yang mendambakan perubahan di Myanmar. Junta militer tentu tak ingin ‘kecolongan’ untuk kedua kali seperti September 2007. Pelarangan membawa telpon seluler di tempat pemungutan suara, mungkin diberlakukan.
Beberapa skenario pasca-referendum
Beberapa skenario mungkin terjadi. Pertama referendum lancar, mayoritas memilih ‘ya’. Artinya tetap tak ada perubahan. Kedua, referendum lancar, mayoritas memilih ‘tidak’. Jika junta militer menerima kekalahan, masih terbuka kemungkinan referendum berikutnya setelah perubahan draf konstitusi atau kemungkinan perundingan dengan oposisi yang lebih seimbang. Jika junta militer menolak kekalahan, berarti pengulangan sejarah 1990, dan demokrasi semakin jauh panggang dari api. Ketiga, referendum diboikot rakyat. Hanya minoritas yang menggunakan suaranya dan terjadi kekacauan di beberapa kota. Jika skenario ini yang terjadi, junta militer akan tetap mengamankan referendum sembari menumpas rakyat yang anti-referendum.
Ketiga skenario di atas memang tak ada yang menjadikan referendum legitimed, sebab sejak dari awal memang tak ada unsur demokrasi di dalamnya. Ini referendum dagelan penuh akal-akalan. Yang kita kehendaki semoga rakyat memilih ‘tidak’ dan tak ada jatuh korban. Rakyat sudah lelah menunggu perubahan. Demokrasi adalah salah satu syarat menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Adalah tanggungjawab masyarakat internasional jika kegagalan sekali lagi menimpa rakyat Myanmar. Para pemimpin dunia dan ASEAN jauh lebih bertanggungjawab karena mereka bisa melakukan upaya yang lebih kongkret untuk menyalamatkan rakyat Myanmar. Para pemimpin ASEAN termasuk Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah gagal mengajak para pemimpin junta militer ke arah demokrasi. Kini menjadi tugas rakyat Indonesia menyelamatkan rakyat Myanmar dari penindasan militer di abad modern ini. Gunakan kebebasanmu untuk membantu rakyat kami, begitu kata Suu Kyi kepada masyarakat internasional.
*} Penulis adalah aktivis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Burma (KMSuB) dan Alternative ASEAN Network on Burma (ALTSEAN-Burma), tinggal di Depok, Jawa Barat.
Tri Agus S Siswowiharjo:
Alamat email: politshirt@yahoo.com dan tass@kmsub.org
Website: www.kmsub.org
Blog: http://tassblog.blogspot.com/
Mobile phone: 0815 803 1815
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

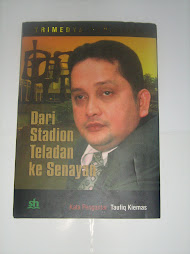













Tidak ada komentar:
Posting Komentar